oleh: Ev. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Nats: 1 Korintus 7:36-38
Para penafsir sepakat bahwa teks ini (terutama ay. 36) merupakan salah satu yang paling sulit untuk ditafsirkan dalam surat 1 Korintus. Hampir setiap bagian telah menjadi sumber perdebatan para penafsir. Siapakah yang dimaksud dengan “seorang” (tis) di ayat 36 yang telah bertindak tidak wajar terhadap gadisnya? Apakah ia adalah ayah dari gadis itu atau suami ‘spiritual’ atau tunangan laki-laki? Apakah yang dimaksud dengan “bertindak tidak wajar” (aschēmoneō)? Apakah kata Yunani hyperakmos ditujukan pada pihak perempuan dengan arti “usianya bertambah tua” (LAI:TB/KJV/NASB/NIV) atau pada pihak laki-laki dengan makna “nafsu yang kuat” (ESV/NLT/RSV)? Bagaimana kita menjelaskan frase “benar-benar merasa harus kawin”? Apakah yang menyebabkan mereka “harus” mengambil tindakan ini?
Persoalan menjadi lebih rumit karena semua pertanyaan di atas saling berkaitan. Secara khusus, pandangan seseorang terhadap pertanyaan pertama (identitas tis) sering kali mempengaruhi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan hal ini kita perlu membahas pertanyaan pertama lebih dahulu sebelum kita menyelidiki ayat 36-38 secara lebih mendetil. Seperti sudah disinggung secara sekilas di atas, para penafsir memberikan 3 usulan tentang identitas tis di ayat 36-37.
Pertama, tis adalah ayah dari “gadisnya” (ee parthenos autou). Menurut pandangan ini, beberapa ayah dalam jemaat telah terpengaruh oleh konsep asketisisme jemaat Korintus yang salah. Mereka kemudian menerapkan konsep itu pada anak-anak gadis mereka. Pemaksaan ini sangat dimungkinkan karena hukum pathr potestas, yaitu hukum Romawi yang memberikan kuasa mutlak kepada ayah atas anak-anak mereka. Begitu kuatnya hukum ini sampai-sampai seorang ayah dimungkinkan untuk menjual anaknya sebagai budak dan apabila anak itu sudah bebas dari perbudakan, ayah tersebut masih berhak lagi untuk menjualnya kembali. Dengan konsep asketisisme yang salah dan kuasa yang berlebihan sebagai seorang ayah, mereka sangat mungkin telah bertindak tidak wajar terhadap anak-anak gadis mereka. Para gadis itu dilarang untuk kawin, sehingga pada saat Paulus menulis surat 1 Korintus usia para gadis itu sudah melewati batas usia perkawinan. Argumen paling kuat untuk pandangan ini adalah pemakaian kata kerja “kawin” (gamizō) di ayat 38. Kata ini secara hurufiah berarti “menyerahkan dalam perkawinan”. Kata ini berbeda dengan kata “kawin” yang berkali-kali dipakai Paulus di pasal ini (7:9, 10, 28, 33, 34, 36, 39), yaitu gameō. Perbedaan ini dianggap disengaja oleh Paulus untuk menyatakan ide yang berbeda. Argumen lain yang dipakai adalah perbedaan dua kata tersebut di dalam ajaran Yesus. Matius 22:30//Markus 12:25//Lukas 12:27 Yesus mengatakan, “orang tidak kawin (gameō) dan tidak dikawinkan (gamizō)”.
Walaupun argumen di atas tampak sangat menarik, namun pandangan ini memiliki beberapa kelemahan yang mendasar. (1) Konteks 7:25-35 tidak membahas relasi antara ayah dan anak gadis mereka sama sekali. Jika ayat 36-38 berbicara tentang relasi ayah-anak perempuan, maka Paulus telah berpindah topik secara cepat dan tiba-tiba serta tanpa petunjuk yang jelas. Hal ini tentu saja menyulitkan para pembaca dan tampaknya terlalu dipaksakan; (2) Perintah Paulus “baiklah mereka kawin” di ayat 36 jelas merujuk pada “seseorang” (tis) dan “gadisnya” (ee parthenos autou). Jika ayat 36-38 adalah tentang relasi ayah-anak, maka Paulus pasti akan mengatakan, “biarlah ia [gadis itu] kawin” (NASB memilih terjemahan ini walaupun teks Yunani tidak mengarah ke sana); (3) Penggunaan istilah parthenos (lit. “gadis”) untuk anak-anak gadis tampak sangat janggal. Jika Paulus memaksudkan ee parthenos autou sebagai “anak gadisnya”, maka ia pasti akan memakai ungkapan thugatēr [anak perempuan] parthenos autou yang lebih umum (bdk. Kis. 21:9 “anak-anak dara”); (4) Perbedaan antara gameō dan gamizō terlalu dilebih-lebihkan. Dalam periode Yunani Koine perbedaan antara akhiran eō dan izō sudah tidak seketat pada zaman Yunani klasik. Makna kedua kata itu cenderung sinonim. Perbedaan yang ada hanyalah untuk variasi penulisan belaka; (5) pandangan ‘relasi ayah-anak’ tidak sesuai dengan arti kata aschēmoneō dan hyperakmos (lihat pembahasan selanjutnya).
Kedua, ayat 36-38 berbicara tentang suami-istri yang menganut asketisisme. Mereka sudah menikah kemudian mengikuti ajaran jemaat Korintus yang salah ini. Karena mereka tidak mau bercerai juga, maka mereka memutuskan untuk tetap hidup serumah tetapi relasi mereka bukan seperti suami-istri pada umumnya. Mereka tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Mereka hidup sebagai saudara-saudari dalam iman. Inilah yang dimaksud dengan ‘perkawinan spiritual’. Tidak ada argumen khusus yang mendukung pandangan ini, namun beberapa dugaan dianggap mendukung pandangan ini. Keadaan ‘perkawinan spiritual’ ini dipercaya sangat menguntungkan, baik secara ekonomis (mengurangi beban ekonomi karena menganut gaya hidup asketis) maupun secara spiritual (keduanya bisa saling mendukung dalam iman secara intensif). Jika salah satu di antara mereka mulai lemah dan menginginkan seks, maka pasangannya dapat membantu untuk menguasai keinginan itu.
Sama seperti pandangan ke-1, pandangan ini juga memiliki kelemahan yang mendasar. (1) tidak ada bukti bahwa model perkawinan seperti ini pernah ada dalam gereja mula-mula. Ketika pasangan suami-istri menganut asketisisme, yang mereka lakukan bukanlah tinggal serumah, karena itu justru akan menggoda mereka untuk melanggar gaya hidup itu. 1 Korintus 7:2-5 menyiratkan bahwa mereka lebih memilih untuk saling menjauhi; (2) jika ayat 36-37 berbicara tentang perkawinan spiritual, maka nasehat Paulus di ayat 38 (tidak menikah adalah lebih baik) akan berkontradiksi dengan nasehatnya di ayat 2-5. Saling menjauhi secara seksual antara suami-istri bukanlah tindakan yang baik (apalagi labih baik!), karena hal itu bisa menyebabkan perzinahan (7:2a, 5b). Lebih jauh, bagi Paulus relasi fisik (seksual) merupakan aspek integral dari sebuah pernikahan (7:3-4); (3) pandangan ‘perkawinan spiritual’ tidak sesuai dengan nasehat “baiklah mereka kawin” (ay. 36), karena mereka memang sudah kawin. Paulus seharusnya mengatakan, “baiklah mereka berhubungan seksual”; (4) penggunaan istilah parthenos (lit. “perawan”) untuk wanita yang sudah kawin tampaknya sangat janggal. Jika Paulus memaksudkan ‘perkawinan spiritual’ di ayat 36-38 maka ia pasti akan memakai kata gunh (lit. “perempuan [yang sudah menikah]”).
Ketiga, ayat 36-38 membicarakan tentang relasi pertunangan. Pandangan ini paling sesuai dengan konteks keseluruhan mulai 7:25. Pandangan ini juga cocok dengan makna kata aschmonew dan hyperakmos, seperti akan terlihat dalam pembahasan berikut ini.
Alasan untuk Menikah (ay. 36)
Di ayat 25-35 Paulus berkali-kali dan dalam berbagai cara telah menunjukkan bahwa tidak menikah merupakan pilihan yang terbaik. Ia bahkan akan mengulangi hal ini lagi di ayat 38. Bagaimanapun, kita tidak boleh menganggap bahwa Paulus sangat anti terhadap perkawinan. Dalam konteks ini nasehat Paulus tidak mengikat setiap orang, karena tiap-tiap memiliki karunia masing-masing, ada yang dipanggil untuk selibat dan ada pula yang ditentukan untuk menikah. Ayat 36 merupakan sebagian petunjuk bahwa seseorang tidak dipanggil untuk hidup membujang.
Alasan pertama adalah “bertindak tidak wajar” (aschēmoneō). Kata ini memiliki arti yang cukup luas dan bisa ditujukan pada tindakan apa saja yang bertentangan dengan tata nilai tertentu. Sama seperti lawan kata aschēmoneō – yaitu kata sifat euschēmenon di ayat 35 - yang bermakna luas (tindakan yang sopan atau layak), kata aschēmoneō juga bermakna luas. Berdasarkan pemunculan kata ini dalam tulisan-tulisan kuno yang mencapai lebih dari 80 kali, kata aschmonew sering kali berkaitan dengan masalah seksual apabila dipakai dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan. Ketidakwajaran atau ketidaksopanan yang dimaksud Paulus kemungkinan besar mencakup masalah seksual. Kita tidak perlu menafsirkan bahwa tindakan negatif ini sudah mengambil bentuk hubungan seks sebelum pernikahan. Jika keduanya sudah melakukan hal itu, maka Paulus pasti tidak akan memberikan toleransi apa pun. Ia akan memakai teguran yang sangat keras. Frase “jika seseorang menganggap (nomizō)” menyiratkan bahwa ketidaksopanan yang dimaksud belum separah melakukan hubungan seks. Jika laki-laki dan tunangannya sudah berhubungan seks mereka pasti langsung tahu bahwa hal itu adalah dosa yang sangat serius. Mereka tidak perlu “menganggap” (nomizō) hal itu sebagai sesuatu yang tidak wajar. Berdasarkan konsep Romawi tentang “rasa malu”, aschēmoneō di sini sangat mungkin merujuk pada tindakan atau pikiran tertentu yang dianggap seseorang kurang daripada yang ideal. Tindakan ini mungkin merujuk pada pikiran yang cenderung terfokus pada seks (pikiran kotor). Mereka yang memiliki kecenderungan ini akan lebih baik jika mereka memutuskan untuk menikah.
Alasan untuk menikah yang selanjutnya adalah hyperakmos. Ada dua persoalan yang sangat berkaitan sehubungan dengan kata ini: apakah arti dari kata ini dan kepada siapa ditujukan? Secara hurufiah kata ini berarti “melampaui batas” (hyperakmos terdiri dari kata hyper = melampaui dan akmē = titik tertinggi dari sesuatu), tetapi batas yang dimaksud tidak terlalu jelas. Sebagian memilih batas yang dimaksudkan adalah usia ideal untuk menikah, sedangkan yang lain memikirkan batas normal dari keinginan seksual. Pilihan pertama mengasumsikan bahwa hyperakmos ditujukan pada pihak laki-laki, sedangkan pilihan kedua mengaitkan hyperakmos dengan pihak perempuan. Walaupun kata sifat hyperakmos dapat berbentuk maskulin atau feminin, tetapi berdasarkan konteks yang ada kata ini sebaiknya dihubungkan dengan pihak laki-laki. Subjek utama di ayat 36 adalah laki-laki (ia menganggap diri telah bertindak tidak wajar; ia menghendaki perkawinan), karena itu tidak berlebihan jika subjek kata sifat hyperakmos adalah laki-laki juga. Jika ini diterima maka hyperakmos merujuk pada nafsu seksual seorang laki-laki yang melebihi batasan normal. Tafsiran seperti ini selaras dengan arti kata aschmonew yang juga berkaitan dengan tindakan negatif dalam konteks seksual. Di samping itu, penggunaan kata hyperakmos dalam literatur kuno mengarah pada kesimpulan yang sama. Kata ini sering dipadankan dengan kata katorgan yang merujuk pada keinginan yang kuat untuk berhubungan seks. Kata ini merupakan sinonim dari “terbakar” [secara seksual] di 7:9.
Alasan berikutnya adalah “benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin”. Dalam teks Yunani ungkapan yang dipakai secara hurufiah mengandung arti “dan karena itu terikat untuk terjadi” (kai aoutōs opheilei ginesthai). Apa yang mengikat laki-laki ini memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Dari konteks yang ada kita dapat menafsirkan bahwa ikatan tersebut berkaitan dengan nafsu seksual yang kuat dalam diri laki-laki itu. Laki-laki yang memiliki keinginan seksual yang sangat kuat sangat mungkin tidak dipanggil untuk hidup membujang. Ia justru akan jatuh dalam perzinahan.
Berdasarkan tiga alasan di atas Paulus menasehatkan bahwa laki-laki tersebut dan tuangannya sebaiknya menikah. Nasehat ini tidak boleh diartikan bahwa Paulus memiliki pandangan yang rendah terhadap perkawinan. Ia tidak mengajarkan bahwa pernikahan adalah solusi bagi godaan seksual yang berlebihan. Konsep seperti ini pasti tidak ada dalam pikiran Paulus. Solusi bagi setiap dosa adalah kuasa salib Kristus dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya (bdk. Rm. 8:5). Perselingkuhan membuktikan bahwa pernikahan bukanlah solusi bagi godaan seksual.
Nasehat Paulus di bagian akhir ayat 36 ini menunjukkan sikap Paulus yang realistis dan kepekaannya terhadap orang lain. Ia menyadari bahwa apa yang paling ideal belum tentu bisa dicapai oleh semua orang. Bagi mereka yang memiliki kelemahan di bidang seksual, keputusan untuk menikah jelas lebih bisa diterima daripada bersikeras hidup membujang. Daripada hangus karena hawa nafsu (7:9), lebih bijaksana bagi seseorang untuk menikah.
Alasan untuk Tidak Menikah (ay. 37)
Walaupun Paulus sudah memberikan alasan-alasan untuk menikah namun ia juga menjelaskan hal sebaliknya. Seseorang boleh saja memutuskan suatu ikatan pertunangan apabila ia memenuhi kriteria yang akan ia bahas di ayat 37. Kriteria ini disampaikan Paulus dalam gaya penulisan chiastic (ABBA). Sayangnya, struktur ini tidak terlalu terlihat dalam terjemahan LAI:TB, karena urutan yang ada sedikit diubah untuk mencapai terjemahan yang lebih mulus. Selain itu, beberapa ungkapan juga diterjemahkan secara agak bebas supaya lebih bisa dimengerti. Sesuai dengan kalimat Yunani yang dipakai, struktur ayat 37 dapat digambarkan sebagai berikut:
A orang yang yakin dalam hatinya
B tidak memiliki keharusan/kebutuhan
B’ memiliki otoritas atas keinginannya sendiri
A’ telah memutuskan hal ini dalam hatinya sendiri
Dari struktur yang ada terlihat bahwa kriteria untuk tidak menikah ada dua. Pertama, seseorang harus memiliki keteguhan hati. Kata “hati” (kardia) muncul dua kali di bagian awal dan akhir (LAI:TB tidak menerjemahkan kata kardia di bagian akhir) untuk merujuk pada bagian terdalam dalam diri manusia. Keputusan untuk menikah atau membujang sangat berhubungan dengan Allah, karena hal itu merupakan karunia yang khusus dari Dia (7:7). Allah bisa saja memberikan beberapa indikasi eksternal untuk memberitahu seseorang tentang panggilan hidup membujang, tetapi yang paling penting adalah pergumulan pribadi orang itu dengan Allah. Jikalau ia sudah meyakini panggilan tersebut, maka ia harus mengambil keputusan yang bulat daam hatinya.
Kedua, seseorang tidak terikat dengan nafsu seksual. Kata “kebutuhan” (anankē) merujuk pada kebutuhan [dalam konteks ini adalah kebutuhan seksual] yang besar sehingga menjadi sebuah paksaan bagi orang tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa mereka yang dipanggil untuk membujang tidak memiliki keinginan seksual sama sekali. Seperti orang-orang lain, mereka tetap memiliki nafsu seksual. Perbedaannya, mereka memiliki otoritas (exousia) atas keinginan itu, dan bukan sebaliknya. Penguasaan seperti ini bisa saja menjadi petunjuk bahwa seseorang mendapat karunia untuk tidak menikah. Penjelasan di atas memberikan pedoman yang bermanfaat bagi mereka yang menggumulkan masa depan (menikah atau membujang). Ada banyak alasan mengapa seseorang tidak menikah (Mat. 19:12). Allah bisa saja memakai beragam cara untuk menyadarkan seseorang pada panggilan hidup membujang. Salah satunya adalah melalui kemampuan rohani untuk mengontrol nafsu seksual. Yang paling penting adalah keyakinan dalam diri seseorang melalui pergumulan pribadi dengan Tuhan.
Konklusi (ay. 38)
Jika ada dua pilihan – yaitu menikah (ay. 36) atau tidak menikah (ay. 37) – manakah yang harus dipilih? Pilihan apa pun harus sesuai dengan karunia seseorang (7:7). Paulus tetap konsisten dengan sikapnya bahwa secara umum keputusan untuk tidak menikah tetap yang terbaik (7:7, 26, 38), walaupun keputusan untuk menikah juga tidak berdosa (7:9, 28, 38). Sikap ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sikap jemat Korintus. Baik Paulus dan jemaat Korintus sama-sama menganggap kehidupan membujang memiliki nilai lebih. Bedanya, Paulus tidak menilai pernikahan sebagai dosa, sedangkan jemaat Korintus memandang itu sebagai dosa.
Perbedaan lain teretak pada konsep tentang “baik”. Jemaat Korintus menganggap kata “baik” (kalōs) memiliki makna superioritas secara moralitas atau spiritual. Di sisi lain Paulus memandangnya secara praktis dan eskatologis. Secara praktis orang yang tidak menikah akan terhindar dari berbagai macam kesusahan (7:28b) dan kekuatiran (7:32a). Secara eskatologis orang yang tidak menikah akan lebih mampu mengarahkan hidupnya secara terfokus untuk menantikan kedatangan Kristus (7:26a, 29-34). Mereka tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal lain yang berpotensi ntuk mengganggu fokus hidup yang eskatologis tersebut. Sebaliknya, ia memiliki kesempatan untuk mengejar kekudusan dan melayani Tuhan seutuhnya (7:35). #
Sumber:
Mimbar GKRI Exodus, 13 September 2009
http://www.gkri-exodus.org/image-upload/1Korintus%2007%20ayat%2036-38.pdf





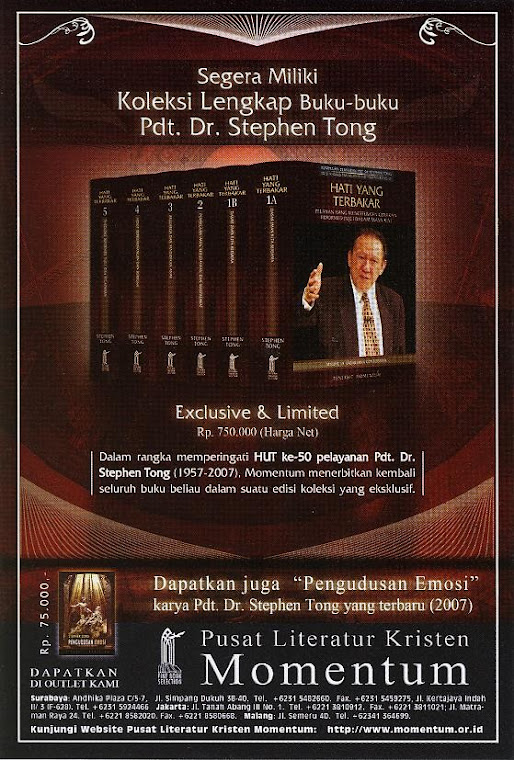
No comments:
Post a Comment