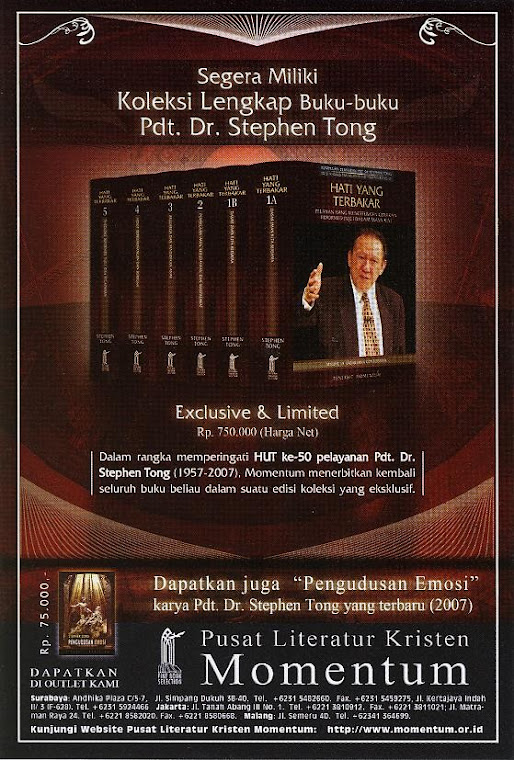oleh: Pdt. Daniel Lucas Lukito, D.Th.
PENDAHULUAN
Apa itu fundamentalisme? Istilah ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang digunakan secara luas di semua tempat di dunia. Di samping kekristenan, kita telah mendengar atau membaca adanya kelompok fundamentalisme di lingkungan agama Islam. Apabila dilihat dari sudut pandang dunia politik, gerakan fundamentalisme Islam lebih tepat merupakan gerakan partai Islam tertentu (yang umumnya radikal) yang telah diliput oleh media cetak atau elektronik secara universal.1 Istilah ini juga dipergunakan untuk menggambarkan gerakan-gerakan ekstrem agama Yahudi, Hindu, Sikh dan Buddha di seluruh dunia.2 Akan tetapi tulisan ini akan dibatasi pada penelitian tentang fundamentalisme Kristen saja.
Lalu apakah fundamentalisme itu? Bagaimana seharusnya fundamentalisme itu didefinisikan? Barangkali, karena kompleksitas fundamentalisme Kristen, sebagian orang lebih suka menghindari definisi-definisi yang sifatnya sederhana.3 Umumnya penulis-penulis Kristen lebih senang menunjukkan sejumlah ciri-ciri khas yang dapat diidentifikasikan dari fundamentalisme ketimbang mendefinisikannya. Karena itulah dalam artikel ini kita hanya akan melihat fundamentalisme baik dalam perspektif historis dan theologis serta melihat perkembangannya sampai saat ini. Setelah membahas sumbernya pada awal abad ini, fenomena fundamentalistik ini akan ditelusuri melalui karakteristik-karakteristiknya yang modern di antara gereja dan orangorang Kristen. Diharapkan melalui pemaparan tema ini kita akan lebih memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, memahami kemajemukan orang-orang percaya di Indonesia dan/atau Asia, serta mungkin menciptakan perubahan dan toleransi yang lebih besar lagi baik di kalangan fundamentalis dan nonfundamentalis.
LATAR BELAKANG FUNDAMENTALISME: LIBERALISME
Sebelum menganalisis fundamentalisme secara rinci, kita akan mempelajari latar belakang atau apa yang mempercepat munculnya fundamentalisme, yaitu munculnya Liberalisme. Liberalisme atau Modernisme timbul sebagai reaksi tidak langsung terhadap gerakan Pencerahan (yang dirumuskan terutama oleh Immanuel Kant) dalam theologi Jerman. Secara negatif boleh dikatakan bahwa Friedrich Schleiermacher (1768-1834), bapak Liberalisme, telah melancarkan suatu protes secara diam-diam terhadap rasionalisme Kant, dan pada saat yang bersamaan, secara positif dapat dikatakan, ia telah bertindak sebagai seorang “apologis” pada zamannya, dalam upayanya untuk mengharmoniskan butir-butir iman Kristen dengan perspektif Pencerahan.
Dalam usaha untuk memperkenalkan iman Kristen kepada dunia modern sekuler pada masanya, kita juga melihat bagaimana Schleiermacher (khususnya bisa dilihat melalui kritik K. Barth) telah mengorbankan hampir semua doktrin kepercayaan tradisional. Schleiermacher menafsirkan ulang dan juga mengubah iman Kristen dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tidak alkitabiah yang ditarik dari dunia sekuler. Sebagai contoh, Yesus Kristus yang telah berinkarnasi seperti yang disaksikan dalam Alkitab diinterpretasi ulang menjadi Yesus sebagai manusia biasa atau sebagai seseorang yang memiliki kesadaran ilahi yang tertinggi (the greatest God-consciousness),4 yakni seorang yang dipanggil dan dipakai Allah sedemikian rupa sebagai suatu contoh bagi semua orang Kristen. Demikian pula ajaran Kristen mengenai Allah Tritunggal telah diganti menjadi semacam tritunggal yang sifatnya fungsional. Ajaran tentang kerajaan Allah tidak lagi didasarkan atas kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi pada kehidupan spiritual dan etikal Yesus. Kesemuanya itu ia soroti melalui sudut pandang berdasarkan prinsip kesadaran diri yang religius (religious selfconsciousness), yaitu suatu prinsip yang memuat transformasi radikal terhadap seluruh doktrin ortodoks yang utama.
Bagi Schleiermacher, berdasarkan pengaruh filsafat Romantisisme yang sedemikian kuat pada pemikirannya, pokok persoalan theologi Kristen yang sesungguhnya bukanlah kebenaran-kebenaran tradisional yang didasarkan atas wahyu ilahi (khususnya kebenaran-kebenaran yang ditarik dari Alkitab secara induktif maupun deduktif), melainkan pengalaman religius manusia. Oleh karena itu, Alkitab dipandang bukan sebagai catatan yang diinspirasikan secara ilahi, melainkan hanya sebagai produk pengalaman religius bangsa Israel. Sebagai akibatnya, bagi kita yang hidup pada masa kini, Alkitab tidak memiliki otoritas yang sama seperti terhadap orang Ibrani. Alasannya, manusia modernlah yang harus menentukan seberapa jauh mereka boleh atau tidaknya mempercayai isi Alkitab. Singkatnya, dengan menggunakan pengalaman religius manusia yang subjektif, Schleiermacher menjadikan manusia modern sebagai penentu akhir dalam rangka menyingkirkan ajaran-ajaran ortodoks yang dianggap irasional.
Dalam konteks pembicaraan pasca-Schleiermacherian pun, Liberalisme justru terpengaruh dengan gagasan dari teori evolusi yang diadopsi sebagai kunci untuk menafsirkan proses religius dalam penulisan Alkitab. Selama periode ini, teori evolusi telah dianggap sebagai petunjuk untuk menguraikan adanya proses perubahan dalam beberapa aspek studi, seperti biologi, moralitas, kebudayaan, dan agama. Dengan menggunakan asumsi dari teori ini, theolog-theolog Liberal mempertahankan pendapat bahwa perkembangan agama orang Ibrani sesungguhnya merupakan suatu proses bertumbuhnya gagasan-gagasan primitif hingga mencapai tahap pemurnian akhir, yakni iman Kristen. Mereka percaya bahwa para nabi-lah, dan bukan Musa, yang pertama-tama menguraikan secara terperinci ide tentang monoteisme. Oleh karena itu, setiap gagasan primitif seperti murka Allah, korban pendamaian, dan penebusan supranatural harus dihapuskan dari dalam daftar agama Yesus dari Nazaret.
Tokoh kunci Liberalisme yang lain, Adolf von Harnack (1851-1930), mengakui bahwa ada terlalu banyak aspek pemikiran primitif yang telah diakomodasi ke dalam Yudaisme atau Perjanjian Lama. Hal yang sama menurutnya dapat kita amati dalam Perjanjian Baru di mana pemikiran Hellenis telah terserap ke dalam pemikiran para penulis Kristen mula-mula (khususnya dalam surat-surat Paulus).5 Tidak mengherankan ketika Harnack menulis karyanya yang terkenal, What is Christianity?, ia mengklasifikasikan dan meringkaskan elemen-elemen kekristenan yang esensial ke dalam tiga hal utama: kebapaan Allah yang universal, persaudaraan manusia dan ketidakterbatasan nilai jiwa manusia (the universal fatherhood of God, the brotherhood of man, and the infinite worth of human soul).6 Ide utama di balik penulisan karya ini adalah sebuah usaha untuk merekonstruksi iman Kristen dengan mengeluarkan seluruh kisah penebusan yang ditemukan dalam Alkitab. Dengan menggunakan gaya pemikiran evolusioner, Harnack telah berhasil menafsir ulang iman Kristen yang ditransformasikan menjadi semacam humanisme yang modern.
Dalam derajat yang sedikit berbeda, Albrecht Ritschl (1822-1889) juga berpendapat bahwa iman Kristen harus dibebaskan dari segala spekulasi metafisis dan sebaiknya dilihat sebagai sebuah kepercayaan yang berusaha mengungkapkan penilaian makna, khususnya berkaitan dengan makna karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena itulah, dalam upaya memberikan penjelasan tentang ajaran-ajaran pokok dalam kekristenan, Ritschl juga menyingkirkan setiap aspek pengajaran ortodoks, seperti dosa asal, pendamaian, dan penghakiman kekal. Ia membuang semua pengajaran tentang kekudusan dan murka Allah serta menyamakan keberadaan Allah dengan sekadar ide tentang kasih, karena baginya kerajaan Allah hanyalah sebuah wilayah yang mengungkapkan kebenaran dan nilai-nilai etis.7
Secara ringkas kita dapat menyimpulkan bahwa karena terjadinya perubahan-perubahan terhadap doktrin-doktrin dasar kepercayaan tradisional yang dibuat oleh para theolog Liberal di atas, kaum fundamentalis pada awal abad 20 (khususnya di Amerika Serikat) mulai menyadari bahwa mereka tengah diperhadapkan pada penyimpangan pengajaran yang membahayakan. Tuduhan utama yang diajukan kaum fundamentalis adalah bahwa theolog Liberal telah memalsukan isi Alkitab. Mereka juga menolak cara golongan Liberal menafsir ulang isi Alkitab.
Dalam hal ini kita mungkin juga dapat memahami mengapa rekonstruksi J. Wellhausen tentang sumber-sumber Pentateukh (teori J, E, D, P) telah diserang secara sedemikian gencar selama bertahun-tahun.8
KEBANGKITAN FUNDAMENTALISME
Istilah “fundamentalisme” pertama kali diberikan kepada mereka yang berpegang pada sudut pandang kepercayaan ortodoks dan pada saat yang sama menolak semua usaha golongan Liberal yang memodifikasi kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Ketika pertama kali diberikan, nama tersebut mengacu pada serangkaian brosur atau traktat-traktat yang diterbitkan antara 1910-1915. Dalam dua belas jilid The Fundamentals: A Testimony to the Truth9 dapat diamati adanya berbagai topik yang didiskusikan oleh banyak penulis. Buku ini berisi kritik tajam (kalau tidak mau dikatakan, kecaman) terhadap theologi Liberalisme, filsafat-filsafat modern, gereja Roma Katolik, sosialisme, ateisme, Mormonisme, Darwinisme dan yang terutama adalah serangan terhadap metode higher criticism. Topik-topik yang ada mencakup doktrin-doktrin esensial seperti: ineransi Alkitab, kelahiran Kristus dari anak dara, pendamaian, kebangkitan Kristus, dan dapat dipercayainya catatan-catatan tentang mujizat.10
Rangkaian dua belas jilid ini merupakan kapita selekta dari tokoh-tokoh yang melayani di sekolah theologi, gereja, kebaktian kebangunan rohani dan gerakan-gerakan independen dari pelbagai denominasi seperti Presbyterian, Baptis, Anglikan, dan yang lain dari Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia, dan Kanada. Apabila ditinjau dari segi isinya, boleh dikata para penulis tersebut telah memberikan kritik dengan cukup objektif dan cukup cermat dalam menangani pokok persoalan. Lebih dari itu, mereka telah memperlakukan materi literatur lawan mereka dengan semangat penghargaan di sana-sini.
Subjudul, A Testimony to the Truth, menunjukkan tujuan fundamentalisme yang mencoba menghadirkan kembali iman Kristen ortodoks dalam rangka menentang theologi Liberal dan isu-isu modern lainnya saat itu. Itu sebabnya, lebih dari tiga juta eksemplar karya ini disebarkan secara gratis kepada para pelayan dan pekerja Kristen di seluruh dunia. Hal itu dimaksudkan sebagai panduan bagi para pelayan Kristen agar mereka dapat memahami orang-orang Kristen kontemporer, baik ortodoks maupun Liberal.
Mengenai istilah “fundamentalisme” sendiri, Curtis Lee Laws, editor The Watchman Examiner, surat kabar dari kelompok Baptis, barangkali adalah orang pertama yang menggunakan istilah tersebut. Baginya, seorang fundamentalis adalah orang yang berkeinginan untuk “berperang” bagi asas-asas dasar iman.11 Istilah itu lalu berkembang menjadi sebuah sarana untuk mengidentifikasi seseorang yang percaya pada iman ortodoks dan yang secara aktif mempertahankannya. Akan tetapi, J. Gresham Machen (1881-1937), seorang theolog Presbyterian, lebih suka tidak menggunakan istilah tersebut. Baginya istilah itu terdengar seperti sebuah agama baru12 dan tidak mewakili iman Kristen historis seperti yang selalu diyakini oleh gereja. Karena istilah tersebut menjadi agak samar-samar baik bagi pendukung maupun penentangnya, kita akan mencoba mendefinisikan istilah “fundamentalisme” lebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan tema ini.
DEFINISI FUNDAMENTALISME
Karena para fundamentalislah yang pertama kali menggunakan istilah tersebut, adalah lebih baik definisinya dipetik terlebih dahulu dari mereka. Seorang penulis dari kalangan fundamentalisme mendefinisikannya sebagai “eksposisi hurufiah terhadap semua penegasan dan pendirian Alkitab serta pengungkapan yang militant terhadap semua penegasan dan pendirian yang tidak Alkitabiah.”13 Melalui definisi tersebut terlihat bahwa penekanannya adalah pada katakata “Alkitab” dan “militan.” Kata yang terakhir, yakni “militan” atau “militansi,” tampaknya memberikan ciri yang lebih dominan ketika seseorang hendak mengidentifikasikan pendekatan dan karakteristik para fundamentalis. Dengan kata lain, seorang fundamentalis akan siap sedia mempertahankan serta memperjuangkan iman ortodoks dengan gigih dan mati-matian. Mereka selalu berada di kancah peperangan religius. Seseorang yang terikat dalam peperangan demikian tidak akan melakukan kompromi ketika tiba pada pokok-pokok iman yang fundamental.
Sebagaimana telah kita amati di atas, Alkitab telah diidentifikasikan oleh para fundamentalis sebagai “medan peperangan” dalam perang religius. Yang menjadi musuh adalah mereka yang berpegang pada interpretasi Alkitab yang berdasarkan theologi Liberalisme, khususnya mereka yang mengadopsi metode “modern higher criticism.” Akan tetapi, bila ditanya: Siapa yang memulai “perang” tersebut? Para fundamentalis mengatakan bahwa golongan Liberal dan modernislah yang pertama-tama memulai perang yang tampaknya tidak pernah berakhir. Alasannya, kaum Liberal-lah yang mulai melakukan penyerangan dan gerakan sistematis untuk meruntuhkan otoritas Alkitab pada awal abad kesembilan belas. Bagi George Dollar serangan ini “lebih mematikan daripada peperangan militer, karena perang tersebut menyapu bersih fondasi spiritual gereja, bangsa dan tradisi kita.”14
Pada sisi lain, apa yang dimaksud para fundamentalis sebagai “eksposisi hurufiah terhadap semua penegasan dan pendirian Alkitab” adalah cara penerjemahan Alkitab yang khusus, yakni memahaminya secara literal. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hal itu tidak berarti mereka berpandangan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam Alkitab harus dilihat secara literal. Aturan pendekatan mereka terhadap Alkitab adalah “lakukan interpretasi literal di mana memungkinkan,” yakni apa pun di dalam Alkitab yang layak diinterpretasi dengan makna literal harus dipahami secara literal dan akurat. Lebih dari itu, mereka menganggap keyakinan akan ke-literal-an Alkitab tersebut sama dengan keyakinan terhadap Alkitab itu sendiri.15 Pada akhirnya, mereka menganggap orang-orang yang percaya Alkitab tetapi menginterpretasikannya dengan cara yang lain sebagai orang yang benar-benar menolak untuk mengakui kebenaran Alkitab.16
Dari definisi dan penjelasan di atas, dalam perspektif historis dapatlah diamati bahwa fundamentalisme sebenarnya telah terpecah ke dalam dua faksi. Yang pertama adalah fundamentalisme kaku dengan karakteristik umum seperti: pemisahan mutlak dari kelompok Liberal serta percaya pada teori pendiktean ilahi dalam pengilhaman Alkitab. Mereka berpegang pada ajaran dispensasionalisme yang sudah mapan dengan pemisahan radikalnya dari masyarakat serta sikapnya yang apatis terhadap upaya perbaikan terhadap permasalahan sosial yang ada.
Singkatnya, dalam fundamentalisme yang rigid ini yang terlihat adalah gejala separatisme dalam sebagian besar fokus perhatian mereka.17 Faksi yang kedua adalah fundamentalis reseptif yang berbeda dengan fundamentalis kaku atau separatis. Walaupun keduanya memiliki posisi yang sama dalam hal ineransi Alkitab, anti-evolusi, dan dispensasionalisme, fundamentalis reseptif lebih terbuka terhadap pendidikan yang lebih tinggi dan intelektualisme dalam dunia kekristenan.18 Mereka lebih komit dalam memberi perhatian kepada isu-isu sosial dan mengakui bahwa pada masa yang lalu mereka telah menghakimi orang percaya lainnya, terlalu menekankan spiritualitas eksternal, terlalu menentang perubahan, dan telah membuat beberapa penambahan kepada Injil dan juga terlalu otoritarian serta eksklusif. Pada hakikatnya, mereka siap untuk membuat perubahan-perubahan, mengakui kelemahan mereka dan melakukan reformasi di sana-sini.19
AJARAN-AJARAN FUNDAMENTALISME YANG KHAS20
Di antara sekian banyak ajaran fundamentalis, tampaknya tidak ada yang lebih ditekankan selain dari Alkitab yang tidak mengandung kesalahan (ineransi). Alkitab yang ineran itu menjadi dasar iman dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Penekanan pada keyakinan ini dilandasi oleh prinsip bahwa satu kesalahan saja akan menghancurkan atau mengancam seluruh doktrin kitab suci. Oleh karena itu, ditekankan bahwa orang Kristen sejati haruslah seorang yang percaya Alkitab, dan keyakinan ini seharusnya meliputi setiap aspek keseluruhan Alkitab (moralitas atau agama, sejarah atau ilmu pengetahuan).21 Sebagai hasilnya, fundamentalis memiliki lebih banyak pengikut yang dengan rela akan lebih skeptis terhadap validitas penemuan-penemuan sains daripada meragukan kitab suci yang pasti.
Faktor utama yang telah meletakkan fondasi bagi doktrin ineransi fundamentalis dimulai di Princeton Seminary pada abad kesembilan belas. Adalah Archibald Alexander (1772-1851), profesor dan leluhur theologi Princeton, yang menekankan otoritas Alkitab. Baginya, setiap hal yang dicatat dalam Alkitab selaras dengan kebenaran yang dapat diuji secara ilmiah. Ia yakin bahwa penemuan-penemuan sains tidak akan menyingkapkan sesuatu yang berkontradiksi dengan data dalam Alkitab. Menurutnya jikalau seorang pembaca Alkitab dipimpin dengan benar oleh Roh Kudus dan seorang ahli ilmu pengetahuan dituntun dengan benar oleh akalnya keduanya akan sampai pada kesimpulan yang sama. Tradisi yang dipimpin oleh Archibald Alexander ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Charles Hodge (1797-1878) dan putranya A. A. Hodge (1823-1886), serta B. B. Warfield (1851-1921). Warfield khususnya mempertahankan iman ortodoks dengan cara yang lebih kritis. Ia mempelajari Alkitab secara eksegetikal untuk membuktikan otoritas dan infalibilitasnya.
Akan tetapi pada tahun 1891, Charles A. Briggs (1841-1913) dari Union Theological Seminary di New York menyerang doktrin ineransi sebagaimana yang diajarkan oleh Hodge dan Warfield. Bagi Briggs, yang sama sekali bukan seorang modernis, setiap orang Kristen seharusnya secara realistis menerima Alkitab sebagaimana adanya, yakni Alkitab mengandung beberapa kesalahan di sana-sini, namun kesalahan-kesalahan tersebut tidak memberi pengaruh terhadap ajaran-ajaran pokok apa pun yang terkandung di dalamnya. Karena posisi atau argumen ini, Briggs kemudian “dibawa ke pengadilan gereja Presbyterian dan dihentikan dari pelayanan. Sebagai akibatnya, baik Briggs maupun seminarinya kemudian meninggalkan gereja Presbyterian.”22 Untuk sementara tampaknya fundamentalis telah memenangkan peperangan dalam institusi tersebut dan juga pada institusi lainnya.
Pada periode belakangan (1920-an), J. Gresham Machen,23 pengganti Warfield, melanjutkan serangan sistematis yang telah dimulai Warfield dan Hodge. Walaupun sebelumnya Machen telah belajar theologi dari W. Herrmann (murid A. Ritschl), ia bertekad membuktikan bahwa Liberalisme tidak ilmiah dan bahkan tidak kristiani.24 Ia memperlihatkan bagaimana Liberalisme mengambil akarnya dari naturalisme dan telah dengan sengaja mengabaikan banyak data Alkitab dan fakta-fakta iman Kristen.25
Dari sini nyatalah sekarang bahwa Alkitab memainkan peran yang tak dapat dipisahkan serta integral dalam fundamentalisme. Ketika diminta untuk menguraikan bagaimana fundamentalis berbeda dengan orang percaya lainnya, mereka akan dengan sendirinya memberi respons bahwa inti perbedaannya adalah pada Alkitab. Alkitab diterima secara literal dalam arti bahwa setiap kata, baik menyangkut doktrin, sejarah maupun sains harus dipandang ineran dan sepenuhnya ilahi. Sekalipun di antara fundamentalis masih terdapat perbedaan-perbedaan secara doktrinal dalam beberapa isu, semua fundamentalis akan menerima Alkitab sebagai perkataan final untuk semua pokok persoalan, baik yang sakral ataupun sekuler.
Untuk mendemonstrasikan prioritas firman yang tertulis, H. Lindsell menjelaskan dengan tegas bahwa “firman Allah yang tertulislah yang menyatakan kepada manusia Firman Allah yang berinkarnasi. Maka, Alkitab adalah satu-satunya firman Allah dan dari firman itulah kami berbicara sekarang.”26 Pada akhirnya Alkitab menjadi standar utama yang menentukan segala-galanya bagi keselamatan, pelayanan dan aspek kehidupan lainnya; Alkitab “dapat dikatakan telah menjadi semacam ikon dan objek sakramental.”27
Seperti yang telah kita ketahui pemahaman terhadap Alkitab di atas ditentang oleh beberapa theolog modern. Karl Barth misalnya, menerima Alkitab dengan gagasan berbeda. Baginya Alkitab sama sekali bukan firman Allah. Yesus Kristus adalah Sang Firman. Alkitab hanya penting bagi dogmatika Kristen karena menyatakan Firman yang berinkarnasi, yaitu Logos.28 Dengan kata lain, teks-teks khusus tertentu akan menjadi Firman Allah sejauh teks-teks tersebut berbicara kepada pembaca melalui perjumpaan ( encounter) yang dikendalikan Allah. Lebih jauh lagi, alasannya, Allah dalam ketidakterbatasan-Nya tidak dapat dicapai oleh manusia dalam keterbatasan mereka. Prinsip ini dapat dinyatakan melalui ungkapan yang umum dalam theologi Reformasi, yaitu: finitum non est capax infiniti (the finite is not capable of the infinite), dan finiti ad infinitum dari proportio non potest (no proportion can be given or made between the finite and the infinite).29
Hampir serupa dengan posisi Barth adalah pendapat Paul Tillich. Baginya Alkitab itu sendiri tidak lebih hanya sekadar catatan tentang penyataan dan bukan penyataan itu sendiri. Baginya penyataan yang sejati hanya dapat ditemukan melalui perjumpaan (encounter) dialektis yang dalam antara Allah dan manusia. Apa yang kita temukan dalam Alkitab adalah kesaksian atau catatan peristiwa khusus tersebut. Itulah sebabnya mengapa Tillich juga mengkritik pemahaman utama para fundamentalis tentang Alkitab. Dalam perkataannya: “The basic error of fundamentalism is that it overlooks the contribution of the receptive side in the revelatory situation and consequently identifies one individual and conditioned form of receiving the divine with the divine itself.”30
Jadi menurutnya pembedaan antara Allah dan manusia adalah hal yang telah diabaikan oleh para fundamentalis. Dari perspektif James Barr, fundamentalis telah menginterpretasikan Alkitab dengan cara yang dapat dikategorikan sebagai ketidakmungkinan yang absolut. Alasannya adalah karena kebanyakan orang percaya pada zaman Alkitab hidup dalam suatu periode “prakitab suci,” yakni periode sebelum adanya Alkitab. Orang-orang pada zaman Alkitab terikat pada proses yang mana pada akhirnya menghasilkan Alkitab kita saat ini. Hal ini berarti kitab suci yang kita miliki sekarang tidak menjelma begitu saja. Oleh karena itu, bagi Barr, agama orang-orang zaman Alkitab bukanlah sebuah agama berdasarkan kitab suci. Ia menyatakan dengan tegas bahwa kekristenan pada masa itu dapat berkembang dan menyebar tanpa satu Alkitab pun. Karena itu mengapa sekarang kita harus merasa terganggu dan mempermasalahkan hal ini?31
Menurut Barr, theolog-theolog ortodoks sedang mencoba membangun suatu bentuk tradisi yang ditarik dari Alkitab secara keseluruhan, namun bentuk tradisi ini tidak dikenal oleh orang-orang pada zaman Alkitab. Ia mengatakan: “Dalam hal ini pandangan tradisional tentang Alkitab mengandung kontradiksi serius: khususnya dalam hal mendorong pembaca untuk mengartikan makna kata-kata kitab suci yang sebelumnya sama sekali tidak ada di sana.”32 Untuk memperkuat hal ini, Barr memberikan bukti bahwa para nabi dalam periode Alkitab, seperti Elia, dan yang terakhir, Maleakhi, tidak pernah menggunakan “sebuah kitab suci yang sudah ada,” dan mereka juga tidak “menyebutkan adanya satu kitab suci seperti itu.” Mereka menyampaikan berita berdasarkan pada “Allah sendiri yang secara langsung memberikan kepada mereka perkataan itu,” dan frase kunci mereka adalah “Demikianlah firman Tuhan.”33
Ketika mendiskusikan PB, Barr kembali berpendapat bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia bukan untuk membawa suatu agama baru yang berdasarkan kitab suci ( a new scriptural religion).34 Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menetapkan status PB dalam kekristenan. Ia bahkan tidak pernah mengatakan kepada murid-murid-Nya untuk menuliskan dan menyusun ajaran-ajaran-Nya. Lebih jauh lagi, baginya, ide yang memutlakkan kitab suci sebagai pengendali agama merupakan konsepsi yang tidak dikenal dalam PB, karena sesungguhnya Yesus sendiri dengan ajaran-ajaran-Nya tidak diikat dan dikontrol oleh PL. Sikap Yesus terhadap PL bersifat kritis dan independen. Karena itu, bagi Yesus, PL tidak lagi bersifat normatif; otoritasnya bersifat relatif ketika diperhadapkan dengan otoritas Yesus yang tertinggi.35 Hal ini berarti Barr sendiri telah menyatakan secara formal bahwa ia menentang pengakuan yang berkesinambungan dari gereja Kristen terhadap PL (sebagaimana juga terhadap PB).
Jika demikian halnya, apakah Alkitab (yaitu PL dan PB) sama sekali tidak memiliki otoritas? Barr akan menjawab tidak; artinya, Alkitab tetap memiliki otoritas.36 Akan tetapi mengapa Alkitab memiliki otoritas? Ia menjawab bahwa “Alkitab memiliki otoritas karena otoritasnya, dalam bentuk tertentu, ikut terbangun di atas struktur iman Kristen dan agama Kristen.”37 Dari butir ini kemudian menjadi jelas bahwa Alkitab bagi Barr tidak sedikit pun memiliki otoritas yang normatif, karena “Alkitab lebih merupakan medan peperangan ketimbang sebuah kitab yang terdiri dari fakta-fakta yang benar.”38
Adapun pembahasan yang paling tajam adalah ketika Barr menghubungkan fundamentalisme bukan kepada mereka yang pada umumnya berpegang pada otoritas Alkitab. Tetapi kepada orang-orang yang “mengatakan bahwa otoritas doktrinal dan praktikal kitab suci perlu terikat kepada infalibilitasnya dan khususnya pada ineransi historisnya,” di mana mereka berpendapat bahwa “otoritas doktrinal dan praktikal tersebut akan bertahan hanya jika [Alkitab] pada umumnya tidak mengandung kesalahan, dan hal ini berarti secara khusus hanya jika [Alkitab] tidak mengandung kesalahan dalam pernyataan-pernyataan historisnya.”39 Akan tetapi, Barr sendiri ingin melepaskan diri dari semua konfesi atau tradisi historis dan ia cenderung berpegang erat pada jenis otoritas yang dapat menilai kitab suci secara subjektif, yakni yang selaras dengan bagaimana ia memahami apa yang dibacanya.40 Apa yang terlihat adalah Barr berusaha memasukkan prinsip-prinsip pengertiannya tentang otoritas guna diaplikasikan ke dalam teks-teks biblikal dan hal itu berarti menegaskan sentralitas unsur manusia dalam menjabarkan status kitab suci.
Kesimpulannya, kita dapat menyatakan bahwa apa yang Barr yakini adalah sebagai berikut: Pertama, baginya kitab suci pada dasarnya adalah tradisi yang senantiasa berkembang; PL sebagaimana juga PB diklasifikasikan sebagai tradisi progresif, bukan sebagai wahyu progresif.41 Kedua, pendekatannya bersifat historis dalam arti bahwa titik tolak referensinya adalah perspektif historis dari para penulis Alkitab. Karena itu metodenya dapat dikategorikan sebagai metode induktif, karena ia berprasuposisi bahwa teks Alkitab telah hadir sebelum adanya seluruh sistem interpretasi. Melalui cara ini Barr merasa telah menemukan cara untuk meneliti Alkitab dari perspektif yang sama seperti orang-orang pada masa periode pembentukan Alkitab.
KARAKTERISTIK UMUM FUNDAMENTALISME
Setelah menelusuri posisi fundamentalisme secara spesifik dalam persoalan Alkitab, sekarang marilah kita memperhatikan karakteristik umum yang ada pada tubuh gerakan tersebut. Pertama, selain Alkitab fundamentalis juga menegaskan penguasaan yang absolut tentang kebenaran. Dalam kalimat Barr, fundamentalis segera akan berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan.42 Mereka mengklaim telah mengenal kebenaran dan jawaban bagi setiap hal. Karena bagi mereka Allah itu tidak jauh dan Alkitab berisi semua jawaban final bagi kebenaran, maka dalam lingkaran keyakinan ini setiap hal menjadi mudah untuk dijawab.
Menurut N. T. Ammerman, dari sudut pandang sosiologis, fundamentalis dapat dikatakan berusaha membangun sebuah dunia di mana Allah sedang memegang kendali. Bagi mereka, pengertian tentang kebenaran yang absolut membuat hidup tidak lagi menjadi sebuah teka-teki.43 Mereka nampaknya mengetahui sepenuhnya bahwa Allah memiliki rancangan yang rapi dan mutlak bagi setiap orang percaya. Karakteristik umum fundamentalis yang lain adalah militansinya.44 Para ahli ilmu sosial kerap menyatakan bahwa fundamentalis cenderung bersikap memecah belah masyarakat secara sosial dan sering kali mengarah pada kekerasan.45 Perilaku militan ini biasanya ditujukan kepada sesama orang Kristen lain yang dianggap terlalu liberal atau modernistik. Sikap anti-modern ini membawa mereka hingga pada usaha untuk memulihkan dunia sekuler menuju pada suatu keadaan yang mereka anggap sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Para fundamentalis bahkan menolak setiap penjelasan rasional dalam rangka menyikapi realita modernitas.46
Sebagai pembanding, baiklah kita melihat apa yang dikatakan oleh H. Richard Niebuhr dalam karya terkenalnya Christ and Culture.47 Dalam karya tersebut ia menyajikan beberapa model tipologi adaptasi kekristenan sepanjang zaman. Misalnya, terdapat model “Kristus di atas Kebudayaan” (yang diadopsi oleh tradisi Katolik-Thomistik) yang berusaha membangun sebuah sintesis di antara nilai-nilai kekal dan hikmat dunia. Kemudian dijumpai pula model “Kristus dan Kebudayaan dalam Paradoks” (biasanya dianut oleh kelompok Lutheran) yang melukiskan ketegangan dualistik di mana orang percaya aktif di dalam dunia namun tidak yakin akan membawa hasil bagi kerajaan Allah. Yang berikut adalah model “Kristus Transformator Kebudayaan”—yang dianut oleh theolog Agustinian-Calvinis pada umumnya—yang berusaha membentuk dunia dalam setiap seginya menurut norma kitab suci dan tradisi Kristen. Melihat tipologinya, dapat kita amati dengan mudah bahwa fundamentalisme terposisikan pada model “Kristus Menentang Kebudayaan” karena ini adalah posisi di mana orang berusaha memisahkan diri dari dunia dengan segala permasalahannya.
Bagi Niebuhr, model “Kristus Menentang Kebudayaan” sesungguhnya telah muncul pada masa kini dalam fundamentalisme sektarian.48 Ia yakin bahwa apa yang kurang dalam paradigma ini adalah kesadaran akan adanya ketegangan antara gereja dan dunia. Karena itu orang yang berpegang pada model ini terpanggil untuk memisahkan diri mereka dari lingkup yang dianggap jahat dan lingkup yang berkompromi dengan dunia. Selain itu orang percaya diperintahkan untuk hidup dalam keadaan sadar untuk menentang nilai-nilai, tuntutantuntutan dan kebiasaan budaya dunia. Dengan demikian kata kuncinya adalah “tidak ada kompromi dengan dunia” dalam setiap bidang kehidupan. Melalui cara ini fundamentalis hidup dalam dunia namun mengambil posisi menentang semua hubungan dengan dunia. Hasilnya adalah militansi, intoleransi, konflik dan fanatisme yang telah menjadi ciri umum mereka.
Dari sini tampaknya juga menarik untuk melihat karakteristik umum fundamentalis dari perspektif E. Troeltsch tentang pola tipe gereja dan tipe sekte. Menurutnya tipe gereja yang banyak melakukan akomodasi diwakili oleh kiprah rasul Paulus yang sangat terbuka terhadap unsur filsafat umum atau Hellenisme. Sedangkan tipe sekte merupakan tipe yang khas diadopsi oleh Yesus dan para pengikut-Nya. Tipe ini dapat dikenali dari sikap radikal dan nonkomprominya terhadap dunia. Selain bersikap revolusioner, yakni selalu berusaha mereformasi aturan sosial yang telah ada, mereka juga secara pasif bersikap kritikal, yakni memilih untuk menarik diri ke dalam komunita kecil di mana tekanan unsur keagamaan secara optimal dapat dipraktekkan. Hal ini berarti bahwa baik tipe gereja dan tipe sekte sebenarnya terpisah dan berbeda, karena mereka mewakili dua kecenderungan dalam kekristenan yang secara radikal berbeda struktur dan orientasi nilainya.49
Apa yang ditulis Troeltsch di sini mungkin dapat dikatakan seperti “nubuat” bagi lahirnya gerakan fundamentalis pada awal abad ini. Fundamentalisme terlihat cocok dengan model tipe sekte. Dalam uraian yang lebih rinci, fundamentalisme dapat diklasifikasikan sebagai sekte agresif,50 yaitu sekte agresif yang berpegang pada ide tentang pembaruan dunia dengan menciptakan komunita yang steril. Pendekatan militan dalam hampir setiap hal adalah karakteristik tipe ini. Hasilnya, ia menjadi kelompok subjektivisme dan provinsialisme dengan sedikit kontak dengan dunia luar.
Untuk menyimpulkan bagian ini, ada baiknya dicatat bahwa fundamentalisme pada dasarnya adalah sebuah gerakan dengan suatu tuntutan akan kebenaran mutlak. Secara sosiologis, tuntutan akan kemutlakan ini dengan segera telah membawa gerakan tersebut ke dalam atmosfer militansi, intoleransi, retorasionisme, dan bahkan protes. Namun, apabila kita melihat fenomena ini lebih dalam, kita perlu bertanya: Apakah semua gerakan fundamentalis memiliki kekhususan dan karakteristik umum yang sama di setiap tempat di dunia? Adakah perbedaan di antara istilah “fundamentalisme” dan “evangelikalisme”?
Hal ini akan kita lihat dalam subjudul berikut.
FUNDAMENTALISME DAN EVANGELIKALISME
Ketika menjabarkan dan melukiskan apa yang kita maksud dengan “fundamentalisme,” kita telah mencatat beberapa kesimpulan dari kekhususan dan karakteristik umumnya; pertama, articulus fundamentalissimus seluruh doktrin dasar mereka adalah keyakinan akan ineransi Alkitab hingga setiap detail dengan interpretasi literalnya.51 Alkitab dan interpretasinya yang tepat telah menjadi tanda raison d’etre fundamentalisme dan ini menjadi satu-satunya sudut pandang rasional mereka. Kedua, fundamentalisme mengklaim telah mendapat kebenaran mutlak yang tidak dapat dinegosiasi. Dengan posisi ini mereka melawan setiap usaha untuk mencapai kesimpulan pluralistik atau relativistik dalam diskusi-diskusi theologis.52 Ketiga, fundamentalisme melakukan pendekatan kepada orang-orang Kristen lain atau sistem kepercayaan yang berbeda dari mereka dengan sikap militan. Bagi mereka, modernisme (atau bahkan, modernitas) seharusnya dihilangkan dari gereja. Oleh karena itu, semangat crusading dan intoleransi terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, menjadi stigma dari kebanyakan gerakan fundamentalis Kristen. Pendek kata, pada hakikatnya gerakan mereka adalah suatu gerakan protes yang berusaha melawan setiap usaha kompromi yang dilakukan oleh gereja, dengan menggunakan suatu otoritas absolut dari masa lalu sebagai senjatanya.
Dengan cara ini, secara agresif mereka mendesak orang percaya lain untuk menerima keyakinan absolut mereka tanpa syarat. Sekarang kita akan melihat secara seksama istilah “evangelikal.”53 Kata ini berasal dari kata benda dalam bahasa Yunani “euanggelion” yang diterjemahkan sebagai kabar baik atau sukacita atau Injil, dan kata kerja “euanggelizomai” yang artinya “mengumumkan atau memberitakan kabar baik.” Kata-kata ini dapat ditemukan hampir seratus kali dalam PB sendiri dan telah diterima dalam bahasa modern melalui padanan kata bahasa Latin “ evangel” atau “ evangelium.” Karena itu, istilah “evangelikal” mengacu kepada suatu jenis keyakinan yang berhubungan dengan Injil dan orang yang disebut “seorang evangelikal” adalah orang yang menganut suatu bentuk agama yang berpusat pada Injil.54
Apabila dibandingkan dengan fundamentalisme yang secara luas telah dikenal sebagai suatu gerakan militan dalam tubuh Protestantisme, evangelikalisme sebaliknya bersifat lebih terbuka karena di dalamnya terkandung koalisi tubuh kekristenan yang lebih luas. Menurut G. Marsden, “evangelikalisme saat ini meliputi orang-orang Kristen yang cukup tradisional untuk menegaskan keyakinan dasar konsensus kaum Injili abad kesembilan belas.”55 Dalam pengertian ini, istilah “evangelikal” atau “evangelikalisme” dapat mengacu kepada pengertian spesifik dari berita Kristen seperti Injil yang telah diafirmasi oleh para Reformator Protestan. I. H. Marshall berpendapat bahwa ketika terjadi “kebangkitan berita [Kristen] di gereja di Inggris pada abad delapan belas, [peristiwa] itu dinamai kebangkitan evangelikal, karena hal itu berarti kembali kepada berita Reformasi Protestan.” Hal ini sama persis ketika “terjadi ‘kebangunan evangelikal kedua’ pada pertengahan abad kesembilan belas,” karena hal itu berarti bahwa “pengalaman pada abad ketujuh belas terulang dengan sendirinya.”56
Dipandang dari perspektif ini dapatlah dikatakan bahwa evangelikalisme memiliki banyak titik kesamaan dengan ajaran dasar dari pegangan iman ortodoks. Marsden mencatat beberapa keyakinan hakiki evangelikal yang meliputi “(1) doktrin Reformasi tentang otoritas final Alkitab, (2) sifat historis yang nyata dari karya penyelamatan Allah seperti yang dicatat dalam kitab suci, (3) keselamatan untuk hidup kekal yang didasarkan pada karya penebusan Kristus, (4) pentingnya penginjilan dan misi, dan (5) pentingnya kehidupan yang ditransformasi secara spiritual.”57 Ini berarti evangelikalisme mencakup semua denominasi dalam Kekristenan seperti: Presbyterian, Baptis, Metodis, Pentakosta, Reformed, Episkopal, dan sebagainya.58 Karena itu dalam makna yang lebih luas evangelikalisme mencakup kalangan lintas denominasi yang memiliki kesamaan keyakinan hakiki dalam iman Kristen. Meskipun identitas denominasinya beragam, hingga pada taraf tertentu semuanya memiliki kesamaan dalam warisan religius masa lalu yang umum dan tetap menyebut diri mereka evangelikal.
Dari sini penulis akan membuat perbandingan antara fundamentalisme dan evangelikalisme.59 Pertama, keyakinan evangelical akan otoritas Alkitab dikontraskan dengan interpretasi literal dan otoritas tertinggi Alkitab dari fundamentalis. Apa yang membuat keyakinan evangelikal berbeda dengan fundamentalis adalah bahwa fundamentalis menjadikan ineransi Alkitab suatu otoritas absolut yang menjadi tumpuan setiap hal di tengah-tengah pandangan sekuler yang beragam. Hal ini tidak mungkin, karena interpretasi Alkitab itu sendiri terbatas dan falibel. Lagi pula suatu interpretasi dari apa yang Alkitab maksudkan untuk komunitas tertentu merupakan produk yang kompleks dari kitab suci dan komunitas tersebut. Memang benar bagian-bagian Alkitab tertentu dan interpretasi terhadap bagian tersebut akan bersifat mengikat. Hal ini terlihat pada beberapa denominasi di mana perikop-perikop Alkitab tertentu akan menjadi begitu hakiki bagi mereka sedemikian rupa sehingga mereka akan menghabiskan banyak waktu dalam menafsirkan bagian tersebut dan menganggapnya sangat penting bagi kehidupan dan pekerjaan Kristen, sedangkan bagi denominasi atau kelompok lain bagian tersebut tidak begitu penting.
Karena itu cara yang pantas untuk menginterpretasi Alkitab adalah pertama-tama menerima otoritasnya serta mengaplikasikannya dalam situasi kita. Tetapi—dan hal ini penting sekali—bilamana Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang suatu isu, para pembaca modern sebaiknya berhati-hati untuk tidak menjadikan interpretasi mereka sendiri pada pokok tertentu sebagai keyakinan yang paling otoritatif atau mutlak sepanjang waktu dan bagi semua kelompok Kristen. Kedua, kita harus mengakui bahwa tradisi diikat oleh budaya dan berbagai faktor lain; oleh karena itu tepatlah bila dikatakan bahwa setiap tradisi, bahkan yang ditarik dari Alkitab, tidak dapat diaplikasikan secara universal. Bahaya akan muncul ketika seseorang mencoba memaksakan tradisi tertentu dalam suatu komunitas dan menganggapnya otoritatif. Kita harus mengetahui bahwa tradisi adalah buatan manusia dan terikat pada budaya, karena itu seseorang harus siap untuk mengubahnya dan menghindari tendensi untuk mencoba menjadikannya sebagai suatu otoritas absolut.
Hal yang sama dapat terjadi terhadap keyakinan akan ineransi Alkitab. Alkitab sendiri tidak secara langsung mengatakan apa-apa dengan tegas mengenai isu ini. Memang Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kebenaran dan bahwa di dalam Dia tidak ada kebohongan (Ibr. 6:18; bdk. 2Tim. 2:13). Alkitab juga memproklamasikan bahwa hukum Allah sempurna (Mzm. 19:8), firman Tuhan itu tanpa cacat (2Sam. 22:31; bdk. Ams. 30:5), dan firman-Nya adalah kebenaran (Yoh. 17:17).60 Walaupun demikian Alkitab tidak menyatakan doktrin ineransi secara komprehensif kepada kita. Karena itu para pembaca Alkitab harus cukup hati-hati untuk tidak menetapkan interpretasinya sebagai keyakinan yang paling mutlak, walaupun kita mengetahui dari tradisi gereja bahwa orangorang terkemuka seperti Luther61 dan Calvin62 sedikit banyak berpegang pada keyakinan akan ineransi.
Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa ada perbedaan hakiki antara fundamentalisme dan evangelikalisme di mana yang belakangan tidak terikat secara mutlak pada “suatu pandangan yang tidak meragukan kitab suci tetapi terbuka terhadap pengertian yang baru dari kitab suci.”63 Apa yang dimaksud dengan “terbuka terhadap pengertian yang baru” adalah secara doktrinal sadar, yakni selalu siap sedia untuk mengklarifikasi bahwa kitab suci cukup memadai untuk tujuan yang Allah maksudkan dan siap sedia untuk menghubungkannya dengan kebutuhan dan pengertian masa kini. Hanya melalui prinsip inilah kaum evangelikal dapat menerima otoritas kitab suci dengan sepenuh hati dan mengertinya secara semper reformanda.
Kedua, penulis akan membandingkan penekanan evangelikal tentang keunggulan kebenaran Injil dengan penekanan fundamentalis pada kebenaran yang tidak dapat dinegosiasi. Berkaitan dengan Injil, agaknya fundamentalis di seluruh dunia mengambil posisi tersebut karena mereka menganggap bahwa kebenaran Injil telah dikompromikan atau dikorbankan oleh orang-orang Liberal serta kelompok Kristen lainnya. Apabila kecurigaan ini memang terbukti benar, maka tampaknya sah untuk tidak melakukan negosiasi dengan orang-orang yang berkompromi. Lagipula, Alkitab nampak mendukung posisi intoleransi terhadap mereka yang membawa “Injil yang lain” (bdk. Gal. 1:8).
Namun, evangelikal tetap bertahan bahwa kebenaran adalah sebuah kualitas yang terbuka untuk diuji.64 Ia adalah sesuatu yang terbuka untuk dikritik, sesuatu yang objektif. Pada sisi lain, fundamentalis berpegang pada pandangan kebenaran yang kaku dan tidak dapat dinegosiasikan. Walaupun beberapa evangelikal mungkin akan memegang posisi yang sama seperti fundamentalis, secara umum evangelikalisme sama sekali tidak akan menolak atau merendahkan Alkitab hanya karena adanya satu kesalahan yang dianggap tidak dapat diharmoniskan. Contohnya, sejauh yang bisa diperlihatkan, tidak ada theolog evangelikal yang berpikiran jernih yang pernah mengajar bahwa jika rincian kesejarahan Injil Lukas tidak dapat diharmoniskan dengan sumber-sumber di luar Alkitab maka Yesus Kristus pasti tetap berada di dalam kubur-Nya, dan Alkitab itu menipu, serta setiap orang percaya akan hidup dan mati tanpa pengharapan. Tidak pernah muncul pemikiran seekstrem itu.
Alasan lain mengapa dalam pokok mengenai kebenaran evangelical harus dibedakan dari fundamentalis adalah karena yang terakhir itu mendasarkan argumentasinya (mengenai ineransi, misalnya) pada kegunaannya, bukan pada kebenaran. Kebanyakan fundamentalis akan siap sedia menjawab bahwa mereka percaya pada Alkitab yang ineran lebih karena manfaatnya daripada karena kebenarannya. Mereka yakin bahwa suatu doktrin kitab suci yang kuat akan membawa kita kepada pengertian konsep Kristus yang lebih baik. Biasanya, demi tujuan praktis, para fundamentalis akan berusaha membenarkan keyakinan mereka tentang ineransi Alkitab dengan cara menarik analogi antara ineransi atau inspirasi dan inkarnasi (Kristus). Mereka memberikan perbandingan antara Firman yang menjadi daging dan firman Allah yang datang kepada umat manusia melalui kata-kata manusia. Karena itu Kristus yang tanpa dosa dianggap sama dengan Alkitab yang ineran. Namun sejauh argumentasi ini dapat diterima, kita dapat mengatakan bahwa penyamaan ini benar-benar tidak tepat, sebab proses Allah menjadi manusia tetap merupakan misteri. Kita tidak tahu bagaimana Allah menjadi manusia serta seperti apa rupanya menjadi Allah dan manusia sekaligus dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah alasannya mengapa untuk menyamakan misteri ini dengan misteri inspirasi adalah tugas yang mustahil. Hanya Allah yang mengetahui kedua proses tersebut dan sayang sekali Ia tidak memberitahukannya kepada kita. Singkatnya, makin cepat seseorang mengabaikan pendekatan ini akan lebih baik, karena argumentasi itu sendiri tidak meyakinkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara theologis.
Dapat dikatakan bahwa bagi fundamentalis kebenaran adalah sesuatu yang akan ia pertahankan ad infinitum dan mereka akan menggunakan semua cara argumentasi demi memenangkan perdebatan; karena itu bagi mereka kebenaran menjadi sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan. Sedangkan bagi seorang evangelikal kebenaran adalah sesuatu yang terbuka untuk diteliti dan bahkan dikritik. Meskipun dalam taraf tertentu kita perlu mengoreksi pandangan yang keliru dari para pengkritik Alkitab, bagi seorang evangelikal minatnya yang terutama adalah memproklamasikan serta mendemonstrasikan kebenaran Injil ke dalam budaya-budaya di mana berita itu belum didengar.65 Jadi, hakikat tradisi evangelikal dan sentra theologinya bukanlah meributkan persoalan ineransi atau teori inspirasi tertentu, melainkan meneruskan suatu berita penebusan dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus.
Kini kita tiba pada butir terakhir perbandingan antara fundamentalisme dan evangelikalisme, yakni militansi fundamentalisme dibandingkan dengan aktivisme evangelikal. Kebanyakan fundamentalis memiliki visi dalam benak mereka untuk memulihkan dunia kepada kondisi masa lalu atau bahkan ke zaman Alkitab. Pada akhirnya mereka menentang semua bentuk modernitas, walaupun mereka memanfaatkan peralatan modern seperti televisi.66 Militansi mereka juga terefleksikan dalam semangat untuk menarik orang mengikut pandangan mereka. Semangat ini tidak hanya diarahkan kepada orang non-Kristen, tetapi juga kepada orang Kristen yang dianggap Kristen nominal atau jenis-jenis theologi lainnya.
Di sisi lain, evangelikalisme telah memperlihatkan diri lebih positif dan jauh lebih kaya dalam aktivisme mereka dibanding fundamentalisme. Para evangelikal tidak takut dan tidak menentang modernitas karena mereka yakin bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Allah dan pertimbangan yang tepat tidak membahayakan iman yang sehat.67 Ketika diperhadapkan pada orang yang berbeda iman, mereka tidak mencela atau menolak dengan cara militan, melainkan dengan cara positif mendemonstrasikan iman Kristen dan tidak memadainya seranganserangan yang ditujukan padanya. Hal ini dilakukan tidak dengan motivasi pembenaran diri sendiri secara intelektual, melainkan demi kemuliaan Allah dan Injil-Nya. Hal ini berarti evangelikal telah memberi jawab atas tantangan fundamentalis mengenai identitas mereka dengan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan cara yang berbeda. Pemimpin mereka umumnya berpartisipasi lebih dari sebelumnya dalam semua aspek budaya modernitas yang ada.68 Hal itu sama sekali bukan usaha yang mudah untuk dijalankan, karena “modernitas menciptakan kondisikondisi yang menyulitkan kemampuan manusia untuk mempertahankan eksistensi yang stabil dan selaras dalam dunia. Manusia modern menderita krisis keyakinan.”69
Pada akhirnya, kita tiba pada kesimpulan bahwa evangelikalisme tidak sama dengan fundamentalisme. Evangelikalisme memiliki karakter yang lebih ilmiah dan lebih simpatik daripada pengamatan Barr. Biasanya mereka terdiri dari orang-orang yang ortodoks, yang pendekatannya tetap biblikal dan evangelistik, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang aktivistik, sederhana dan realistik. Secara pribadi penulis yakin bahwa penilaian terhadap evangelikalisme dan perannya dalam masyarakat akan terus berlangsung, dan citra kekristenan evangelikal menjadi lebih jelas di masa mendatang.
PERKEMBANGAN FUNDAMENTALISME KONTEMPORER
J. Naisbitt dan P. Aburdene secara meyakinkan telah memperkirakan bahwa pada penghujung abad (kedua puluh) atau awal milenium (ketiga) akan “ada tanda-tanda yang tak dapat diragukan lagi mengenai kebangkitan agama secara multidenominasi di seluruh dunia.”70 Namun apa yang dimaksud dengan “kebangkitan agama” tidak mencakup agama-agama utama atau gereja; justru yang terjadi adalah akan ada kemunduran yang sangat berarti pada gereja-gereja utama pada periode perubahan besar ini.71 Singkatnya, agama yang terorganisir akan ditolak dan menderita kemunduran, tetapi gerakan-gerakan “fundamentalisme dan pengalaman spiritual pribadi” akan tumbuh subur.72
Barangkali yang perlu diperhatikan dari apa yang dikatakan Naisbitt dan istrinya adalah karakterisasi umum dari gerakan-gerakan di atas, yaitu adanya suatu mata rantai antara kehidupan mereka sehari-hari, dengan hal-hal yang transenden, suatu pembalikan kepada masa yang lebih sederhana, serta adanya penolakan terhadap otoritas dari luar.73
Sebagai akibat dari karakterisasi ini adalah pertama-tama fundamentalisme telah mengembangkan suatu jenis isolasionisme yang aneh di mana mereka memperhatikan kepentingan sendiri dan tidak mencampuri kelompok Kristen atau denominasi lain. Dengan keegosentrisan yang ekstrem ini mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga berbaris maju secara agresif untuk mengorbankan kelompok-kelompok lain (yang biasanya dianggap bidat) guna memperluas “kerajaan” mereka sendiri. Mereka menolak terlibat demi kepentingan orang lain. Para pemimpin mereka juga menolak bergaul dengan orang lain. Apabila mereka bersama-sama atau bekerja sama, biasanya diakhiri dengan bertempur satu dengan yang lain. Bahkan di sini di Indonesia kita dapat mengamati banyak kasus seperti ini terjadi dalam gereja atau kalangan pemimpin dengan karakteristik demikian.74
Akibat lain dari karakterisasi ini adalah berkembangnya semangat negativistik dan kontroversial dalam fundamentalisme. Karena berkembangnya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh modernitas khususnya dalam era globalisasi, fundamentalisme memberikan reaksi karena ketakutan, yaitu ketakutan bahwa segala sesuatu akan ikut berubah termasuk tradisi dasar mereka. Ciri seperti ini dapat terlihat pada diri beberapa orang yang bereaksi demikian, yaitu melalui fanatisisme yang berlebihan untuk mempertahankan kebenaran interpretasi mereka terhadap kitab suci.75 Mereka mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan semangat tempur dan kontroversi.
Karena pada dasarnya ini adalah sebuah gerakan protes yang intinya adalah mempertahankan iman, fundamentalis menyerang isu-isu spesifik dari dekade ke dekade seperti evolusi, Liberalisme, gerakan ekumenikal, pendidikan sekuler, pluralisme, dan lain-lain.76 Tetapi jika “sparring-partner” mereka pergi atau tidak memberi respons, fundamentalisme juga surut atau menjadi kurang aktif.
KESIMPULAN AKHIR
Dalam bagian kesimpulan ini penulis akan menyoroti beberapa implikasi penting berkenaan dengan topik di atas. Pertama, problem fundamentalisme agaknya tidak akan sirna pada dekade-dekade mendatang; bahkan, persoalan ini kemungkinan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan peradaban dan modernisasi global. Fundamentalisme sudah terlihat juga di antara gereja-gereja di Asia atau Indonesia, karena pada dasarnya ia merupakan gerakan reaktif, yaitu reaksi terhadap modernitas atau modernisme yang juga telah masuk ke dalam gereja. Itulah sebabnya fundamentalisme telah hidup kembali dan menjadi populer di antara beberapa kelompok orang percaya pada dekade ini.
Kedua, fundamentalisme lambat laun telah berhasil mengembangkan reputasi yang “terkenal” karena sifatnya yang memecah belah, suka bertempur, kontroversial, negativistik, dan persisten. Fundamentalisme adalah gerakan protes yang bersifat apokaliptik, profetik dan kritis terhadap kehidupan modern serta perkembangan masa depan. Sebagian besar karakter ini adalah akibat dari naturnya yang reaksioner. Dengan natur demikian fundamentalisme melawan setiap perubahan atas rumusan-rumusan doktrinal. Mereka cenderung menjadi elit dalam semua bidang kepercayaan, sehingga setiap orang yang tidak berpegang pada posisi seperti mereka biasanya tidak termasuk saudara atau saudari dalam Kristus. Bahkan orang yang berpegang pada pandangan lain (seperti pandangan yang berbeda dalam premillenialisme yang tidak begitu hakiki) dipandang dengan kecurigaan. Karena pendirian seperti ini, kebanyakan fundamentalis tidak siap untuk bersekutu dengan kelompok Kristen lain (termasuk Pentakosta dan Kharismatik). Harapan satu-satunya adalah pada orang-orang yang moderat yang dapat menciptakan iklim yang lebih baik bagi dialog dan persekutuan namun tetap dipenuhi dengan hasrat yang kudus untuk memenangkan masyarakat Indonesia bagi Kristus sebagai ganti dari sikap bertempur yang tidak kenal akhir.
Ketiga, terlepas dari fenomena fundamentalis yang negatif seperti yang dikatakan di atas, dengan rendah hati dan jujur kita semua harus memeriksa diri berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang telah didiskusikan. Apa yang dikemukakan kaum fundamentalis adalah bahwa dalam kehidupan nyata cukup banyak orang Kristen yang tidak hidup di bawah otoritas Alkitab. Pengkritik-pengkritik fundamentalis hanya bersikap evasif bila mereka mengatakan tidak ada masalah doktrinal yang serius yang terlibat. Fakta yang sebenarnya adalah justru sebaliknya. Maka dari itu, di samping elemen-elemen militansi, isolasionisme, separatisme dan lain-lain yang dapat dijumpai dalam fundamentalisme, kita mungkin harus mengakui bahwa fundamentalisme tetap meninggalkan satu realitas penting, yakni mereka tetap memelihara kasih terhadap Alkitab dan membacanya. Mereka telah memelihara banyak doktrin iman yang kaya yang acapkali diabaikan. Mereka mengungguli dan memberi inspirasi kepada yang lain dalam penginjilan dan misi.
Keempat, kita harus mengakui bahwa fundamentalis kadang-kadang (jika tidak mau dikatakan, sering) membuat lebih banyak kemajuan dalam misi dan penginjilan daripada kelompok Liberal. Bahkan pengkritik fundamentalis terkadang mengakui bahwa mereka memiliki beberapa sumber kekuatan yang kurang dijunpai di antara kelompok Liberal. Jika asumsi-asumsi dasar fundamentalis dianggap benar, posisi mereka jelas dan logis. Mereka tahu dengan tepat apa yang mereka percayai dan tidak sekadar mencari kebenaran. Hal ini merupakan kontras yang tajam dengan pemikiran Liberal yang membingungkan dan tercampuraduknya ide-ide yang berkontradiksi. Karena itu tidak heran jika kita menjumpai adanya banyak petobat fundamentalis yang berasal dari anggota gereja Liberal yang mereka tinggalkan.
Kelima, adalah tidak adil dan hanya penyamarataan sekilas saja jika seseorang menyamakan fundamentalisme dengan evangelikalisme, atau fundamentalisme dengan tradisi Reformed. Fundamentalisme menerima Alkitab dengan cara interpretasi literal dan bahkan menjadikan Alkitab sebagai penguji ilmu pengetahuan modern. Setiap ayat, setiap kata dalam Alkitab, menjadi kebenaran literal dan “fakta” yang berdiri sendiri. Pada sisi lain, evangelikal atau tradisi Reformed menerima authoritas Scripturae dengan mencoba menangkap pemahaman seluruh Alkitab dan memberi tempat bagi interpretasi simbolik (tidak hanya literal) pada banyak bagian Alkitab. Mereka juga melihat kesaksian Roh Kudus dalam hati pembacanya sebagai bagian penting dari otoritas kitab suci, bukan kata-kata Alkitab saja. Militansi atau anti-modernisme (atau modernitas) juga membedakan fundamentalis sebagai subset dari evangelikalisme yang lebih luas. Beberapa denominasi bersifat evangelikal dalam doktrin (misalnya, Metodis, Baptis, Lutheran) tetapi tidak memiliki militansi yang berhubungan dengan fundamentalis. Di sini kita melihat isu atau perdebatan tentang doktrin telah bergeser dari sikap/pendirian ke arah pertahanan doktrin tersebut. Oleh karena itu tidaklah tepat untuk mengelompokkan semua agama konservatif evangelikalisme di bawah bendera fundamentalisme. Jelas bahwa secara historis tidak semua evangelikal atau kelompok konservatif menginginkan label fundamentalis. Setelah menyelidiki sejarah label yang populer dan acapkali merendahkan ini, kita akan menemukan bahwa banyak kelompok yang telah dicap fundamentalis telah lama menentang istilah religius tersebut.
Terakhir, diharapkan bahwa karya tulis ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang bagaimana seharusnya sejarawan Kristen dan theolog memandang fundamentalisme. Pada satu sisi fundamentalis selalu menentang ide-ide baru, inovasi, atau perubahan baru, namun perlu dicatat bahwa pada sisi lain sejumlah perubahan telah berlangsung dalam beberapa aspek pada kelompok yang diberi label fundamentalis. Dengan kata lain, fundamentalis atau evangelikal tidak bersifat statis ataupun monolitis. Karena itu para pengamat masa depan gerakan ini harus sadar akan perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga generalisasi sepintas yang “asal pukul rata” saja tidak akan muncul secara sembarangan.
Catatan Kaki:
* Artikel ini dapat terketik dengan baik atas bantuan dari Sdri. Lie Ing Sian, S.Th.; untuk kontribusinya penulis mengucapkan terima kasih.
1. Lih. N. T. Jabbour, “Islamic Fundamentalism: Implications for Missions,” International Journal of Frontier Missions 11/2 (April 1994) 81-86 dan N. Madjid, “Fundamentalisme Islam,” Tempo 22 (11 Juli 1992), hlm. 99.
2. “Fundamentalisme: Fenomena Baru Setiap Agama,” Kompas 27 (25 September 1992) 15. Untuk studi ekstensif fundamentalisme di seluruh dunia, lih. M. E. Marty & R. S. Appleby, eds., Fundamentalism Observed (The Fundamentalism Project; Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 1-872.
3. Sebagai contoh, lih. posisi J. Barr, Fundamentalism (Philadelphia: Westminster, 1977, 1978), hlm. 1.
4. The Christian Faith (New York: Harper & Row, 1963), hlm. 377 dst.
5. History of Dogma (London: Williams & Norgate, 1896) 1:169 dst.
6. (New York: Harper & Brothers, 1957), hlm. 55, 124-131. Dalam beberapa hal, buku ini mewakili akhir pencarian tentang Yesus. Bagi Harnack, kitab-kitab Injil tidak memberi kita cara untuk membangun sebuah hikayat Yesus yang lengkap, karena isinya hanya mengisahkan sedikit sekali permulaan kehidupan Yesus. Ia percaya bahwa yang Yesus sendiri beritakan dalam kitab-kitab Injil bukanlah tentang diri-Nya, tetapi terutama tentang Allah Bapa dan kerajaan-Nya (bdk. h. 27-33). Oleh karena itu, menurut Harnack, orang-orang Kristen modern seharusnya menaruh percaya pada Yesus, bukan di dalam Yesus (hlm. 144).
7. Contohnya, lihat karyanya The Christian Doctrine of Justification and Reconciliation (Edinburgh: T. & T. Clark, 1900) 3:30 dst., 473.
8. G. Hebert, Fundamentalism and the Church (Philadelphia: Westminster, 1957), hlm. 78-79.
9. Belakangan diterbitkan menjadi empat jilid saja; lih. R. A. Torrey, et al., The Fundamentals: A Testimony to the Truth (Grand Rapids: Baker, 1988).
10. Bdk. pernyataan J. R. Rice (I Am a Fundamentalist [Murfreesboro: Sword of the Lord Publishers, 1975], hlm. 9) yang mengatakan: “ . . . asas-asas iman Kristen meliputi inspirasi dan otoritas Alkitab, keilahian Kristus, kelahiran dari anak dara, pendamaian yang dikerjakan oleh darah Kristus, kebangkitan tubuh, kedatangan Kristus yang kedua kali secara pribadi, kejatuhan dan kondisi terhilangnya semua umat manusia, keselamatan melalui pertobatan dan iman, anugerah yang lepas dari perbuatan, hukuman kekal di dalam neraka bagi mereka yang tidak bertobat serta kebahagiaan kekal di dalam sorga bagi orang-orang yang diselamatkan.”
11. G. M. Marsden, Fundamentalism and American Culture (Oxford: Oxford University Press, 1980), hlm. 158.
12. Pada sisi lain, Machen sendiri secara implisit menyebut “Liberalisme” atau “modernisme” sebagai sebuah agama baru (yang tidak bersifat penebusan) karena didirikan di atas naturalisme; lih. Christianity and Liberalism (Grand Rapids: Eerdmans, 1946), hlm. 2.
13. G. W. Dollar, A History of Fundamentalism in America (Greenville: Bob Jones University Press, 1973), xv. Peter Berger et al. (The Homeless Mind: Modernization and Consciousness [New York: Random House, 1973] Bab 8) berargumen bahwa dampak-dampak modernisasi terhadap kesadaran manusia telah mengakibatkan bertumbuhnya peran birokrasi, teknologi, dan pluralisme. Karena itu ketika menggambarkan fenomena fundamentalisme, Berger dan penulis lainnya menjelaskan bahwa fundamentalisme, seperti halnya nasionalisme dalam lingkup politis, merupakan reaksi yang tak terhindarkan terhadap modernitas yang berupaya merekonstruksi nilai-nilai yang ada. Sampai pada tingkatan tertentu reaksi tersebut telah membuahkan suatu “sikap yang militan” terhadap yang lain.
14. Ibid., hlm. 1.
15. Karena itu berkaitan dengan hal ini baiklah kita perhatikan apa yang dikatakan James Barr: “My argument is simply and squarely that fundamentalist interpretation, because it insists that the Bible cannot err, not even in historical regards, has been forced to interpret the Bible wrongly; conversely, it is the critical analysis, and not the fundamentalist approach, that has taken the Bible for what it is and interpreted it accordingly. The problem of fundamentalism is that, far from being a biblical religion, an interpretation of scripture in its own terms, it has evaded the natural and literal sense of the Bible in order to imprison it within a particular tradition of human interpretation. The fact that this tradition . . . assigns an extremely high place to the nature and authority of the Bible is no way alters the situation described, namely that it functions as a human tradition which obscures and imprisons the meaning of scripture” (“The Problem of Fundamentalism Today” dalam The Scope and Authority of the Bible [Philadelphia: Westminster, 1980] 79; penegasan tambahan adalah dari penulis).
16. Di samping serangan terhadap Liberalisme, fundamentalis bahkan mengutuk fundamentalis lain. Contohnya, fundamentalis yang paling ketat, Bob Jones III dari Bob Jones University, menjuluki Jerry Falwell, seorang fundamentalis Baptis, sebagai seorang “pseudo neo-fundamentalis” dan G. W. Dollar menyebut Falwell sebagai “the leading TV Bishop of Compromise, Inc.”; lih. The Fundamentalist Phenomenon: The Resurgence of Conservative Christianity (ed. J. Falwell with E. Dobson & W. Hindson; Garden City: Doubleday, 1981), hlm. 160.
17. Lih. seluruh karya N. Ammerman, Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World (New Brunswick: Rutgers University Press, 1987). Walaupun dirinya seorang evangelikal, Ammerman mengakui bahwa ia telah memperoleh akses dari kelompok fundamentalis dan memahami cara pikir mereka sepenuhnya. Baginya, fundamentalis yang rigid berjuang untuk membentuk komunitas yang khas, berbeda dari dunia, dan terpisah dari orang Kristen lain yang mengkompromikan kesaksian dan identitas mereka. Dengan demikian mereka menolak bergabung dan bekerja dengan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan ortodoks keras yang sama.
18. Fakta ini juga disebutkan dalam bab ketiga karya Harvey Cox, Religion in the Secular City: Toward a Postmodern Theology (New York: Simon & Schuster, 1984).
19. Falwell, Fundamentalist Phenomenon, hlm. 219-221.
20. Penulis menyadari bahwa karakteristik khas fundamentalisme akan meliputi topik-topik seperti penginjilan, premillenialisme atau dispensasionalisme, separatisme, Darwinisme dan yang lainnya. Akan tetapi, untuk membatasi diskusi ini, kita akan melihat topik-topik yang kontroversial saja, seperti Alkitab.
21. Menurut K. C. Boone ( The Bible Tells Them So [Albany: State University of New York Press, 1989], hlm. 24), fundamentalis akan berpegang teguh pada sesuatu yang absolut dan membayangkan “diri mereka sendiri setia dalam kebenaran absolut atau berputar dalam kisaran nihilisme.”
22. G. W. Marsden, Understanding Fundamentalism and Evangelicalism (Grand Rapids: Eerdmans, 1991) 38. Untuk bibliografi ekstensif karya-karya yang berkaitan dengan isu ineransi , lihat M. A. Noll, “Evangelical and the Study of the Bible” dalam Evangelicalism and Modern America (ed. G. W. Marsden; Grand Rapids: Eerdmans, 1984), hlm. 198-199.
23. Lihat catatan kaki 12 mengenai karya kontroversialnya Christianity and Liberalism. Machen sendiri akhirnya menemukan bahwa seminarinya (Princeton) terlalu Liberal sehingga ia meninggalkannya untuk mendirikan sebuah seminari baru (Westminster Theological Seminary, Philadelphia) pada tahun 1929. Ia melihat bahwa setelah Princeton Seminary direorganisasi, seminari itu terlalu banyak bersikap toleran dalam hal doktrin. Bagi Machen, toleransi terhadap modernisme benar-benar tidak selaras dengan iman ortodoks. Oleh karena itu, sebagai seorang yang berkeyakinan tradisional, ia meninggalkan institusi tersebut setelah gagal membersihkannya dari dalam. Lih. juga C. A. Russell, Voices of American Fundamentalism: Seven Biographical Studies (Philadelphia: Westminster, 1976), hlm. 153-156.
24. Ibid., hlm. 7.
25. Ibid., hlm. 2. Machen bahkan secara meyakinkan menandaskan bahwa “Kekristenan didirikan di atas Alkitab. . . . pada sisi lain Liberalisme didirikan di atas perubahan emosi dari manusia berdosa” (h. 79).
26. The Battle for the Bible (Grand Rapids: Zondervan, 1976), hlm. 30, 139.
27. Boone, The Bible, hlm. 13.
28. K. Barth, “The Doctrine of the Word of God” dalam Church Dogmatics (Edinburgh: T. & T. Clark, 1936) I:2. 35, 346, 534-535.
29. Bdk. perkataan E. Gritsch ketika ia berargumen bahwa “Mereka yang sadar akan perbedaan antara Allah (yang tidak dapat dicapai melalui segala usaha atau kegiatan manusia) dan eksistensi manusia yang fana dalam ruang dan waktu, tidak akan memiliki ultimate trust pada Alkitab sebagai sebuah kitab. Mereka akan setuju dengan wawasan ekumenikal yang terbaik, yaitu bahwa penyataan Allah dalam Kristus akan membuktikan keabsahannya sendiri” (Born Againism: Perspectives on a Movement [Philadelphia: Fortress, 1982], hlm. 59). Ini adalah perspektif yang standar dari kaum ekumenis dan neo-ortodoks.
30. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality (Chicago: University of Chicago Press, 1955), hlm. 4.
31. Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism (Philadelphia: Westminster, 1983), hlm. 1-2. Walaupun karya Barr ini tidak secara eksplisit ditujukan kepada fundamentalis (ia hanya menyebutnya kelompok Protestan atau Protestantisme), kita tetap dapat melihat bagaimana argumen Barr yang secara implisit tidak setuju dengan sebagian besar gagasan fundamentalis mengenai kitab suci.
32. Ibid., hlm. 4. Karena posisi ini, Barr juga menolak pandangan tradisional yang meletakkan Alkitab sebagai standar tertinggi bagi gereja. Ketika membahas ayat krusial seperti 2 Timotius 3:16, dengan lantang Barr mengemukakan bahwa ayat itu tidak menyatakan apa-apa mengenai Alkitab yang menjadi fondasi iman Kristen. Dengan perkataan lain, menegaskan bahwa kitab suci diinspirasikan tidak berarti secara otomatis ia menjadi norma yang mengontrol dan mendominasi natur serta karakter iman Kristen (lih. hlm. 20). Bdk. diskusi Barr tentang hal ini dalam The Scope and Authority of the Bible (Philadelphia: Westminster, 1980), hlm. 63 dan Beyond Fundamentalism (Philadelphia: Westminster, 1984), hlm. 3.
33. Ibid., hlm. 5.
34. Ibid., hlm. 11-13.
35. Ibid., hlm. 14-15. Bagi Barr, Yesus secara terbuka telah menyangkal makna literal PL (khususnya hukum Taurat), karena PL bukanlah dasar dan otoritas ajaran-Nya; sebaliknya Yesus memberitakan secara terbuka makna spiritual dari PL (dan hukum Taurat).
36. Scope and Authority, hlm. 52.
37. Ibid.
38. Ibid., hlm. 53.
39. Ibid., hlm. 65. Pada satu sisi, penulis menghargai apa yang Barr katakan dalam seluruh bab ini (Bab 5. “The Problem of Fundamentalism Today”), akan tetapi, pada sisi lain, yang paling mengecewakan adalah membaca ungkapan istilah-istilah yang merendahkan, kalau tidak mau dikatakan, melecehkan, atau bahkan sarkastik, yang dipergunakan Barr untuk mengklasifikasikan kaum fundamentalis. Ia menyebut fundamentalisme sebagai suatu gerakan yang tidak memiliki “pemikir-pemikir theologis kelas satu” (hlm. 66). Menurutnya fundamentalisme bukan hanya ekspresi emosionalisme dan kefanatikan (bigotry), tetapi juga mereka memadukan intelektualisme rasionalistik dengan penipuan diri secara intelektual yang dikawinkan dengan suatu bentuk kelaparan yang kuat untuk mendapatkan pengakuan intelektual; karena itulah menurutnya kaum fundamentalis boleh disebut telah “menjadi jahat [atau kesurupan] (demonic)” (hlm. 68). Barr bahkan menyamaratakan semua karya akademik fundamentalis saat ini sebagai “tidak menarik, membosankan, tidak membangkitkan semangat dan kurang menyentuh” (hlm. 87). Ejekan yang meremehkan ini seharusnya tidak muncul dalam sebuah karya ilmiah yang baik. Dalam hal ini, sampai pada taraf tertentu agaknya N. Clark benar ketika ia mengatakan bahwa “Barr lebih merupakan seorang pakar pembongkar ketimbang seorang pembangun” (“In the Study,” The Baptist Quarterly 30 [1984], hlm. 282).
40. Alasan Barr, pada hari penghakiman nanti setiap orang Kristen tidak akan “ditanya mengenai doktrin kitab suci apa yang ia pegang,” sebab “tidak ada bukti bahwa Allah menghukum seseorang karena doktrin kitab suci mereka” (lih. Holy Scripture 19; juga catatan kaki 17).
41. Bdk. juga posisi ini dalam karyanya yang lain Old and New in Interpretation (London: SCM, 1966), hlm. 15, 19, dan The Bible in the Modern World (London: SCM, 1973), hlm. 146.
42. J. Barr, “Fundamentalism—A Challenge to the Church,” Quarterly Review 11/2 (1991), hlm. 32. Bdk. analisis H. Schäfer, “Fundamentalism: Power and the Absolute,” Exchange 23/1 (April 1994) khususnya hlm. 3-7.
43. Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World 16, hlm. 88. Barangkali fenomena ini dapat dimengerti dalam istilah yang disebut P. Berger sebagai perlindungan “tudung sakral,” yang artinya, dunia para fundamentalis yang tertib ini merupakan tudung proteksi bagi kelestarian gerakan tersebut. “The sacred cosmos, which transcends and includes man in its ordering of reality, thus provides man’s ultimate shield against the terror of anomy. To be in a ‘right’ relationship with the sacred cosmos is to be protected against the nightmare threats of chaos. To fall out of such a ‘right’ relationship is to be abandoned on the edge of the abyss of meaninglesness” (The Sacred Canopy [New York: Doubleday, 1969], hlm. 26-27).
44. Barr, “Fundamentalism—A Challenge to the Church”, hlm. 33.
45. Bdk. J. D. Hunter, “Fundamentalism in Its Global Contours” dalam The Fundamentalists Phenomenon (ed. N. J. Cohen; Grand Rapids: Eerdmans, 1990), hlm. 63.
46. Menurut Berger, ada tiga pilihan bagi orang Kristen untuk menghadapi tantangan modernitas. Yang pertama adalah penyerahan kognitif (cognitive surrender), yaitu secara mudah menerima fakta bahwa kelompok mayoritas itu benar dan kemudian melakukan adaptasi diri terhadap sudut pandang tersebut. Inilah yang pertamatama ditolak fundamentalis. Pilihan ekstrem kedua yang berseberangan adalah reduksi kognitif (cognitive retrenchment). Pada sisi ini pun para fundamentalis menolak sepenuhnya asumsi dasar posisi modernis. Dari perspektif Berger, ini adalah prasuposisi fundamentalis yang menyedihkan. Posisi di tengah sebagai pilihan terakhir adalah tawar-menawar kognitif (cognitive bargaining), di mana hal ini disebabkan seseorang melihat adanya dua sudut pandang dunia yang bertentangan dan ia mulai memikirkan langkah melakukan negosiasi. Secara teori dikatakan bahwa inilah wilayah di mana para fundamentalis diharapkan mencapai kompromi kognitif. Namun, sebagaimana telah dicatat oleh para ahli teori sosial, fundamentalis cenderung bersikap nonkompromi dan secara sosial memecah masyarakat serta budaya (The Sacred Canopy, hlm. 55-58).
47. (New York: Harper, 1951).
48. Bagi Niebuhr sebenarnya model ini telah terbentuk pada permulaan tradisi Kristen semasa penganiayaan awal Kekaisaran Romawi. Bagi orang percaya pada masa itu, kerajaan Allah tidak ada urusan apa pun dengan kekaisaran; orang Kristen hidup dalam dunia yang penuh dosa, tetapi mereka bukan milik dunia.
49. The Social Teaching of the Christian Churches (Chicago: University of Chicago Press, 1960) 1:331-346.
50. Ibid., hlm. 691 dst.
51. Untuk melihat pokok bahasan tentang interpretasi Alkitab secara literal, lih. G. Hebert, Fundamentalism and the Church 84-98. Lih. juga kritik J. Barton, People of the Book? The Authority of the Bible in Christianity (London: SPCK, 1988), hlm. 1.
52. Lih. R. Gill, Competing Convictions (London: SCM, 1989), hlm. 23.
53. Di sini penulis berusaha menjernihkan dan membedakan istilah “fundamentalis” dan “evangelikal.” Penulis sadar bahwa bagi mereka yang menentang keduanya tidak akan setuju dengan gagasan ini. Contohnya, lihat J. Barr (Fundamentalism, hlm. 4 dst.) yang percaya bahwa kedua istilah tersebut saling melengkapi saja; pada dasarnya keduanya sama saja.
54. Sedangkan istilah “evangelistik” mengacu pada suatu jenis kegiatan yang dihubungkan dengan Injil, yaitu kegiatan yang membuat Injil dikenal oleh orang lain dengan tujuan untuk meyakinkan mereka menerimanya dan karenanya menjadi orang percaya.
55. Understanding Fundamentalism and Evangelicalism, hlm. 4. Bdk. misalnya “evangelical” dalam konteks Jerman kontemporer (evangelisch) yang sama persis dengan Protestan. Kalangan Lutheran juga menggunakan istilah “evangelical” dalam makna yang lebih luas yang kira-kira sepadan dengan “Protestan” dan bahkan “Kristen” (lih. h. 5, catatan kaki 2).
56. “Are Evangelicals Fundamentalists?,” Vox Evangelica 22 (April 1992), hlm. 8.
57. Marsden, Understanding Fundamentalism and Evangelicalism, hlm. 4-5. Bdk. pandangan D. Bebbington yang memakai istilah serupa “biblicism, crucicentrism, conversionism, and activism” dalam menggambarkan kualitas-kualitas hakiki evangelikalisme (Evangelicalism in Modern Britain [London: Unwin Hyman, 1988], hlm. 2 dst.).
58. Ibid., hlm. 5.
59. Untuk ide perbandingan ini penulis bergantung pada artikel I. H. Marshall, “Are Evangelicals Fundamentalists?”, hlm. 11 dst. Namun demikian, untuk kepentingan argumentasi, urutan Marshall (dari satu hingga tiga) telah ditukar dan diubah sedikit. Bdk. juga dengan E. Jorstad, “Two on the Right: A Comparative Look at Fundamentalism and New Evangelicalism,” The Lutheran Quarterly 23/2 (May 1971), hlm. 107-117.
60. Walaupun secara pribadi yakin akan ineransi Alkitab, penulis tidak berpikir bahwa melalui bukti ayat-ayat ini saja sudah cukup untuk membangun sebuah theologi absolut tentang tema ini. Yang terjauh yang penulis lakukan adalah menerima ineransi sebagai komitmen theologis, yaitu seperti keyakinan dalam iman, dan kepercayaan kepada Allah yang tidak mungkin berbohong; tetapi keyakinan dan kepercayaan itu sendiri bukan Allah.
61. Lih. S. Wood, Captive to the Word: Martin Luther—Doctor of Sacred Scripture (Grand Rapids: Eerdmans, 1969) 144; J. W. Montgomery, “Lessons from Luther” dalam God’s Inerrant Word: An International Symposium on the Trustworthiness of Scripture (Minneapolis: Bethany, 1975) 88-90; P. Althaus, The Theology of Martin Luther (Philadelphia: Fortress, 1966) 6; M. Reu , Luther and the Scriptures (Columbus: Wartburg, 1944) 24; dan R. D. Preus, “The View of the Bible Held by the Church: The Early Church Through Luther” dalam Inerrancy (Grand Rapids: Zondervan, 1979), hlm. 380.
62. J. Calvin, Commentary on the Book of Psalms (Grand Rapids: Baker, 1979) 4:480; bdk. J. S. K. Reid, The Authority of Scripture: A Study of the Reformation and Post-Reformation Understanding of the Bible (New York: Harper & Brothers, t. t.), hlm. 55; H. J. Forstman, World and Spirit: Calvin’s Doctrine of Biblical Authority (Stanford: Stanford University, 1962), hlm. 1-6; J. McNeill, “The Significance of the Word of God for Calvin,” Church History 28 (1959), hlm. 131-146; F. L. Battles, “God Was Accommodating Himself to Human Capacity,” Interpretation 31 (1977), hlm. 19-38; E. Dowey, The Knowledge of God in Calvin’s Theology (New York: Columbia University, 1952), hlm. 104-105; dan B. Gerrish, “Biblical Authority and the Continental Reformation,” Scottish Journal of Theology 10 (1957), hlm. 354-355.
63. Marshall, “Are Evangelicals Fundamentalists?”, hlm. 22.
64. Meminjam istilah M. Heidegger yang menerangkan natur kebenaran sebagai “letting—something—be—seen” dan “being false . . . amounts to deceiving in the sense of covering up” (Being and Time [New York: Harper, 1962], hlm. 56-57 [yang dicetak tegak adalah aslinya]). Untuk diskusi ekstensif tentang makna atau natur kebenaran, lih. A. F. Holmes, All Truth is God’s Truth (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), hlm. 34-38; A. C. Thiselton, “Truth” dalam The New International Dictionary of New Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1978) 3:874-901; E. J. Carnell, Christian Commitment (New York: Macmillan, 1957), hlm. 10-30; G. H. Clark, “The Bible As Truth,” Bibliotheca Sacra 114 (April 1957) 158 dst.; N. Geisler, “The Concept of Truth in the Inerrancy Debate,” Bibliotheca Sacra 137 (October-December 1980), hlm. 333-334.
65. Menurut P. L. Berger, “The most obvious fact about the contemporary world is not so much its secularity, but rather its great hunger for redemption and for transcendence” (The Heretical Imperative [Garden City: Doubleday, 1979], hlm. 183-184). Bdk. H. J. Ockenga, “From Fundamentalism, Through New Evangelicalism, to Evangelicalism” dalam Evangelical Roots (ed. K. S. Kantzer; Nashville: Thomas Nelson, 1978), hlm. 41-44.
66. Lih. J. Barr, “Fundamentalism—A Challenge to the Church”, hlm. 33.
67. Dari data historis dapat dilihat bahwa fundamentalisme kurang lebih ditandai dengan ketidakpercayaan pada akal, apologetika yang dangkal, ketandusan kultural, individualisme eksentrik, dan sebagainya. Tentu saja beberapa evangelikal akan mewarisi satu dan dua karakteristik di atas, namun tentu tidak semua evangelical seperti itu. Bdk. D. M. Lloyd-Jones, What is an Evangelical? (Edinburgh: Banner of Truth, 1992), hlm. 44-61; R. Quebedeaux, The Young Evangelicals: Revolution in Orthodoxy (New York: Harper & Row, 1974), hlm. 28-41.
68. Contohnya, lih. kesaksian R. V. Pierard, “The Quest for the Historical Evangelicalism: A Bibliographical Excursus,” Fides et Historia 11/2 (Spring 1979), hlm. 60-69, dan J. T. Hickman, “The Polarity in American Evangelicalism,” Religion in Life 44/1 (Spring 1975), hlm. 53-57.
69. Bagi Liberalisme hal ini tidak sulit karena pada hakikatnya Liberalisme adalah adaptasi kesadaran terhadap nilai-nilai modern dan norma-norma kultural. Bdk. J. D. Hunter, Evangelicalism: The Coming Generation (Chicago: University of Chicago Press, 1987), hlm. 8. Sulit bagi evangelikal karena tugas seorang Kristen dan identitasnya telah didefinisikan melalui apa yang diyakininya, bukan oleh otoritas institusional eksternal seperti dalam Roma Katolik, tidak juga oleh pengalaman seperti dalam Hinduisme dan Buddhisme, dan juga tidak dalam komunitas etik religius seperti dalam Yudaisme. Sama seperti tradisi Kristen konservatif, evangelikal akan menderita akibat dari instabilitas, relativisme dan fragmentasi budaya modern karena mereka memiliki apa yang disebut Hunter sebagai “fiksasi theologi” (hlm.19).
70. Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990’s (New York: Avon, 1990), hlm. 290.
71. Ibid., hlm. 294.
72. Ibid., hlm. 28. Kita harus memahami bahwa Naisbitt dan Aburdene nampaknya lebih menyukai gerakan yang belakangan (yaitu spiritualisme), dan tentu saja bukan yang lebih dulu. Keduanya memberikan diskusi ekstensif dan positif tentang New Age Movement pada halaman 302-321.
73. Ibid. Menarik untuk dicatat bahwa baik Liberalisme maupun fundamentalisme tidak menyukai kredo, pengakuan, dan otoritas dari luar dengan alasan berbeda. Liberalisme dalam usaha mereka merelatifkan kekristenan merasa terganggu dengan formulasi-formulasi doktrinal historikal yang konkret, sedangkan fundamentalisme dalam ketaatan kepada otoritas biblikal berpendapat bahwa ungkapan-ungkapan demikian merupakan bahaya terhadap agama yang harus eksklusif biblikal.
74. Karena perhatian penulis dalam artikel ini adalah menyoroti anomali atau kekeliruan fundamentalisme, dengan sengaja di sini dihindari penyebutan atau pemberian catatan atau referensi kasus-kasus tersebut (meskipun dokumentasi demikian dapat dibuat dengan mudah).
75. Untuk mengenal fundamentalisme di Indonesia dari perspektif pemikir ekumenis, lih. E. Darmaputera, “Sikap Terhadap Fundamentalisme Kristen—Kita Harus Menentukan di mana Kita Berdiri,” Materi yang Tidak Diterbitkan (1989); E. G. Singgih, “Fundamentalisme Sebagai Reaksi yang Menolak Perubahan,” Materi yang Tidak Diterbitkan (t.t.); E. Darmaputera, “Fundamentalisme—Refleksi Theologis,” Peninjau XVII/2 + XVIII/2 (1992/2+1993/1) 69-75; A. A. Sutama, “Alkitab, Fundamentalisme dan Pendidikan Kristen,” Penuntun 1/2 (Januari-Maret 1995) 187-195; Soetarman SP, et.al., Fundamentalisme, Agama-agama dan Teknologi (Jakarta: Gunung Mulia, 1993). Karya J. Barr Fundamentalism juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh BPK Gunung Mulia.
76. Beberapa pemimpin fundamentalis bahkan dapat dikatakan telah mempergunakan kampanye menentang Liberalisme, ekumenikalisme, dan yang lainnya untuk menambah jumlah pengunjung gereja mereka, untuk meningkatkan pelanggan majalah, dan dalam kasus tertentu untuk meningkatkan kemakmuran dan prestise mereka. Lih. N. F. Furniss, The Fundamentalist Controversy (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 24-33.
Sumber:
VERITAS 2/1 (April 2001), hlm. 71-99
Profil Pdt. Dr. Daniel Lucas Lukito:
Pdt. Daniel Lucas Lukito, S.Th., M.Th., D.Th. adalah Rektor sekaligus dosen Theologi Sistematika dan Theologi Kontemporer di Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang. Beliau meraih gelar Sarjana Theologi (S.Th.) dari SAAT Malang; Master of Theology (Th.M./M.Th.) dari Calvin Theological Seminary, U.S.A.; dan Doctor of Theology (Th.D./D.Th.) dari Southeast Asia Graduate School of Theology, Filipina.
Editor dan Pengoreksi: Denny Teguh Sutandio