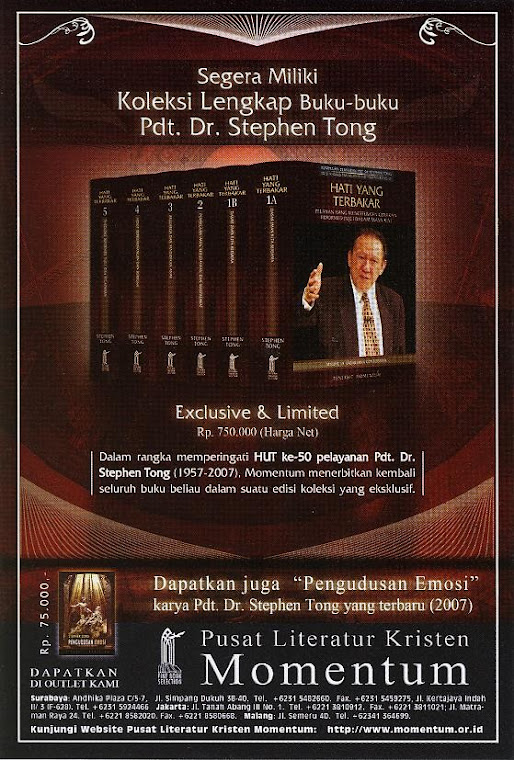oleh: Ev. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Nats: 1 Korintus 7:10-11
Perintah dari Tuhan Sendiri (ay. 10a)
Perhatian Paulus terhadap isu perceraian di sini harus dilihat dalam kaitan dengan problem utama yang sebelumnya sudah dibahas (7:1b). Konsep theologis yang salah dari jemaat Korintus tentang kerohanian membuat mereka menghindari hubungan seksual antara suami-istri. Apa yang mereka sedang lakukan bukan hanya untuk sementara waktu seperti yang dinasehatkan Paulus di ayat 5, tetapi mereka bahkan berpikir untuk bercerai. Kepada mereka, Paulus memberikan nasehat di ayat 10-11.
Paulus menujukan nasehat ini “kepada orang-orang yang sudah kawin” (tois gegamēkosin, ay. 10). Sekilas ungkapan ini tampaknya tidak diperlukan. Kalau mereka belum kawin, tentu Paulus tidak perlu repot-repot memberi nasehat agar jangan jangan bercerai. Paulus ternyata memikirkan kelompok jemaat tertentu pada saat ia menyebut “orang-orang yang sudah kawin”.
Maksud dari sebutan di atas adalah “orang-orang Kristen yang kawin dengan orang Kristen juga”. Dengan kata lain, nasehat ini ditujukan pada pasangan Kristen. Ada beberapa argument yang mendukung bagian ini. Pertama, kelompok jemaat di ayat 10-11 dikontraskan dengan jemaat tertentu di ayat 12-16 yang memiliki pasangan non-Kristen. Di ayat 12 LAI:TB secara kurang tepat menerjemahkan “kepada orang-orang lain”. Semua versi Inggris menerjemahkan “kepada yang lainnya/sisanya” (tois loipois). Yang dimaksud loipoi di ayat ini adalah orang-orang yang berbeda dengan di ayat 10-11. Kedua kelompok ini sama-sama sudah kawin, tetapi kelompok pertama adalah pasangan Kristen, sedangkan yang lainnya bukan dengan orang Kristen.
Kedua, di ayat 2-5 Paulus sudah membahas tentang pasangan Kristen. Hal ini kita ketahui dari ungkapan “supaya kamu dapat berdoa” (ay. 5). Jika salah satu pasangan bukan orang Kristen maka Paulus tidak akan menyinggung tentang doa.
Pembedaan kelompok ini perlu ditekankan, karena Paulus memberikan perintah yang agak berbeda untuk dua kelompok itu. Bagi pasangan Kristen, perceraian dan kawin lagi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi (ay. 10-11). Bagi pasangan campuran, perceraian tetap dimungkinkan, meskipun harus memperhatikan beberapa syarat dan pertimbangan tertentu (ay. 12-16).
Kepada kelompok pertama Paulus menyatakan bahwa Tuhan sendiri (bukan dia) memerintahkan (ay. 10). Pemilihan kata “memerintahkan” (parangellō) di ayat ini merupakan sesuatu yang menarik dan menyiratkan penekanan. Paulus biasanya hanya memakai ungkapan yang – sekalipun tetap berotoritas – tetapi setegas di ayat ini, misalnya “kelonggaran, bukan perintah” (ay. 6), “aku anjurkan” (ay. 8), “baiklah/adalah baik” (ay. 8, 26), “aku katakan” (ay. 12), “aku memberikan pendapatku” (ay. 25).
Ungkapan “aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan” (ay. 10) telah mendorong beberapa penafsir untuk menduga bahwa Paulus mengoreksi apa yang sudah terlanjur ia tuliskan. Dugaan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Di samping alasan doktrinal bahwa Roh Kudus mengilhami dia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan apa pun, dugaan tersebut juga tidak sesuai dengan konteks. Di ayat 12 Paulus menggunakan ungkapan yang sama, sekalipun kali ini ia mengubah susunannya: “aku, bukan Tuhan katakan...”. Berdasarkan hal ini kita seharusnya menyimpulkan bahwa Paulus memang dari semula bermaksud menyatakan dengan ungkapan seperti di ayat 10 dan 12.
Paulus pasti tidak akan berpikir bahwa pernyataannya di ayat 10 memiliki otoritas yang lebih tinggi dan mengikat dibandingkan yang di ayat 12. Di bagian selanjutnya ia menegaskan bahwa ia memberikan pendapat “sebagai orang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah” (ay. 25). Dia juga adalah orang “yang mempunyai Roh Allah” (ay. 40). Lebih jauh, setiap bagian dari kitab suci adalah diilhamkan Allah sendiri (2Tim 3:16), walaupun yang menuliskan secara langsung adalah manusia pilihan Allah (2Pet 1:20-21).
Apa maksud dari ungkapan di ayat 10a? Paulus sebenarnya sedang menjelaskan sumber dari pernyataannya. Perintah di ayat 10 memang langsung berasal dari Tuhan Yesus (bdk. Mat. 5:32//Luk. 16:16; Mat. 19:9//Mrk. 10:11), sedangkan perintah di ayat 12 merupakan pandangan Paulus sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah berkaitan dengan pasangan campuran, karena isu ini pada jaman-Nya bukanlah isu yang mendesak. Setelah injil menjangkau orang-orang tidak beriman dari bangsa lain, isu ini menjadi mendesak karena sebagian orang non-Kristen tersebut pasangannya akhirnya menjadi percaya. Dari sini terlihat bahwa Paulus sangat berhati-hati dengan tradisi yang di aterima. Kalau itu memang langsung dari Tuhan (bdk. 1Kor. 9:14; 11:23), dia akan menyatakan hal itu. Kalau itu adalah penafsiran dia, maka ia juga memberitahukan hal tersebut.
Maksud lain dari ungkapan ayat 10 berkaitan dengan situasi konkrit yang dialami jemaat. Pada waktu itu mereka menganggap diri rohani dan menerima “pewahyuan Roh Kudus” (bdk. 7:40), sehingga mereka mengklaim bahwa praktik selibasi atau asketisisme yang mereka sedang lakukan adalah dari “Roh Kudus”. Kepada orang-orang seperti ini Paulus menegaskan bahwa ucapan Tuhan Yesus merupakan otoritas tertinggi. Tidak ada pewahyuan dari Ro Kudus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Tradisi ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus dan diajarkan oleh para rasul harus lebih ditaati daripada “wahyu” spektakuler yang sebenarnya bukan dari Roh Kudus (bdk. Kol. 2:7, 18).
Perintah di ayat 10-11 ditujukan pertama kali kepada para istri. Dalam budaya Yahudi hal ini sepertinya tidak akan ditemukan, karena wanita memang tidak memiliki hak untuk menceraikan suaminya. Dalam budaya Yunani-Romawi, baik suami maupun istri bisa mengajukan perceraian. Ketika Paulus menyinggung para istri lebih dahulu, hal ini mungkin tidak lebih daripada sekadar kebiasaan pada waktu itu. Di tempat lain Paulus juga memberikan perintah/nasehat kepada pihak yang lebih lemah/rendah, setelah baru yang lebih kuat/tinggi (Ef. 5:226:9; Kol. 3:18-4:1). Jika kita mengamati pembahasan Paulus di 1 Korintus 7, maka kita akan menemukan bahwa Paulus tidak selalu menyinggung pihak yang lebih rendah lebih dahulu. Ia kadang menasehati suami dulu (ay. 2, 3, 12-13), kadangkala istri (ay. 4, 10-11, 16). Variasi seperti ini memang menyiratkan bahwa Paulus bertindak adil terhadap suami-istri, namun ada kemungkinan lain bahwa sumber masalah di tiap nasehat memang berganti-ganti.
Dalam kasus di ayat 10-11, para penafsir berpendapat bahwa istrilah yang menjadi sumber masalah. Dengan kata lain, istrilah yang menuntut atau mengusahakan perceraian. Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain: (1) istri disinggung pertama kali; (2) porsi pembahasan untuk istri jauh lebih banyak (ay. 10-11a) daripada suami (ay. 11b); (3) istri diperintahkan untuk kembali kepada suami (ay. 11a); ini menyiratkan bahwa upaya menceraikan diri berasal dari istri; (4) sikap para wanita yang tidak tertib dalam ibadah (11:1-16) memberi indikasi pada gerakan feminisme kuno; (5) bapa Eusebius mencatat adanya para wanita spiritual/nabiah dalam gerakan bidat Montanisme abad ke-2 M yang meninggalkan suami mereka. Walaupun kisah ini terlalu jauh dari masa hidup jemaat Korintus (pertengahan abad ke-1 M) dan tidak relevan, namun contoh ini tetap menyiratkan bahwa ada kemungkinan konsep spiritualitas yang salah bisa medorong wanita untuk bercerai dari suaminya.
Isi Perintah (ay. 10b-11)
Paulus memberikan dua perintah yang saling berkaitan. Perintah ini tetap berlaku untuk suami-istri, walaupun nasehat untuk suami hanya disebut secara sambil lalu saja oleh Paulus (ay. 11b).
Jangan bercerai (ay. 10b)
Paulus melarang para istri untuk menceraikan (chōrizō) suami mereka. Secara hurufiah kata ini memiliki arti “meninggalkan” (KJV/NASB) atau “memisahkan diri” (NIV/RSV).
Berdasarkan hal ini, beberapa penafsir mencoba membedakan antara kata cwrizw di ayat 10b dengan kata afihmi di ayat 11b. Chōrizō dianggap perceraian tidak resmi (sekadar pisah rumah), sedangkan afihmi disertai dokumen resmi.
Pembedaan di atas tampaknya terlalu dipaksakan. Kata afihmi juga dipakai Paulus untuk istri (ay. 13). Di ayat 15 kata chōrizō dikenakan pada suami maupun istri (bdk. Mat. 19:6//Mrk. 10:9). Selain itu, proses perceraian dalam budaya kuno tidak seformal sekarang. Dalam beberapa konteks, tidak bersetubuh dengan pasangan sudah dianggap “bercerai” sekalipun tidak disertai dengan proses hukum maupun dokumen resmi.
Dalam bagian ini Paulus tidak memberikan alasan apa pun di balik larangan untuk bercerai. Ketidakadaan keterangan ini mengasumsikan bahwa jemaat Korintus sudah mengetahui alasan di baliknya. Hal ini pasti merujuk ada suatu kebenaran yang sudah sangat populer. Paulus sangat mungkin memikirkan ajaran Yesus (Mat. 19:1-12//Mrk. 10:1-12) yang juga sudah dikenal dengan baik oleh jemaat Korintus. Dalam teks ini Yesus menyandarkan larangan perceraian pada rencana awal Allah untuk perkawinan. Perkawinan dirancang supaya dua menjadi satu (Kej 2:24). Allah dari dahulu tidak pernah berkompromi dengan perceraian (Mal. 2:16a). Kalaupun Allah memerintahkan Musa untuk memberikan surat cerai, hal itu dilakukan karena ketegaran hati bangsa Yahudi (Mat. 19:8//Mrk. 10:5).
Jika dilihat dari situasi konkrit jemaat Korintus, larangan untuk bercerai ini merupakan larangan yang luar biasa keras. Alasan yang dipakai oleh jemaat Korintus adalah “kerohanian”. Walaupun mereka memiliki konsep spiritualitas yang salah, tetapi mereka berani bercerai untuk mencapai “tingkat kerohanian yang lebih tinggi”. Kalau untuk alasan “rohani” saja Paulus melarang perceraian, apalagi untuk sekadar alasan-alasan klise seperti tidak cocok, tidak bisa menafkahi, dsb. Kalau untuk saling menjauhi dalam waktu yang tidak tertentu saja dilarang (1Kor. 7:5), apalagi bercerai.
Jangan kawin lagi (ay. 11)
Apakah kata “jikalau” di awal ayat 11 menunjukkan suatu tindakan yang mungkin terjadi atau tidak? Dari tata bahasa Yunani yang dipakai, tindakan yang diasumsikan bisa saja terjadi. Dari sisi konteks, hal ini tampaknya juga sangat mungkin terjadi. Perceraian adalah rencana ideal Allah, namun orang percaya sering kali gagal menaatinya. Jika beberapa orang sudah terlanjur melakukan hal itu, Paulus memberikan nasehat khusus agar situasi mereka tidak menjadi lebih buruk. Pola seperti ini mirip dengan pada jaman Musa. Sekalipun dilarang bercerai, bangsa Israel tetap melakukan hal itu. Supaya para mantan istri tidak diperlakukan lebih sengsara lagi (status mereka terkatung-katung), mereka harus diberikan surat cerai. Jadi, 1 Korintus 7:11 bukanlah bentuk kompromi, tetapi cara pencegahan terhadap dosa lainnya lagi.
Kepada mereka yang bercerai, Paulus memberikan dua alternatif: tetap sendiri atau rujuk dengan suami. Alternatif pertama jelas didasarkan pada pertimbangan dosa perzinahan. Jika seseorang menikah dengan orang yang bercerai, maka keduanya melakukan perzinahan (bdk. Mat. 19:9//Mrk. 10:11-12). Dalam kasus jemaat Korintus, keputusan untuk bercerai sudah merupakan dosa, karena itu mereka tidak boleh menambahi lagi dengan dosa yang lain. Jika dilihat dari larangan Paulus kepada jemaat untuk saling menjauhkan diri (ay. 2-5) maupun bercerai (ay. 10), perintah untuk tetap hidup sendiri ini merupakan sesuai yang menarik. Hdup sendiri untuk kepentingan “kerohanian” adalah dilarang, sebaliknya hidup sendiri setelah perceraian adalah keharusan.
Menariknya, Paulus memberikan alternatif untuk rujuk dengan mantan suami. Hal ini tidak dikategorikan sebagai perzinahan. Mengapa? Di mata Paulus, pernikahan merupakan komitmen seumur hidup sampai salah satu meninggal dunia. Selama keduanya masih hidup maka pernikahan masih mengikat (Rm. 7:1-3). Dengan dasar pertimbangan ini, menikah kembali dengan mantan suami bukanlah perzinahan, karena keduanya memang disatukan untuk seumur hidup.
Walaupun dua alternatif di atas sekilas tampak berupa pilihan eksklusif (pilih satu atau yang lainnya), namun bukan itu maksud Paulus. Keduanya saling berkaitan. Perintah untuk tidak kawin dimaksudkan agar keduanya masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali. Jika salah satu sudah menikah lagi dengan orang lain, maka rujuk menjadi tidak mungkin. Dalam tradisi Yahudi, seorang istri yang sudah kawin atau berzinah dengan laki-laki lain tidak boleh kembali pada suaminya lagi. Ulangan 24:4 “maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN”. Salah satu contoh tentang budaya ini adalah istri-istri Daud yang sudah dicemari oleh Absalom (2Sam. 16:21-22). Daud tidak lagi bersetubuh dengan mereka. Mereka diperlakukan ibarat janda (2Sam. 20:3).
Dari dua alternatif yang diberikan Paulus tampaknya mengantisipasi kalau para istri sadar terhadap konsep mereka yang salah dan kembali lagi kepada suami mereka. Dengan kata lain, Paulus mengharapkan pertobatan mereka. Dia juga mengantisipasi dalam kesendirian mereka, mereka rentan terhadap dosa percabulan (bdk. ay. 2, 5).
Di akhir ayat 11 Paulus mengaplikasikan perintah di ayat 10-11a kepada suami, tetapi kali ini tidak secara panjang lebar. Hal ini menyiratkan bahwa pihak suami bukanlah sumber perceraian. Hal ini juga membuktikan bahwa sekalipun perceraian merupakan hal yang umum dalam masyarakat Yahudi maupun Yunani, dalam kehidupan gereja hal tersebut merupakan hal yang tidak biasa. Perceraian dilarang, apalagi kawin lagi. Betapa Alkitab sangat menekankan keutuhan keluarga Kristiani! Amin. #
Sumber:
Mimbar GKRI Exodus, 26 April 2009
http://www.gkri-exodus.org/image-upload/1Korintus%2007%20ayat%2010-11.pdf