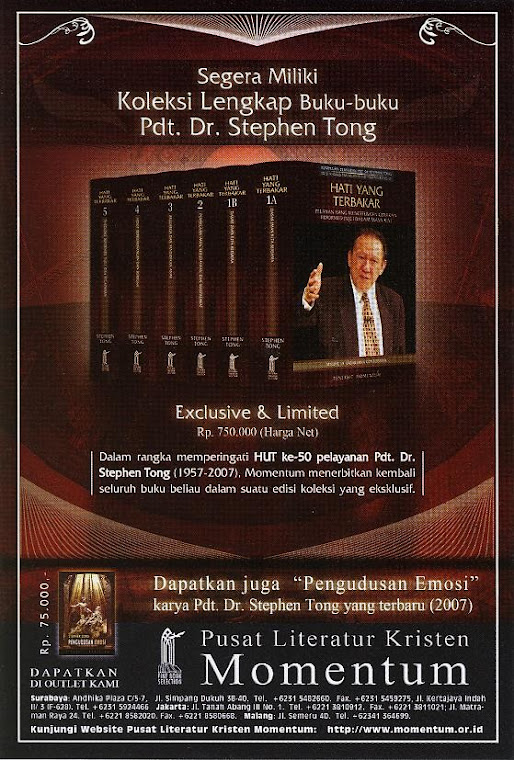oleh: Ev. Pancha Wiguna Yahya, M.Th.
Since the death of the godlike Author, any number of idols have been erected in His place under the names of our diverse theoretical schools as the ultimate reference of literature and resting point of this study. Each of these schools promises its own version of salvation through correct interpretation in a grounder, and by that token valid, reading of texts
—Howard Felerpin2
PROLOG
“There is a spectre haunting classical Christianity, that of postmodernism,” demikian R. Albert Mohler, Jr. mengawali artikelnya yang dimuat dalam sebuah antologi yang bertemakan “tantangan pascamodernisme bagi Kekristenan Injili.”3 Pendapat Mohler tersebut adalah sebuah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa pengaruh (negatif) pascamodernisme merupakan ancaman bagi Kekristenan, termasuk di dalam ranah hermeneutika.4 Menurut Roy B. Zuck, hermeneutika adalah “sains sekaligus seni”dalam menafsir Alkitab.5 Hermeneutika, di satu sisi adalah sains karena ia adalah teknik menafsir Alkitab dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu,6 di sisi lain ia juga adalah seni karena melibatkan imajinasi dan perasaan penafsir, serta membutuhkan keterampilan penafsir untuk menerapkan kaidah-kaidah penafsiran tersebut.7 Namun, hermeneutika tidak berhenti pada teknik menafsir Alkitab; hermeneutika juga harus mengaplikasikan hasil penafsiran tersebut pada situasi kontemporer.8
Selain sains dan seni, Osborne menambahkan satu unsur lagi dalam hermeneutika, yaitu tindakan spiritual (spiritual act karena menurutnya, penafsiran Alkitab dilakukan di bawah pimpinan Roh Kudus).9 Sehubungan dengan adanya pengaruh pascamodernisme terhadap hermeneutika biblika, artikel ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: (1) Apa saja dan sejauh mana pengaruh (negatif) pascamodernisme terhadap hermeneutika? (2) Bagaimana seharusnya kita menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut? (3) Apakah pascamodernisme hanya berdampak negatif? Adakah sumbangsih positif dari pascamodernisme bagi hermeneutika biblika?
KARAKTERISTIK PASCAMODERNISME YANG MEMENGARUHI HERMENEUTIKA BIBLIKA
Mendefinisikan pascamodernisme tidaklah mudah karena tidak seragamnya para ahli dalam mendefinisikannya. Beberapa definisi atas pascamodernisme yang pernah ditawarkan antara lain:
Jean Francois Lyotard menyebutnya “akhir dari narasi-narasi besar”atau “ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar;”Fredric Jameson, “upaya untuk mengatur suhu zaman tanpa alat bantu dan dalam situasi di mana kita bahkan tidak yakin lagi adanya sesuatu yang begitu koheren sebagai suatu ‘zaman’ atau Zeitgeist (‘semangat zaman’) atau ‘sistem’ atau ‘situasi masa kini’”; Terry Eagleton, “ragam gaya hidup dan permainan bahasa yang heterogen yang menyudahi nostalgia desakan untuk mentotalkan [sic] serta mengesahkan dirinya sendiri;”atau Richard Bernstein, “suatu serangan melawan humanism serta legasi pencerahan.”10
Selain itu, kalangan pascamodern sendiri menolak untuk mendefinisikan pascamodernisme secara bulat, utuh, dan monolitik karena justru pengertian semacam itulah yang ditolak oleh pascamodernisme.11 Secara garis besar, ragam definisi pascamodernisme dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang mendefinisikan pascamodernisme sebagai sebuah periodisasi yang terjadi setelah masa modern.12 Sedangkan kelompok kedua memandang pascamodernisme sebagai produk budaya yang menolak, menyempurnakan, merevolusi, atau mendekonstruksi modernisme.
Dari sekian banyak karakteristik pascamodernisme, penulis hanya memilih tiga karakteristik yang paling berpengaruh terhadap hermeneutika biblika. Tiga karakteristik itu adalah: (1) Tiadanya kebenaran objektif; (2) Permasalahan bahasa: dari prastrukturalisme ke pascastrukturalisme; (3) Matinya sang pengarang: dari makna pengarang menuju makna pembaca.13
Tiadanya Kebenaran Objektif
Bangkitnya modernisme diinspirasikan oleh Rene Descartes yang melalui wawasan humanismenya menjadikan manusia—dengan segala kemampuan rasionya—pusat dan tolok ukur alam semesta. Kemudian filsafat Descartes dikokohkan oleh gerakan Pencerahan (Enlightenment/Aufklärung) di mana sains mendominasi umat manusia. Pada saat itu, berkembang filsafat positivisme yang memiliki keyakinan akan adanya fakta yang objektif, dan juga semua fakta dapat dijelaskan dan diuji melalui teori yang objektif.14 Yang dimaksud dengan objektif di sini adalah memiliki realitas dan validitas yang extra-mental, yaitu realitas dan validitas yang berlaku secara universal bagi semua orang—tidak peduli apakah orang itu menganggapnya sebagai kebenaran atau tidak—dan melintasi ruang dan waktu.15 Selain keobjektifan ilmu pengetahuan dan kebenaran, hal lain yang menandai zaman modern adalah keyakinan yang kokoh akan kebaikan (goodness) dan kepastian (certainty) rasio manusia dan ilmu pengetahuan.16
Di pihak lain, pascamodernisme menolak kebenaran objektif yang diagungkan oleh modernisme. Bagi penganut pascamodernisme, tidak ada satu pun kebenaran yang objektif; sebaliknya semua kebenaran hanya partikular, terbatas, dan insuler.17 Menurut Carson, Immanuel Kant dalam tulisannya yang berjudul The Critique of Pure Reason telah menjadi benih bagi tumbuhnya pascamodernisme.18 Dalam tulisan itu Kant menyatakan bahwa diri (self) tidak dapat menemukan secara objektif apa yang ada di dalam dunia, tetapi sebaliknya “projects order creatively uponthe world.”19 Penolakan pascamodernisme atas adanya kebenaran yang absolut dan objektif menjadi ancaman serius bagi Kekristenan, secara khusus bagi otoritas Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen golongan Injili sebagai tulisan yang diinspirasikan Allah.20 Jika penganut pascamodernisme mengklaim tidak ada kebenaran yang objektif, maka dengan sendirinya otoritas Alkitab yang universal atas diri pemercaya Kristen tidak diakui.
Lalu, apa dampak hal itu bagi hermeneutika biblika? Seperti yang telah dijelaskan pada bagian prolog, tugas hermeneutika tidak sekadar menemukan makna teks Alkitab tetapi lebih jauh lagi ia harus mengaplikasikan makna (baca: kebenaran) itu dalam kehidupan pembacanya. Jika kebenaran Alkitab tidak dianggap absolut, maka—sama dengan karya sastra lain atau buku sejarah—pengaplikasian kebenaran Alkitab bukanlah hal yang mutlak. Dengan demikian, maka hermeneutika telah gagal dalam melaksanakan tugasnya.
Pengaruh lain dari tiadanya kebenaran yang objektif adalah terciptanya subjektivisme dalam penafsiran Alkitab. Jika kebenaran yang objektif disangkal, maka semua hasil tafsir adalah benar dan sah, meskipun berbeda satu sama lain bahkan saling bertolak belakang.21 Iklim subjektivisme itu akan menyuburkan penafsiran-penafsiran “ngawur,”dan tak jarang penafsiran Alkitab yang anarkis, yaitu “pemerkosaan”makna (yang dimaksud) penafsir terhadap makna (yang dimaksud) penulis Alkitab.22
Permasalahan Bahasa: Dari Prastrukturalisme ke Pascastrukturalisme
Menurut Sugiharto, saat ini filsafat sedang mengalami pembalikan ke arah bahasa (lingistic turn). Sekitar seratus tahun yang lalu, istilah kunci dalam filsafat adalah “akal,”“Roh,”“pengalaman,”dan “kesadaran.”Kini, istilah kunci itu adalah “bahasa.”23 Seorang tokoh yang memberikan pengertian baru dalam bidang linguistik adalah Ferdinand de Saussure (1857-1913). Saussure tidak menyetujui pandangan umum pada masanya, yang mengatakan bahwa bahasa harus dipandang secara historis. Pada masa itu, studi tentang bahasa menekankan perilaku linguistik actual (perkataan manusia; yang disebut Saussure sebagai parole), yaitu sebuah usaha untuk menelusuri perkembangan kata-kata dan ekspresi dengan meneliti pengaruh geografi, migrasi, pergerakan populasi dan hal-hal eksternal lainnya.24 Namun, Saussure menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan antihistoris yang memandang bahasa sebagai sebuah sistem yang koheren secara internal (yang disebutnya langue).25
Pandangannya ini disebut dengan strukturalisme karena menekankan struktur bahasa ketimbang perkembangan historis sebuah bahasa. Oleh sebab itu, teori Saussure disebut bersifat sinkronis (ahistoris, menekankan pada literary) yang berbeda dengan sifat diakronis (historis, menekankan pada perkembangan bahasa).26 Pandangan Saussure tersebut memberikan pengaruh terhadap lahirnya kritik sastra (literary criticism), yaitu: metode penafsiran yang memfokuskan pada penelitian sastra tanpa memusingkan masalah-masalah historis seperti: identitas penulis, keadaan sosial budaya penulisan Alkitab, pembaca pertama dan sebagainya.
Macam-macam kritik sastra antara lain kritik naratif (narrative criticism)27 dan kritik retorik (rhetorical criticism).28 Strukturalisme dengan sifat antihistorisnya telah membuka jalan munculnya pandangan yang disebut pascastrukturalisme. Pandangan pascastrukturalisme ini diusung oleh sejumlah pemikir kontemporer Perancis seperti: Roland Barthes (1915-1980), Michael Foucault (1926-1984), Pierre-Félix Guattari (1903-1992), Julia Kristeva (1941- ), dan Jacques Derrida (1930-2004). Para pemikir ini memiliki pandangan yang berlawanan dengan yang diyakini oleh strukturalisme. Bila strukturalisme berpandangan sistem bahasa itu stabil, bagi mereka justru sistem bahasa itu sangat labil.29 Berkenaan dengan itu, Derrida menyatakan bahwa kestabilan stuktur sistem bahasa seperti yang dinyatakan oleh strukturalisme adalah upaya untuk mengontrol dan mereduksi fenomena ke dalam sistem yang baku; padahal menurutnya, bahasa tidak dapat direduksi dan dibakukan karena selalu terbuka kemungkinan-kemungkinan yang baru.30 Pembatasan teks oleh struktur yang baku merupakan contradictio in terminis dengan watak teks yang terbuka dan jalin menjalin.
“Teks”berakar dari bahasa Latin textus, yang berarti kain (tissu) dan kata texere yang berarti rajutan (tisser). Dengan demikian, teks pada prinsipnya selalu bersifat intertekstual dan saling berjalin dengan teks-teks lain di dalam proses yang tidak kunjung usai.31 Kritik lain Derrida atas strukturalisme adalah strukturalisme masih dipengaruhi logosentrisme filsafat modern. Yang dimaksud dengan logosentrisme ialah “the general assumption that there is a realm of ‘truth’ existing prior to and independent of its representation by linguistic signs.”32 Para filsuf modern meyakini bahwa suatu bahasa ada untuk menandai (to signify) dan mewakili logosentrisme itu.33 Namun, bagi Derrida logosentrisme tidak ada karena tidak ada sesuatu pun yang menjadi dasar sistem pikiran dan bahasa manusia.34 Oleh sebab itu, dibanding menelusuri logosentrisme di balik suatu teks, Derrida lebih memilih mendekonstruksi teks. Dekonstruksi, yang merupakan ciri khas penafsiran pascamodern, adalah “usaha untuk membongkar teks demi menemukan kontradiksi-kontradiksi yang inheren di dalam teks, lalu membiarkan teks itu centang-perenang sehingga tidak dimungkinkan untuk dibangun kembali.”35 Coba bayangkan, apa yang akan terjadi bila dekonstruksi dipraktikkan dalam penafsiran Alkitab? Selain dekonstruksi menghancurkan otoritas Alkitab, cara penafsiran seperti ini akan membuat Alkitab kehilangan maknanya karena semua teksnya telah dibongkar habis.36
Matinya Sang Pengarang: Dari Makna Pengarang Menuju Makna Pembaca
Julukan bapak penafsiran modern dikenakan pada diri Friedrich Schleiermacher (1768-1834) atas jasanya dalam merumuskan metodologi penafsiran yang baku.37 Menurutnya, penafsiran Alkitab tidak cukup dilakukan hanya melalui penyelidikan grammatika, melainkan juga penafsiran psikologis atas diri pengarang. Penafsiran psikologis tersebut dilakukan melalui intuisi, imajinasi, dan empati penafsir atas pengalaman hidup pengarang.38 Dengan melakukan baik penyelidikan grammatika maupun penafsiran psikologis pengarang, menurutnya, niscaya penafsir akan menemukan makna yang dimaksud pengarang bahkan lebih lengkap dari yang dimiliki pengarang.39
Pandangan Scheiermacher itu diteruskan dan disempurnakan oleh penulis biografinya, Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dilthey berpandangan bahwa melalui ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften), yang memiliki wilayah studi yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam (Naturwissenschaften), seorang penafsir mungkin memahami kehidupan dan pengalaman pengarang.40 Pemahaman akan kehidupan dan pengalaman pengarang itu mungkin dimiliki oleh penafsir, karena menurutnya terdapat “keterhubungan hidup”(the connected of life) antar umat manusia di segala tempat dan zaman.41 Schleiermacher beserta Dilthey telah berhasil meletakkan dasar bagi metode kritik historis (historical criticism)—meliputi kritik sumber (source criticism), kritik bentuk (form criticism) dan kritik redaksi (redactional criticism)—yang bertujuan mencari makna yang dimaksudkan oleh pengarang.42
Pada tahun 1960 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) menerbitkan magnum opus-nya, Wahrheit und Methode (Truth and Method). Dalam buku itu, ia merevisi pengertian hermeneutika seperti yang telah dijelaskan oleh Schleiermacher. Baginya, hermeneutika bukanlah sebuah proses mekanis melainkan suatu pekerjaan seni sehingga tidak dapat menghasilkan kebenaran objektif seperti yang dihasilkan oleh penelitian ilmiah.43 Bertentangan dengan Schleiermacher, ia menyangkal adanya kemungkinan penafsir untuk dapat memahami pikiran dan maksud pengarang maupun sejarah masa lampau mengingat di antaranya terbentang jarak waktu dan budaya yang lebar.44 Gadamer juga menentang pendapat Dilthey yang mengklaim adanya prinsip yang objektif untuk dapat memahami pengalaman orang lain pada masa lampau.45
Pandangan Gadamer itu telah memicu tumbuhnya penafsiran yang berorientasi pada teks, seperti yang dipelopori oleh seorang filsuf Perancis bernama Paul Ricoeur (1913-2005). Ricoeur beranggapan bahwa teks itu bukanlah sebuah sistem yang bersifat tertutup, melainkan bersifat otonom. Artinya, teks memiliki hidupnya sendiri yang terlepas dari diri sang pengarang, sehingga teks terbuka akan kemungkinan dibaca lebih luas sesuai dengan konteks pembacanya. Ricoeur menyatakan bahwa menafsir adalah pertama-tama melakukan dekontekstualisasi, yaitu proses membebaskan teks dari konteks pengarangnya dan dilanjutkan dengan rekontekstualisasi, yaitu: proses memasukkan teks ke dalam konteks pembacanya.46 Pemikiran Ricoeur ditambah dengan strukturalisme ala Saussure telah menyuburkan metode kritik sastra (literary criticism). Rupanya, pendulum hermeneutika tidak berhenti pada penafsiran yang berpusat pada makna teks, namun telah bergerak kepada penafsiran yang berpusat pada pembaca. Salah satu bentuk penafsiran semacam ini adalah kritik respons-pembaca (reader-response criticism) yang dipelopori oleh Stanley Fish (1938- ) dan Wolfgang Iser (1926- ). Asumsi dasar dari kritik respons-pembaca ialah teks tidak pernah lengkap dan hidup sebelum dilengkapi dan dihidupkan oleh pembaca. Menurut mereka teks itu sendiri masih merupakan “bahan mentah”yang harus diolah oleh pembaca.47 Secara garis besar metode kritik respons-pembaca dibagi menjadi dua, yaitu: yang konservatif dan yang radikal. Kritik respons pembaca yang konservatif berpandangan bahwa tugas penafsir adalah menemukan makna dengan mengisi “lubang-lubang”yang terdapat pada teks dengan makna mereka sendiri.48 Sedang kritik respons-pembaca yang radikal menolak adanya makna normatif yang dimaksudkan pengarang sehingga pembaca berhak mengisi teks dengan makna mereka sendiri. Kritik respons-pembaca ini, terlebih yang radikal, akan menghasilkan subjektivisme yang liar. Semangat pascamodernisme yang menjiwai kritik respons-pembaca ini membuka peluang bagi berbagai kritik ideologis (ideological criticism), seperti kritik feminis (feminist criticism), kritik theologi hitam (black theology criticism), kritik pembebasan (liberation criticism) atau kritik homoseksual (gay criticism).49
Kritik ideologis sangat bersifat subjektif karena ia tidak berusaha mencari makna yang dimaksud pengarang, namun sebaliknya memasukkan ideologi atau theologi yang dimiliki penafsir ke dalam penafsiran, seperti yang ditulis Kwok Pui Lan, seorang tokoh feminis Asia,
Since I reject both the sacrality of the text and the canon as a guarantee of truth, I also do not think that Bible provides the norm for interpretation in itself. For a long time, such “mystified”doctrine has taken away the power from women, the poor and the powerless, for it helps to sustain the notion that the “divine presence”is located somewhere else and not in ourselves. Today, we must claim back the power to look at the Bible with our own eyes and to stress that divine immanence is within us, not in something sealed off and handed down from almost two thousand years ago.50
Subjektivisme metode penafsiran pascamodernisme mencapai puncaknya dalam metode dekonstruksi yang “diilhami”oleh filsafat dekonstruksi Derrida. Metode penafsiran dekonstruksi melakukan pembongkaran atas teks Alkitab dengan mencari kontradiksi-kontradiksi di dalam dirinya sendiri maupun dengan pemahaman dan pengalaman penafsir, sehingga tidak jarang penafsiran dekonstruktif justru mempersalahkan teks-teks Alkitab ketimbang mencari makna yang terkandung di dalamnya dan mengaplikasikan makna tersebut.51
TANGGAPAN
Kritik utama atas hermeneutika biblika yang dipengaruhi pascamodernisme adalah penafsiran ini sangat kental dengan subjektivisme, karena menurut mereka setiap penafsir sah untuk memasukkan maknanya sendiri dalam proses hermeneutika. Subjektivitas semacam itu tidak dapat diterima. Seorang penafsir tidak diperkenankan memasukkan maknanya sendiri, melainkan ia harus berusaha menemukan makna yang dimaksud penulis Alkitab. Menurut Vanhoozer, maksud penulis adalah penyebab terciptanya sebuah teks. Teks itu sendiri tidak pernah berdiri sendiri, melainkan ia hanya “dipinjam”oleh penulis untuk menyampaikan maksudnya.52 Oleh sebab itu, penafsiran yang benar adalah penafsiran yang bertujuan menemukan makna yang dimaksud oleh pengarang, seperti yang diucapkan E. D. Hirsch, “All valid interpretation, of every sort, is founded on the recognition of what an author meant.”53
Lebih lanjut, kita meyakini bahwa Allah adalah Penulis Utama di balik para penulis Alkitab. Allah, dalam keMahatahuan dan keMahakuasaan-Nya, telah menginspirasikan para penulis Alkitab untuk memilih kata-kata tertentu sehingga kebenaran-kebenaran-Nya dapat terkomunikasikan dengan baik (2Tim. 3:16). Tentu saja kita yang berdosa dan terbatas ini mungkin saja salah dalam mengerti Alkitab, namun Alkitab itu sendiri tetaplah objektif, seperti yang ditulis oleh Carson,
Of course, we will misunderstand the communication in all sorts of ways, owing both to our finiteness and to our sinfulness. But the content itself is objectively true, a subset of what Omniscience knows, and cast in culture-laden forms that demand of modern reader that we attempt to fuse the horizon of our understanding with that of the culture and language in which the deposit was given. Moreover, this God not only knows perfectly and in advance what wrong interpretation mortals will assign his words, he also knows that some later mortal will see true connections (meanings) in the complex of his words. . . .54
Kelemahan kedua dari hermeneutika yang dipengaruhi faham pascamodernisme adalah sifatnya yang ahistoris bahkan antihistoris. Padahal, Alkitab bukanlah karya sastra biasa—semacam buku fiksi atau sebuah antologi puisi—melainkan Alkitab menceritakan sejarah umat Allah yang bergumul dalam melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka. Jadi, tugas hermeneutika pertama-tama adalah melakukan penelitian sejarah terhadap teks Alkitab (identitas penulis, latar belakang zaman penulis, keadaan pembaca pertama) di samping melakukan penelitian sastra (literary) untuk, sedapat mungkin, menemukan makna yang dimaksud pengarang.55
Selain memiliki kelemahan, pascamodernisme memberikan sumbangsih kepada hermeneutika. Paling sedikit ada dua sumbangsih; pertama, pascamodernisme “mengajar”kita untuk memperhatikan konteks pembaca dalam melakukan penafsiran Alkitab. Pada satu pihak, pascamodernisme terlalu menekankan konteks pembaca dan mengabaikan konteks pengarang sehingga melahirkan penafsiran Alkitab yang anarkis, di pihak lain sebagian penafsir kadangkala kurang “membumi”dalam mengaplikasikan makna (baca: kebenaran) Alkitab ke dalam konteks pembaca sehingga kebenaran Alkitab dirasakan di awang-awang.
Kedua, pascamodernisme “menyadarkan”kita bahwa praanggapan (presupposition) seorang penafsir pasti memengaruhi proses hermeneutika. Berkaitan dengan hal itu, Robertson McQuilkin dan Bradford Mullen menulis demikian:
Apart from these basic disagreement with postmodern thinking, however, we recognize some legitimate contributions to evangelical thinking, primarily in alerting us to issues that we have not sufficiently addressed. Postmodern perspectives have sensitized us to the difficulty of verbal communication, alerted us to nearly imperceptible influence of preunderstanding....56
Berkaitan hal tersebut, Graham N. Stanton menyatakan hal yang benar bahwa “Even a master of historical method is not able to remain completely free from the prejudice of his time, his social environment, his national position etc.”57
Bagi pemikir pascamodernisme, praanggapan penafsir memiliki peran yang penting, kalau tidak dikatakan yang paling utama, dalam hermeneutika. Menurut mereka, karena sang pengarang telah mati, maka setiap penafsir memiliki hak yang sama untuk memaknai teks menurut praanggapan mereka masing-masing.58 Bagi kita yang percaya bahwa otoritas Alkitab mutlak dan mengutamakan pencarian makna yang dimaksud oleh para penulis Alkitab, pandangan yang diyakini oleh pascamodernisme itu seharusnya ditolak. Namun ironis, kita sendiri sering terjebak di dalam praktik penafsiran Alkitab subjektif ala pascamodernisme yang sebenarnya kita tolak. Sebagai contoh, betapa seringnya kita mengutip ayat-ayat Alkitab demi melakukan atas pandangan theologis atau pendapat kita (proofing text)?59 Mengenai hal ini Osborne menyatakan pendapatnya:
I might note that a great deal of what the deconstructionist argues actually occurs in some modern preaching and Bible study groups. The tendency has often been to ignore the historical dimension of biblical text and to ask directly, “How does this relate to my situation?”The difference of course that Derrida denies the historical referent while many evangelical merely unaware of it. However, the result (namely, subjective interaction with text) is quite similar.60
Penafsiran yang menafikan makna historis bukanlah eksegesis melainkan eisegesis. Meski kita tidak menyetujui sebagian pandangan Rudolf Bultmann, pendapatnya berikut ini adalah benar, “every exegesis that is guided by dogmatic prejudices does not hear what text says, but only lets the latter says what it want to hear.”61
Jika kita menerima fakta bahwa seorang penafsir tidak mungkin dapat melepaskan diri dari praanggapannya, lalu bagaimana caranya agar kita dapat menafsir Alkitab secara objektif? Menjawab pergumulan itu, ada beberapa rambu yang harus kita patuhi supaya kita tidak terjebak pada subjektivisme buta. Pertama, kita harus sadar bahwa kita menafsir Alkitab dengan praanggapan tertentu.62 Meski praanggapan dapat menjerumuskan penafsir ke dalam jurang subjektivisme, namun sebetulnya praanggapan diperlukan sebagai dasar untuk mengerti Alkitab.63 Untuk itu, kita harus sadar bahwa saat menafsir Alkitab, kita sedang menafsir dengan praanggapan kita, entah itu pemahaman theologis atau pengalaman kita. Kesadaran ini penting untuk menaati rambu yang berikutnya.
Kedua, kita harus selalu terbuka untuk dikoreksi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Osborne menyebut pengoreksian praanggapan penafsir oleh kebenaran-kebenaran secara terus-menerus sebagai spiral hermeneutika.64 Spiral hermeneutika adalah sebuah proses yang terus berputar antara penafsir dan Alkitab. Pertama-tama penafsir membaca Alkitab dengan praanggapan tertentu, namun jika penafsiran itu menghasilkan kebenaran yang berbeda dengan praanggapan penafsir, ia harus bersedia dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Pemahaman yang telah dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan itu kini menjadi praanggapan penafsir yang baru untuk menafsirkan Alkitab begitu seterusnya sehingga secara progresif penafsir mencapai pemahaman yang benar.65
Ketiga, penafsir harus menggunakan alat-alat dan metode tafsir yang tepat. Yang dimaksud dengan alat-alat tafsir adalah segala hal yang dapat membantu penafsir melakukan tugasnya dengan maksimal, seperti kamus bahasa Ibrani dan Yunani, buku tata bahasa Ibrani dan Yunani, konkordansi, kamus Alkitab dan buku-buku latar belakang politik ekonomi- sosial-budaya zaman penulisan Alkitab. 66 Sedang metode penafsiran yang tepat adalah menafsirkan teks Alkitab sesuai dengan genrenya, melakukan penyelidikan bahasa yang ketat, dan menelusuri latar belakang sejarah penulisan Alkitab.67
Keempat, sebagai bagian dari komunitas orang percaya seorang penafsir harus berinteraksi dengan tafsiran-tafsiran lainnya agar hasil penafsiran kita tidak subjektif.68
EPILOG
Setiap zaman—pramodern, modern, dan pascamodern—dengan karakteristiknya masing-masing telah memberikan pengaruh terhadap hermeneutika biblika. Dalam makalah ini telah dibahas bahwa pascamodernisme telah memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk terhadap penafsiran Alkitab, yaitu sifatnya yang ahistoris serta subjektivitas yang anarkis terhadap otoritas kebenaran Alkitab. Namun, di lain pihak pascamodernisme “memaksa”kita untuk memikirkan dengan serius mengenai peran praanggapan dalam penafsiran Alkitab.
Setelah zaman pascamodern ini entah zaman apa lagi yang akan memengaruhi peradaban umat manusia. Namun zaman apa pun tidak akan pernah dapat menggerus otoritas Alkitab, karena kebenaran firman Allah itu kekal seperti diri Allah sendiri, “The authority of the holy Scripture, for which it ought to be believed and obeyed, dependent not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God (who is truth itself), the author thereof.”69
Catatan kaki:
1. Penulis dengan sengaja menggunakan istilah “hermeneutika biblika”dalam artikel ini mengingat hermeneutika dipakai juga secara luas dalam disiplin ilmu lain, seperti: filsafat (mis. lih. Gianni Vattimo, Beyond Interpretation: the Meaning of Hermeneutics for Philosophy [tr. David Webb; Palo Alto: Stanford University Press, 1997]).
2. Beyond Deconstruction: The Uses and Abuses of Literary Theory (Oxford: Clarendon, 1985), hlm. 204.
3. “The Integrity of the Evangelical Tradition and the Challenge of the Postmodern Paradigm”dalam The Challenge of Postmodernism: An Evangelical Engagement (ed., David S. Dockery; Grand Rapids: Baker, 2001), hlm. 67. Dalam buku yang sama, Carl F. Henry menulis sebuah artikel yang berjudul “Postmodernism: The New Spectre?”(ibid., hlm. 34-52). Dalam kaitan ini adalah penting bagi pembaca untuk mengetahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup hakiki antara pascamodernisme dengan pascamodernitas. I. Bambang Sugiharto mendefinisikan pascamodernitas sebagai situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, usangnya negara bangsa, serta penggalian kembali inspirasi-inspirasi tradisi (Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat [Yogyakarta: Kanisius, 1996], hlm. 24). Istilah “pascamodernisme”pertama kali muncul pada tahun 1934 dalam karya sastra yang ditulis oleh Frederico de Oniz yang berjudul Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamericana. Dalam karya itu, de Oniz menuliskan kata “postmodernismo”untuk menunjukkan reaksi terhadap modernisme. Namun, penggunaan yang signifikan terhadap kata itu dilakukan oleh Arnold Tonybee yang pada tahun 1939 menyatakan bahwa masa modern telah berakhir pada tahun 1914, dan era yang bangkit dari puing-puing pengalaman kegalauan akibat Perang Dunia I harus disebut dengan “Post-Modern”(ibid.; bdk. Mohler, “The Integrity”, hlm. 54).
4. Pascamodernisme telah memengaruhi segala lini kehidupan; salah satu buktinya adalah istilah ini tidak hanya dipakai dalam bidang filsafat tetapi juga dalam bidang musik (mis. Cage, Stockhausen, dan Glass), seni rupa (Rauschenberg, Baselitz, Warhol, dan Bacon), fiksi (mis. novel-novel dari Vonnegut, Barth, Pynchon, dan Burroughs), film (Lynch, Greenaway, dan Jarman), drama (teater dari Artaud), kritik sastra (mis. Spanos, Hassan, Sontag, dan Fiedler), antropologi (Clifford, Tyler, dan Marcus), sosiologi (Denzin), dan geografi (Soja) (Sugiharto, Postmodernisme, hlm. 23).
5. Basic Bible Interpretation (Wheaton: Victor, 1991) 19; bdk. Grant R. Osborne, The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation (Downers Grove: InterVarsity, 1991), hlm. 5. Kata “hermeneutika”dari kata Yunani hermēneuō yang berarti “to explain, to interpret, to translate”(William F. Ardnt dan Willbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature [2nd ed.; Chicago: The University of Chicago Press, 1979], hlm. 310).
6. Elliot E. Johnson, Expository Hermeneutics: An Introduction (Grand Rapids: Zondervan, 1990), hlm. 8; Zuck, Basic Bible Interpretation, hlm. 19; William W. Klein, Craig L. Blomberg, dan Robert L. Hubbard Jr., Introduction to Biblical Interpretation (Dallas: Word, 1993) xix, 4, 19, 97; Osborne, The Hermeneutical Spiral 5, 353; Moses Silva dan Walter C. Kaiser Jr., An Introduction to Biblical Hermeneutics: The Search for Meaning (Grand Rapids: Zondervan, 1994) 15; Millard J. Erickson, Evangelical Interpretation (Grand Rapids: Baker, 1993), hlm. 9; Robert L. Thomas, Evangelical Hermeneutics: The New Versus Old (Grand Rapids: Kregel, 2002), hlm. 27.
7. Yohanes Adrie Hartopo, “Catatan Kuliah Isu-Isu Hermeneutika Kekinian”(Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2006); Osborne, The Hermeneutical Spiral, hlm. 5.
8. Ibid. 5, hlm. 265; Gordon D. Fee dan Douglas Stuart, How to Read the Bible for All Its Worth (2nd ed.; Grand Rapids: Zondervan, 1993), hlm. 25; Klein, Introduction, hlm. 18; Dan McCartney dan Charles Clayton, Let the Reader Understand: A Guide to Interpreting and Applying the Bible (Wheaton: Victor, 1994), hlm. 78.
9. The Hermeneutical Spiral, hlm. 5. Sebuah bacaan yang dapat membantu kita untuk mengerti peran Roh Kudus dalam penafsiran Alkitab ditulis oleh Roy B. Zuck, “The Role of the Holy Spirit in Hermeneutics,”Bibliotheca Sacra 141/2 (1984), hlm. 120-129.
10. Nindyo Sasongko, “Tinjauan Terhadap Hermeneutika Tindak-Komunikatif Sebagai Metode Bertheologi Injili yang Hermeneutis di Era Pascamodern”(Skripsi S.Th.; Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2002), hlm. 2-3.
11. Hal itu diungkapkan antara lain oleh Dick Hebdige, “upaya pendefinisian posmodernisme hanya mengundang munculnya masalah-masalah”(dikutip dalam Yasfar Amir Piliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna [Yogyakarta: Jalasutra, 2003], hlm. 101) bdk. Christian Sulistio, “Penerapan Konsep Kebenaran Cornelius Van Til untuk Menghadapi Tantangan Pascamodernisme”(Tesis M.Th.; Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2004), hlm. 1.
12. Yang mendefinisikan demikian misalnya adalah Kristi Siegel, “Introduction to Modern Literary Theory: Literary Trends and Influences,”http://www.kristisiegel.com/theory.htm.
13. Karakteristik pascamodernisme lainnya yang tidak dibahas dalam makalah ini antara lain: anti fondasionalisme, menolak proses, penekanan pada komunitas ketimbang individu, dan melibatkan intuisi (Hartopo, “Catatan Kuliah”).
14. Ernest Gellner, Menolak Posmodernisme: Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 42.
15. D. A. Carson, The Gagging of God: Christianity Confronts Pluralism (Grand Rapids: Zondervan, 1996) 120.
16. Stanley J. Grenz, “Star Trek and the Next Generation: Postmodernism and the Future of Evangelical Theology”dalam The Challenge of Postmodern, hlm. 91.
17. Mohler, “The Integrity of Evangelical Tradition”, hlm. 71.
18. The Gagging of God, hlm. 67.
19. Dikutip dalam ibid.
20. Mohler, “The Integrity of Evangelical Tradition”, hlm. 73.
21. Henry, “Postmodernism: The New Spectre”, hlm. 36.
22. Kevin J. Vanhoozer menyebut penafsiran pascamodern sebagai kekerasan penafsiran (interpretative violence) (Is There Meaning in This Text?: The Bible, The Reader, and the Morality of Literary Knowledge [Grand Rapids: Zondervan, 1998], hlm. 161-162).
23 Postmodernisme 79 bdk. Vanhoozer, Is There Meaning, hlm. 17.
24. Stanley J. Grenz, A Primer on Postmodernism (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), hlm. 115.
25. Ibid.
26. Beberapa prinsip strukturalisme adalah: (1) prinsip struktural, yaitu: bahasa dilihat memiliki relasi struktural di mana tanda dilihat sebagai kesatuan yang bersifat material; (2) prinsip kesatuan, yaitu: penanda (signifier)—yaitu: suara, tulisan, gambar, objek—tidak dapat dipisahkan dengan petanda (signified), yaitu: konsep, ide, gagasan, makna; (3) prinsip konvensional, yaitu relasi struktural antara penanda dan petanda sangat bergantung pada konvensi, yaitu: kesepakatan sosial di antara komunitas bahasa; (4) prinsip sinkronik, yaitu: kajian tanda sebagai suatu sistem yang tetap pada konteks waktu dianggap konstan, stabil dan tidak berubah; (5) prinsip representasi, yaitu: hubungan antara penanda dan petanda bersifat mewakili. Dengan kata lain, keberadaan penanda sangat bergantung pada realitas. Dalam hal ini realitas mendahului penanda; ketiadaan realitas berakibat logis pada ketiadaan tanda; (6) prinsip kontinuitas, yaitu: relasi struktural penanda dan petanda selalu berlanjut dan tidak pernah berubah, sehingga di dalamnya tidak dimungkinkan adanya perubahan radikal (Piliang, Hipersemiotika, hlm. 47-49).
27. Secara garis besar kritik naratif adalah penafsiran Alkitab dengan melakukan sebuah “pembacaan yang cermat”(close reading) terhadap teks Alkitab dengan memperhatikan kaidah-kaidah penceritaan, tanpa melakukan pendekatan historis. Secara umum kaidah-kaidah tersebut menyangkut dua hal, yaitu: isi cerita dan cara penyampaian cerita. Yang dimaksud dengan isi cerita antara lain: (1) tokoh; (2) alur cerita; (3) adegan; (4) latar (setting): tempat, waktu, dan suasana. Sedangkan cerita disampaikan dengan cara: (1) pengulangan; (2) pemelukan (inklusio); (3) kesejajaran; (4) rujukan pada Perjanjian Lama; (5) nubuatan; (6) ringkasan; (7) kontras. Untuk mengerti metode kritik ini secara mendetail dapat membaca beberapa tulisan berikut: Armand Barus, “Analisis Naratif: Apa dan Bagaimana?,”Forum Biblika 9 (1999) 48-60; Adji A. Sutama, Mengapa Kamu Menengadah ke Langit?: Analisis Naratif Kisah Kenaikan Yesus (Jakarta: Gunung Mulia, 2001); Adji A. Sutama, “Hermeneutik Kritik Naratif dan Posmodernisme,”Penuntun 3/20 (2004), hlm. 365-381; Osborne, The Hermeneutical Spiral, hlm. 153-173; E. Gerrit Singgih, “Apa dan Mengapa Exegese Naratif?,”Gema 45 (1993), hlm. 5-26; Steven L. McKenzie dan Stephen R. Haynes, eds., To It’s Own Meaning: A Introduction to Biblical Criticisms and Their Application (rev. & ed.; Lousville: Westminster: John Knox, 1999), hlm. 201-229.
28. Kritik retorik adalah metode penafsiran dengan membaca Alkitab secara cermat (close reading) dengan memperhatikan struktur dan substansi teks serta gaya penulisan, kebanyakan digunakan untuk menafsirkan surat-surat. Penjelasan lebih dalam mengenai kritik retorik dapat dibaca dalam ibid., hlm. 156-180; Duane F. Watson dan Alan J. Hauser, Rhetorical Criticism of the Bible: A Comprehensive Bibliography with Notes on History Method (Leiden: E. J. Brill, 1994); George A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism (Cape Hill: University of North Carolina Press, 1987).
29. Vanhoozer, Is There, hlm. 150.
30. Muhammad Al-Fayyadl, Derrida (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 63.
31. Ibid., hlm. 64, 68.
32. “Deconstruction”dalam Encyclopædia Britannica 2005 [CD ROM] (Chicago: Encyclopædia Britannica Inc., 2005). Dalam tulisan-tulisan filsafat logosentrisme itu adalah sang pengarang sebagai subjek yang memiliki otoritas terhadap makna yang hendak disampaikannya (Al-Fayyadl, Derrida, hlm. 16).
33. Grenz, A Primer, hlm. 141.
34. Ibid., hlm. 142.
35. Al-Fayyadl, Derrida, hlm. 21; bdk. dengan definisi berikut ini, “to deconstruct is to explore the tensions and contradictions between the hierarchical ordering assumed (and sometimes explicitly asserted) in the text and other aspects of the text's meaning, especially those that are indirect or implicit or that rely on figurative or performative uses of language”(“Denconstruction”dalam Britannica).
36. Yasraf Amir Piliang menyatakan bahwa penafisiran pascamodernisme yang dekonstruktif akan menghasilkan “diseminasi” yakni keadaan kehampaan makna (Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan [Yogyakarta: Jalasutra, 2004], hlm. 268-269).
37. Hartopo, “Catatan Kuliah.” Meski demikian, menurut Anthony Thiselton, Schleiermacher bukanlah orang pertama yang memikirkan metodologi hermeneutika. Sebelumnya, telah ada orang-orang yang menggumulkan hal tersebut, seperti Origenes dan Irenaeus (lih. “Biblical Studies and Theoritical Hermeneutics”dalam The Cambridge Companion to Biblical Interpretation [ed. John Barton; Cambridge: Cambridge University Press, 1998], hlm. 96).
38. David S. Dockery, Biblical Interpretation Then and Now: Contemporary Hermeneutics in the Light of the Early Church (Grand Rapids: Baker, 1992), hlm. 163.
39. Ibid.
40. E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 50-51.
41. Ibid., hlm. 62.
42. Penjelasan yang mendalam mengenai kritik historis dapat dilihat dalam Roy A. Harrisville dan Walter Sundberg, The Bible in Modern Culture: Theology and Historical-Critical Method from Spinoza to Käsemann (Grand Rapids: Eerdmans, 1992); Edgar Krentz, The Historical-Critical Method (Philadelphia: Fortress, 1975). Sedangkan tanggapan atas metode ini dari kubu Injili dapat dilihat dalam Grant R. Osborne, “Historical Criticism and The Evangelical,”Journal of the Evangelical Theological Society 42/2 (Juni 1999), hlm. 193-210. Pemaparan kelemahan-kelemahan metode kritik historis secara ekstensif dilihat dalam tiga karya Eta Linneman, Historical Criticism of the Bible: Methodology or Ideology? Reflections of a Bultmannian Turned Evangelical (Grand Rapids: Baker, 1990); Is There A Synoptic Problem?: Rethinking the Literary Dependence of the First Three Gospels (Grand Rapids, Baker, 1992); Biblical Criticism on Trial: How Scientific Is "Scientific Theology"? (Grand Rapids: Kregel, 2001).
43. Sumaryono, Hermeneutik, hlm. 77; Grenz, A Primer on Postmodern, hlm. 109.
44. Dockery, Biblical Interpretation, hlm. 169.
45. Grenz, A Primer on Postmodern, hlm. 109.
46. Sumaryono, Hermeneutik, hlm. 108-109.
47. Vanhoozer, Is There Meaning153; bdk. Osborne, Hermeneutical Spiral, hlm. 378-380.
48. Ibid.
49. Ibid., hlm. 162-163; Richard L. Pratt, Jr., He Gave Us Story: The Bible Student’s Guide to Interpreting Old Testament Narratives (Grentwood: Wolgemuth & Hyatt, 1990), hlm. 27.
50. “Discovering the Bible in the Non-biblical”dalam Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World (ed. R. S. Sugirtharajah; London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1991), hlm. 311.
51. Hartopo, “Catatan Kuliah.”
52. Is There Meaning, hlm. 44.
53. Validity in Interpretation (Chicago: University of Chicago Press, 1976), hlm. 126; bdk. pendapat Osborne yang mengatakan bahwa mengetahui makna yang dimaksudkan pengarang adalah tanggung jawab etis seorang penafsir (lih. Hermeneutical Spiral, hlm. 385).
54. The Gagging, hlm. 130-131.
55. Dockery, Biblical Interpretation, hlm. 178.
56. “The Impact of Postmodern Thinking on Evangelical Hermeneutics,”Journal of Evangelical Theological Society 40/1 (Maret 1997) 71 [penekanan ditambah oleh penulis]; bdk. Johnson Liem, “Contemporary Hermeneutics: Bane or Boon?,”Stulos Theological Jurnal 9/1 & 2 (Mei-November 2001), hlm. 6.
57. “Presuppositions in New Testament Criticism”dalam New Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods (ed. I. Howard Marshall; Grand Rapids: Eerdmands, 1977), hlm. 62.
58. Vanhoozer, Is There Meaning 162; Robert P. Carrol, “Poststructuralist Approaches New Historicism and Postmodernism”dalam The Cambridge Companion, hlm. 61.
59. Bill Flatt, “Function of Presuppositions and Attitudes in Biblical Interpretation”dalam Biblical Interpretations: Principles and Practices Studies in Honor of Jack Pearl Lewis Professor Bible Harding Graduate School of Religion (eds. F. Furman Kearly, Edward P. Myers, dan Timothy D. Hadley; Grand Rapids: Baker, 1986), hlm. 61.
60. The Hermeneutical Spiral, hlm. 384. John Calvin pun mengatakan hal senada, “it is audacity akin to sacrilege to use the scripture at our own pleasure and to play with them as with a tennis ball, which many before us have done”(dikutip dari Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics [3rd. ed.; Grand Rapids: Baker, 1970], hlm. 58).
61. Dikutip dari Stanton, “Presuppositions in New Testament”, hlm. 64.
62. Liem, “Contemporary Hermeneutics”, hlm. 8-9; Stanton, “Presuppositions in New Testament”, hlm. 62, 68.
63. Hartopo, “Catatan Kuliah.”
64. The Hermeneutical Spiral, hlm. 6.
65. Bdk. McQuilkin, “The Impact of Postmodern Thinking”, hlm. 76; Stanton, “Presuppositions in New Testament”, hlm. 68; Flatt, “Function of Presuppositions”, hlm. 70.
66. Ibid., hlm. 65.
67. Osborne, The Hermeneutical Spiral, hlm. 413-415.
68. Pratt, He Gave Us Story, hlm. 40.
69. The Westminster Confession Faith bab 1 artikel 4 (Atlanta: The Committee for Christian Education & Publication, 1990), hlm. 5.
Sumber:
VERITAS 10/1 (April 2009), hlm. 117-133
Profil Pancha Wiguna Yahya, M.Th.:
Ev. Pancha Wiguna Yahya, M.Th. adalah Dosen Biblika di Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang. Beliau menyelesaikan studi Sarjana Theologi (S.Th.) dan Master of Theology (M.Th.) di SAAT Malang.