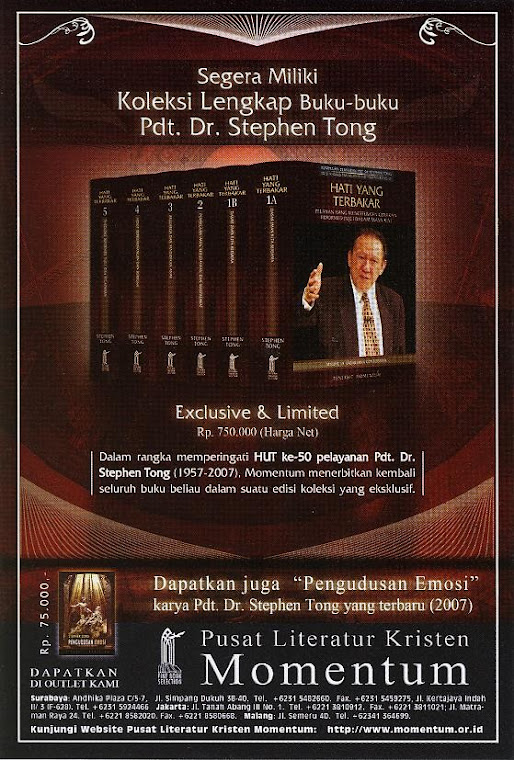Tinjauan Kritis Iman Kristen terhadap Penyimpangan Penggunaan Kata
oleh: Denny Teguh Sutandio
PENDAHULUAN: THE DEATH OF THE AUTHOR ALA POSTMODERNISME
Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sedang hidup di zaman postmodern dengan ide postmodernisme yang salah satu ajarannya berusaha menghilangkan makna asali/sesungguhnya dan menggantikannya dengan makna subjektif. Di dalam ilmu penafsiran (hermeneutika) ala postmodernisme, kita mengenalnya dengan istilah the death of the author (matinya sumber). Istilah ini berarti makna dari suatu teks atau perkataan TIDAK lagi ditafsirkan dari perspektif sumbernya (penulis atau pembicara/orang yang berkata), tetapi boleh ditafsirkan oleh si pembaca dan orang yang mendengarkan perkataan tersebut. Dengan kata lain, istilah ini berarti setiap orang boleh menafsirkan teks atau perkataan orang lain semau gue tanpa harus sesuai dengan maksud asli dari sumbernya. Tidak heran, dunia penafsiran entah itu umum maupun Alkitab semakin kacau. Semakin lama kita juga makin memperhatikan bahwa satu kata yang aslinya bersifat agung dan indah akhirnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga makna kata tersebut sekarang tidak lagi sesuai dengan makna asali karena telah ditafsirkan dengan muatan tertentu yang menguntungkan diri sendiri. Kata-kata apa saja yang sering ditafsirkan seenaknya sendiri? Bagaimana kita sebagai orang Kristen terpanggil untuk mengatakan sesuatu yang sesuai dengan makna asalinya?
VARIASI PENYIMPANGAN KATA DAN TINJAUAN KRITISNYA
Kita akan mencoba menunjukkan variasi kata yang sering kali ditafsirkan seenaknya sendiri yang tidak sesuai dengan makna asalinya dengan mencoba memberikan definisi yang sebenarnya kemudian penyimpangan maknanya (demi menguntungkan diri sendiri), lalu terakhir kita akan mengkritisinya. Kata-kata tersebut meliputi:
1. Rohani
Dunia kita memahami arti rohani itu sebagai lawan dari jasmani (rohaniah >< batiniah). Tetapi Alkitab memiliki definisi yang lebih agung dari definisi dunia. Alkitab TIDAK pernah memisahkan antara jasmani dan rohani, karena itu satu kesatuan dalam diri manusia. Namun ketika mendefinisikan rohani, maka Alkitab secara implisit memberikan definisi sebagai sebuah kondisi di mana seseorang berjalan bersama Roh Allah untuk taat kepada Kristus dengan menjadikan firman Allah, Alkitab sebagai satu-satunya sumber dan dasar bagi iman dan praktik hidup Kristen. Seorang yang rohani adalah seorang yang taat kepada Allah dan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Itulah yang dimaksud Paulus dengan hidup oleh Roh di Galatia 5:16, “Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.” (yang dijelaskan Paulus kemudian sebagai buah Roh di ayat 22-23)
Namun sayang sekali, hari-hari ini, istilah agung “rohani” dimengerti dengan sesuatu yang benar-benar membingungkan. Seorang “Kristen” (lebih tepatnya Katolik Roma) yang mengaku diri “rohani” dapat memilih seorang istri yang berbeda iman sama sekali, apa alasannya? Saudara sepupunya menjawab bahwa agama dari istri ini mirip dengan Kristen, di mana penganut agama ini menyembah “Tuhan” yang sama dengan Kristen (Allah Bapa). Padahal Alkitab dengan jelas dan tanpa kompromi mengajar kita, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” (2Kor. 6:14) TIDAK ada pengecualian dari firman Tuhan ini: jangan mencari pasangan yang berbeda iman! Tetapi herannya mengapa yang dikatakan rohani bisa melanggar firman Tuhan? Itu rohani dari sebelah mana?
Definisi “rohani” juga diselewengkan dengan pengertian sebagai suatu aktivitas agamawi atau sekadar pengalaman ekstase agamawi. Orang lain melihat seseorang itu rohani karena orang tersebut berdoa sebelum makan, rajin mengikuti acara gereja, bahkan rajin mendalami Alkitab, namun sayangnya tidak mengalami hubungan intim dengan Tuhan. Pengetahuan theologisnya hanya bersarang di otak tanpa pernah ada pengalaman rohani. Namun di sisi lain, ada yang mengukur orang rohani dari gejala pengalaman ekstase, misalnya: sering bertemu Tuhan di dalam doa, mendapat “wahyu” dari Tuhan, dll, namun sayangnya Alkitab dilecehkan dengan menganggap Alkitab lebih rendah dari pengalaman ekstase mereka. Kedua hal ekstrem ini tentu TIDAK benar, karena rohani TIDAK pernah berat sebelah! Hidup rohani selalu terintegritas dan menyeluruh, di mana pengetahuan iman sesuai dengan Alkitab yang dimulai dari hati yang mengasihi Allah selalu mengakibatkan pemikiran, perkataan, dan tindakannya memuliakan-Nya. Dengan kata lain, di dalam Kekristenan, TIDAK pernah ada dualisme: agama vs sains! Oleh karena itu, makin mencintai Tuhan dan belajar firman-Nya, orang yang rohani makin rendah hati, rela dikoreksi oleh orang lain asalkan itu sesuai dengan firman-Nya. Namun herannya, orang yang mengklaim diri “rohani” hari-hari ini makin hidup “rohani”, makin merasa diri hebat. Jika ada ajaran/imannya salah, lalu ditegur, selalu ada saja alasannya. Saya makin meragukan: layakkah orang tersebut disebut “rohani”?
2. Pendidikan Dekrit Pertama
Seorang yang rohani mempengaruhi cara orang tersebut mendidik anaknya. Orang yang hatinya untuk Tuhan selalu mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Pdt. Sutjipto Subeno, M.Div. dengan pendidikan dekrit pertama (first decree). Kalau kita kembali kepada Alkitab, maka Alkitab dengan jelas mengajar para orangtua untuk mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Perhatikan firman Allah sendiri kepada Musa, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” (Ul. 6:4-7) Di dalam Dasa Titah, pada permulaan, Allah sendiri mengingatkan Israel akan siapakah Allah itu yang harus disembah (Kel. 20:2), lalu disusul dengan titah pertama, “Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.” (Kel. 20:3) Setelah pengenalan akan Allah beres, baru disusul dengan perintah lain, termasuk salah satunya menghormati orangtua (Kel. 20:12). Dengan kata lain, Allah menginginkan anak dari kecil mengenal Penciptanya terlebih dahulu dan tentunya menjalankan kehendak-Nya secara pribadi di dalam diri anak tersebut, baru setelah itu diajar untuk menghormati orangtua. Namun ada orang yang mendengarkan uraian Pdt. Sutjipto tentang pendidikan dekrit pertama ini lalu (sengaja) menyimpangkan artinya dengan mengajar bahwa anak dari kecil harus dididik yang benar (yang benar ditafsirkan sebagai memenuhi kehendak orangtua). Jadi, yang menjadi Allah dalam hidup seorang anak itu siapa: Allah Trinitas atau orangtua? Benar-benar mengenaskan orang ini.
3. Cinta
Seorang yang hatinya untuk Tuhan sebenarnya memiliki konsep cinta yang beres, karena Allah itu adalah Kasih (God is Love). Apa itu cinta/kasih? Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Kasih. Di dalam kasih Allah, ada kepemilikan (Allah terlebih dahulu memilih beberapa manusia untuk diselamatkan di dalam Kristus—Rm. 8:29-30), pengorbanan (Kristus berkorban demi mereka yang telah dipilih Allah), Kebenaran atau Truth (menuntun manusia untuk mengenal Allah yang sejati), keadilan (menuntun manusia untuk berlaku adil), kejujuran dan ketulusan (mengajar manusia untuk berkata jujur dan murni dari hati), dll. Dan di dalam perspektif theologi Reformed, objek kasih Allah kepada dunia dibagi menjadi dua: secara umum yaitu kepada semua orang tanpa kecuali (Mat. 5:45) dan secara khusus yaitu HANYA kepada umat pilihan-Nya melalui pemeliharaan keselamatan, kehidupan, dll, sehingga umat pilihan-Nya memiliki hidup yang lebih dari pemenang (Rm. 8:37). Itu semua konteksnya adalah kasih Allah. Namun di Alkitab juga ada wujud kasih lain, yaitu kasih antar saudara, suami dan istri, dll. Tentang hubungan spesial suami dan istri, Alkitab secara konsisten mengajar kita bahwa pernikahan monogami yang dikehendaki-Nya (Kej. 2:24; Mat. 19:5; Ef. 5:31). Di dalam teks Yunaninya, Matius 19:5 dan Efesus 5:31, kata laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan bentuk tunggal, sehingga sangat jelas bahwa Allah memerintahkan pernikahan monogami! Namun karena dosa, maka Allah membiarkan orang-orang di zaman Perjanjian Lama memiliki lebih dari 1 istri (yang akhirnya bermasalah: perkelahian di antara anak-anak dari istri yang berbeda, dll) dengan maksud untuk mengajar kita sekarang tentang bahaya pernikahan poligami. Bahkan di dalam titah ketujuh, Allah sendiri berfirman, “Jangan berzinah.” (Kel. 20:14) Berarti Ia menginginkan kesetiaan di dalam hubungan cinta suami dan istri. Lebih dipertajam lagi, Ia menginginkan jika kita mengatakan bahwa kita mencintai seseorang, kita benar-benar setia terhadap orang yang kita cintai! Berarti, cinta MANUSIA hanya ditujukan kepada satu orang saja (ada komitmen yang jelas, bukan ngegombal)! Di luar itu dianggap berzinah.
Namun hari-hari ini, dunia kita melalui film-film Holywood mengajar generasi muda dengan suatu ide bahwa cinta itu sesuatu yang murah, bisa dikatakan kepada siapa pun tanpa adanya ikatan komitmen yang jelas! Ambil contoh, tontonlah film Holywood (500) Days of Summer (2009) yang mengisahkan seorang cewek (Zooey Deschanel berperan sebagai Summer Finn) yang sudah memiliki pacar dengan mudahnya pergi berdua dengan cowok lain (Joseph Gordon-Levitt berperan sebagai Tom Hansen) bahkan yang paling gila, bermain seks dengan si cowok lain tersebut, lalu setelah itu Summer Finn mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Akibatnya Tom Hansen sedih karena telah dibohongi oleh Summer, namun di akhir cerita, Summer yang sudah menikah (dengan pacarnya) ini mendatangi Tom dan masih memegang tangan si Tom. Lain halnya dengan film Holywood yang lain, My Girlfriend’s Boyfriend (2010) yang menceritakan sosok janda yang bernama Jesse Young (diperankan oleh Alyssa Milano) berkenalan dengan dua cowok sekaligus (Ethan Reed dan Troy Parker) di kafe tempat ia bekerja. Kedua cowok ini meminta nomer HP si Jesse, kemudian di tempat dan waktu berbeda, masing-masing cowok mengajak Jesse pergi berkencan, dan si Jesse menyanggupinya. Kemudian, ketika kedua cowok ini mengatakan mencintai Jesse, tanpa pikir panjang si Jesse menerima cinta mereka berdua (dengan mengatakan, “I love you” kepada mereka berdua di tempat dan waktu berbeda) dan berpacaran dengan mereka.
Gara-gara film Holywood ini dan lagu Putus Nyambung ditambah berita perceraian dari banyak artis dan memang karena natur manusia yang berdosa, perhatikanlah gaya hidup generasi muda zaman postmodern. Seorang cowok/cewek yang sudah resmi berpacaran bisa dengan mudahnya berkenalan dengan lawan jenis lain, lalu ketika ditanya, siapa lawan jenis tersebut, mereka menjawab bahwa itu hanya “teman”. Lagi-lagi alasan klise! Benarkah orang tersebut DAPAT membedakan dengan jelas mana teman dengan “teman” (teman spesial)? Kalau dalam tahap berpacaran saja, sudah tidak setia dan mudah berkenalan dengan lawan jenis lain, bagaimana jika orang ini menikah? Dijamin kalau tidak segera bertobat, orang ini akan dengan mudahnya berselingkuh, namun untuk menutupi perselingkuhannya (natur manusia berdosa: sudah berdosa, masih tidak mau mengakui dosanya), maka ia akan beralasan, “kami hanya berteman biasa, tidak lebih.” Saya jadi teringat akan peringatan dari Pdt. Yohan Candawasa, S.Th. dalam rekaman MP3 dari Seminar: Ambillah Aku Melayani Engkau yang mengatakan bahwa perselingkuhan (dalam pernikahan) dimulai dari persahabatan! Beliau mengatakan bahwa awal-awalnya cowok dan cewek (pasangan selingkuh) sama-sama mengatakan, “kami hanya berteman biasa, tidak lebih”, namun waktu membuktikan bahwa “pertemanan” itu mengakibatkan perselingkuhan. Oleh karena itu, beliau memberikan tanda awas kepada para pelayan Tuhan (dan tentunya kita sebagai jemaat Kristen) untuk tidak merasa diri bisa mengendalikan segala pencobaan. Pdt. Dr. Stephen Tong di dalam Seminar Pembinaan Iman Kristen (SPIK) 2010: Rahasia Kemenangan Menuju Cinta dan Seks Menuju Pernikahan juga mengatakan hal serupa bahwa perselingkuhan terjadi justru di dalam persahabatan (rekan bisnis, dll) di mana seorang cowok dan cewek berada di dalam satu kantor yang sama. Si cowok tidak puas dengan istrinya dan si cewek tidak puas dengan suaminya, akhirnya si cowok dan cewek ini akhirnya ada affair dan keluarga mereka berantakan!
4. Bekerja
Seorang yang hatinya untuk Tuhan adalah seorang yang terus-menerus bergumul untuk mencari kehendak Tuhan di dalam profesinya. Ia akan bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Apa itu bekerja? Apa motivasi bekerja? Rasul Paulus di dalam Efesus 2:10 mengajar kita tentang kaitan panggilan Allah dan profesi, “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya.” Dari ayat ini, kita diajar oleh Allah melalui Paulus bahwa setelah kita diselamatkan melalui anugerah Allah oleh iman di dalam Kristus (Ef. 2:8-9), maka kita yang telah diciptakan oleh Allah harus mengerjakan sesuatu yang telah disiapkan-Nya sebelumnya. Secara logis, maka Allah yang mencipta manusia tentu adalah Allah yang memberikan talenta yang BERBEDA kepada manusia dan manusia bertugas untuk menemukan talenta itu dan mengembangkannya demi kemuliaan-Nya. Orang yang diberi talenta oleh Tuhan untuk melayani-Nya di dalam bidang musik JANGAN dipaksa untuk bekerja bisnis, karena talentanya bukan di situ, demikian juga sebaliknya kalau orang memang berbakat dagang jangan disuruh menyanyi, biasanya banyak dari mereka suaranya gak karuan, hehehe. Berarti, setiap orang yang telah diberi Tuhan talenta tertentu harus mengembangkan talenta itu di dalam profesi tertentu/khusus yang memuliakan-Nya dan profesi itu TIDAK melulu hanya satu jenis. Mengutip khotbah mimbar dari Pdt. Hendry Ongkowidjojo, M.Th. tanggal 28 November 2010, setiap orang itu bekerja, entah itu ayah/suami bekerja di kantor, ibu/istri bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, anak bekerja sebagai siswa/mahasiswa, dll.
Namun, karena pengaruh dari materialisme dan utilitarianisme dari manusia berdosa (khususnya pengaruh materialisme dari beberapa filsafat Timur/Tiongkok atau mungkinkah pengaruh dari bukunya Robert T. Kiyosaki, “Rich Dad, Poor Dad”?), maka beberapa orang “Kristen” mengidentikkan bekerja dengan berdagang! Jika seseorang tidak bisa berdagang, maka orang itu dianggap tidak bisa bekerja. Mengapa? Karena bekerja hari-hari ini diidentikkan dengan menghasilkan uang (banyak)! Tidak heran, seorang ibu yang berasal dari sebuah gereja Injili Tionghoa di Surabaya menghina saudara sepupunya yang adalah seorang penginjil sebagai orang yang tidak bisa bekerja. Jika pengertian bekerja identik dengan berdagang, maka orang yang paling tidak bisa bekerja adalah Tuhan Yesus! Saya menantang ibu Kristen ini, beranikah ia menghina Yesus tidak bekerja hanya karena Ia tidak pernah berdagang di dunia? Jika tidak berani, lalu dengan dasar pikir apa ia menghina sepupunya yang adalah seorang penginjil sebagai seorang yang tidak bisa bekerja?
5. Dinamis
Orang yang hatinya untuk Tuhan mengakibatkan ia akan peka melihat pimpinan Roh Kudus di dalam setiap inci kehidupannya. Dan Alkitab mengajar kita bahwa pimpinan Roh Kudus adalah pimpinan yang DINAMIS di dalam hidup kita. Kata dinamis berasal dalam kata Yunani dunamis (δύναμις) yang dalam Alkitab LAI diterjemahkan “kuasa”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (1990), dinamis diartikan sebagai, “penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dng keadaan dsb;” (hlm. 206) Berarti, dinamis berarti yang memiliki kekuatan besar, entah itu kuasa, mukjizat, dll dan itu dikaitkan dengan karya Allah. Oleh karena jalan-Nya berbeda dengan jalan kita, maka sesuatu yang dinamis dari Allah pasti sesuatu yang melampaui jalan pikiran manusia. Akibatnya, kita harus siap sedia tatkala Ia menginterupsi apa yang kita ingin kerjakan, karena kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, tatkala kita diinterupsi oleh Allah, maka menurut definisi dari KBBI, kita harus dinamis yang berarti harus mudah menyesuaikan diri, karena yang harus kita ikuti adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Di Alkitab, ketika Paulus dan Silas hendak memberitakan Injil di Asia, Roh Kudus mencegah mereka dan memimpin mereka untuk memberitakan Injil di tanah Frigia dan Galatia (Kis. 16:6). Pdt. Dr. Stephen Tong menyebutnya sebagai pimpinan Allah yang “negatif” (kelihatan negatif, namun bertujuan positif). Saya menyebutnya sebagai pimpinan Allah yang dinamis. Kedinamisan cara kerja Allah ini PASTI berkaitan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Cara kerja Allah yang dinamis ini TIDAK berarti Ia melarang kita memiliki rencana hidup, namun kita diperintahkan oleh Allah untuk merencanakan segala sesuatu lalu mengaitkannya dengan kehendak-Nya. Yakobus sangat memahami konsep ini dengan mengajar kita, “Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.” (Yak. 4:15)
Namun hari-hari ini, kembali, kata dinamis diselewengkan artinya. Dinamis tidak lagi berkaitan dengan kehendak-Nya, namun berkaitan dengan kehendak diri atau lebih tepatnya untuk menutupi kesalahan/kelemahan diri. Sehingga hari-hari ini, kata dinamis hampir TIDAK bisa dibedakan dengan lupa atau plin-plan! Seorang gembala sidang yang suka mengganti jadwal pengkhotbah untuk gerejanya selalu berargumentasi bahwa dirinya itu dinamis. Benarkah itu dinamis? Ataukah itu berkaitan dengan drinya sendiri yang suka lupa atau bahkan karakter dirinya yang memang plin-plan? Mengapa sesuatu yang berubah di dalam salah satu aliran Kristen selalu dikaitkan dengan dinamis? Puji Tuhan, Allah kita yang dinamis tahu batas-batas di mana Ia perlu dinamis, di mana Ia tidak perlu dinamis, sehingga Ia tidak secara tiba-tiba mengangkat Kristus pada waktu Ia berada di jalan salib (via dolorosa). Jika Ia terlalu dinamis lalu mengangkat Kristus pada waktu di jalan salib, maka kita semua pasti binasa karena tidak ada jalan keselamatan. Jika Ia melakukan hal demikian, maka Ia TIDAK layak disebut dinamis, namun Ia lebih layak disebut: TIDAK konsisten, karena rencana kekal-Nya untuk menebus dosa manusia tiba-tiba ditolak-Nya sendiri! Berhati-hatilah menggunakan kata yang agung!
6. Bergumul
Orang yang hatinya untuk Tuhan adalah orang yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan orang itu selalu bergumul untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Apa itu bergumul? Bergumul adalah sebuah proses pengalaman hidup rohani anak Tuhan dengan Tuhan untuk makin mengerti dan menjalankan firman dan kehendak-Nya dalam hidupnya. Pergumulan ini terjadi karena adanya ketegangan yang terus-menerus antara kehendak Allah yang Mahakudus dengan keinginan manusia yang berdosa. Misalnya, dalam melawan dosa, anak Tuhan terus-menerus bergumul, karena mereka tahu bahwa Allah membenci dosa, namun anak Tuhan yang masih bertubuh jasmani ini menginginkan dosa tersebut, sehingga mereka harus bergumul bagaimana mengalahkan dosa dengan mengarahkan hatinya HANYA kepada Allah. Dengan kata lain, di dalam proses pergumulan: pusatnya adalah Allah Trinitas dan firman-Nya, Alkitab; kedua, motivasi dan tujuannya untuk menyenangkan Allah dengan menjalankan firman dan kehendak-Nya. Perhatikan pergumulan Paulus melawan dosa di dalam Roma 7:18-26. Itulah pergumulan sejati, karena ia terus-menerus menyadari bahwa Allah dan firman-Nya harus ditaati dan tujuannya hanya untuk memuliakan-Nya.
Namun kata yang begitu agung, “bergumul” dimengerti dengan cara yang ngawur. Seorang pemudi “Kristen” yang sudah mengetahui bahwa pasangan hidupnya itu tidak seiman masih dengan mudahnya mengatakan bahwa ia sedang bergumul dan proses pergumulannya berlangsung satu tahun. Bukankah Alkitab sudah jelas mengajar kita bahwa jangan menjadi pasangan yang tidak seiman? Kalau Alkitab sudah jelas, mengapa perlu waktu satu tahun untuk bergumul? Lebih tajam lagi, apakah benar si pemudi “Kristen” ini berkomitmen menaati firman Tuhan yang melarang umat-Nya mencari pasangan yang tidak seiman? Ataukah sebenarnya ia hanya mengerti firman Tuhan tersebut secara kognitif (nyangkut di otak), namun ia tetap bernafsu dengan pasangan yang tidak seiman, lalu supaya orang lain tidak mengetahui niat buruknya itu, maka ia memoles kata “bernafsu” dengan “bergumul” supaya terkesan “rohani” dan “saleh” (mengingat orang yang mengatakan bahwa dia lagi bergumul ini adalah orang yang keras kepala)? Terus terang, saya ngeri melihat gejala banyak generasi muda (tidak menutup kemungkinan: generasi tua) zaman ini baik yang Kristen maupun non-Kristen yang makin lama bukan makin mengerti firman Tuhan dan berusaha menjalankannya secara konsisten, namun makin sok tahu dan melawan Alkitab seolah-olah mereka lebih hebat dari Allah. Bertobatlah selagi Tuhan memberi kita kesempatan!
7. Baik
Terakhir, orang yang hatinya untuk Tuhan pasti berusaha mengerti apa yang benar dan baik dari perspektif Allah. Kali ini saya tidak hendak mendefinisikan benar, namun saya hendak menyoroti masalah baik, karena hari-hari ini justru definisi baik yang paling suka dipakai setan untuk diselewengkan. Apa itu baik? Kembali kepada Alkitab. Di Roma 12:2, Paulus mengatakan, “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” Kata “baik” dalam ayat ini teks Yunaninya adalah agathos (ἀγαθός) yang bisa berarti baik atau berguna. “Baik” di sini merupakan salah satu ciri kehendak Allah dan “baik” ini dikaitkan dengan dua ciri kehendak Allah yang lain yaitu: berkenan kepada Allah (bisa diterjemahkan: menyenangkan Allah) dan sempurna. Berarti standar baik menurut firman Allah adalah baik yang berguna, terintegrasi, dan menyeluruh. Allah yang baik pasti berkaitan dengan Allah yang Kudus, Benar, Adil, Jujur, dan Kasih. Memisahkan kesemuanya berarti memisahkan Allah sendiri, karena semuanya itu atribut Allah yang saling berkaitan! Dari perspektif Alkitab, maka penilaian orang Kristen akan “baik” itu harus saling berkaitan, apakah kebaikan itu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kekudusan, dan kemurnian? Ataukah kebaikan itu memiliki unsur terselubung? Dengan kata lain, kebaikan harus dipikirkan: dasar pikir/standarnya (presuposisi), motivasi, dan tujuannya.
Namun banyak orang zaman sekarang terlalu cepat memuji orang lain dengan sebutan “orang itu baik” tanpa standar dan arah yang jelas. Pertama, standar kebaikan sudah mulai rusak. Kebaikan dimengerti sebagai sesuatu yang menyenangkan diri (egosentris). Contoh, seorang guru disebut sebagai guru yang baik oleh anak muridnya karena guru tersebut selalu murah nilai (artinya selalu memberi nilai yang bagus kepada muridnya). Contoh lain, A mengatakan B itu sosok yang baik, karena B itu telah menyenangkan A, misalnya: membelikan (dan memberikan) dia makanan, mengantarkan dia pulang, dll. Jika B menegur si A, apakah A masih menganggap B itu baik? Jika B tidak menuruti beberapa kemauan dari si A agar si A lebih dewasa, apakah A masih menganggap A itu sosok yang baik?
Selain standar kebaikan rusak, motivasi dan tujuan kebaikan itu sendiri rusak. Ketika kita memuji orang lain sebagai orang yang baik, apa motivasi dan tujuan kita? Apakah dengan memuji orang lain itu baik, kita ingin memanfaatkan orang yang kita puji tersebut agar di lain kesempatan kita dapat memanfaatkan lagi tenaga, waktu, dan uangnya demi memenuhi kemauan kita? Ataukah kita memuji orang lain sebagai orang yang baik itu hanya sekadar lip service (bahasa Jawa: mbasahi lambe)? Ataukah kita memuji orang lain sebagai orang yang baik itu keluar dari hati kita yang terdalam?
TANTANGAN BAGI ORANG KRISTEN
Di atas, kita telah membaca dan mengkritisi 7 kata yang sering diselewengkan maknanya oleh banyak orang bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengaku diri “Kristen”, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang normal?
1. Kembali Kepada Alkitab (Sumber)
Salah satu semboyan Reformasi gereja dari Dr. Martin Luther yang terkenal adalah Sola Scriptura yaitu hanya Alkitab! Tuhan memakai momen Reformasi Luther sebagai momen untuk menyadarkan orang Kristen agar mereka kembali kepada Alkitab (back to the Bible) atau kembali kepada sumber (ad fontes). Dari sini, kita melihat bahwa Alkitab sebagai firman-Nya adalah satu-satunya sumber dan dasar mutlak bagi iman dan praktik hidup Kristen serta standar penentu kebenaran mutlak. Oleh karena itu, adalah bijaksananya kita jika kita dengan rendah hati kembali kepada Alkitab, mau dikoreksi oleh Alkitab tatkala kita salah jalan atau salah prinsip. Jangan sok tahu, karena kita memang pada prinsipnya tidak pernah mengetahui segala sesuatu, apalagi kehendak-Nya.
2. Telitilah Makna Suatu Kata
Kembali kepada Alkitab sebagai sumber menuntun kita bukan hanya menjadikan sumber itu satu-satunya kebenaran mutlak, namun juga seharusnya menuntun kita untuk lebih mendalami sumber itu. Ketika membaca satu ayat Alkitab yang belum kita mengerti, coba dalami ayat tersebut dengan membaca ayat sebelum dan sesudahnya, lalu cari terjemahan Alkitab dalam bahasa lain, kemudian bandingkan kitab yang memuat ayat tersebut dengan kitab lain di dalam seluruh Alkitab. Dengan cara mendalami Alkitab demikian, kita dimampukan untuk mengerti ayat Alkitab yang sulit tersebut. Demikian juga, tatkala kita tidak mengerti definisi satu kata entah itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain, selidikilah makna aslinya dengan membaca kamus bahasa atau menanyakan kepada orang lain yang lebih mengerti. Jangan menafsirkan satu kata dengan pengertian kita sendiri, karena pengertian kita yang seenaknya sendiri akan satu kata BERBEDA dengan pengertian objektif akan satu kata tersebut, lalu perbedaan itu akhirnya mengakibatkan adanya miskomunikasi dan misinterpretasi dan berakhir dengan ketidakmengertian bahkan perpecahan/perselisihan.
3. Pergunakanlah Secara Bertanggung Jawab
Setelah meneliti makna satu kata dengan benar, maka tugas orang Kristen yang normal adalah mempergunakannya secara bertanggung jawab. Jika kita sudah menelitinya dan mendapati bahwa apa yang kita alami/lakukan (atau kebiasaan kita) tidak sesuai dengan makna asli suatu kata, maka jangan lagi mempergunakan kata itu. Contoh, kita adalah sosok pelupa, sehingga kita mudah mengganti jadwal, maka jangan mengidentikkan kebiasaan kita yang suka lupa ini dengan perkataan “dinamis”, karena dinamis TIDAK sama dengan lupa! Jika lupa, katakan LUPA.
PENUTUP
Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus berkomitmen menggunakan setiap kata dengan bertanggung jawab demi kemuliaan-Nya? Meskipun sulit, biarlah Roh Kudus memampukan dan memimpin hati, pikiran, dan perkataan kita untuk memperkatakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Soli Deo Gloria.