Tuhan, Ajarlah Kami Memberitakan Firman-Mu
(Sebuah Refleksi Pribadi Atas Panggilan Berkhotbah)
oleh : Pdt. Billy Kristanto, Dipl.Mus., M.C.S.
Judul di atas tidak pernah saya dengar secara langsung sebagai suatu doa yang dikatakan oleh pak Tong (Pdt. Dr. Stephen Tong, ed.). Namun yang pernah saya dengar adalah kesadaran akan ketidaksanggupan beliau ketika harus mengajar mata kuliah homiletika (ilmu berkhotbah, ed.), karena beliau sendiri berpendapat belum begitu bisa berkhotbah. Suatu kerendahan hati yang pura-pura supaya mendapat kemuliaan yang lebih tinggi? Saya kira tidak. Karena pengertian paradoks seperti ini tidak mungkin tidak beliau mengerti dari pengajaran Firman Tuhan sebagaimana diteruskan oleh para reformator.[1] Dan saya pikir pemahaman seperti ini bukan hanya cocok diterapkan untuk homiletika tapi juga untuk semua bidang yang lain.
Tulisan singkat ini tidak bermaksud untuk merepresentasikan homiletika yang diajarkan oleh pak Tong (lebih baik kita mendengar langsung dari beliau), namun sebagai suatu refleksi pribadi yang subyektif sifatnya, sejauh yang dapat saya cerna dan olah kembali. Saya akan mulai dari tiga, bahkan empat poin dasar yang seringkali dikatakan oleh pak Tong mengenai tugas khotbah.
Yang pertama, khotbah harus menyatakan otoritas dari Tuhan. Kita teringat perkataan Luther yang menyatakan bahwa seorang pengkhotbah setelah menyelesaikan khotbahnya tidak perlu meminta pengampunan mengenai kekurangan dan keterbatasannya, “for it is God’s Word and not (the preacher’s) and God ought not and cannot forgive it, but only confirm, praise, and crown it.”[2] Kedengarannya seperti bertentangan dengan pemahaman paradoks di alinea pertama tadi, mengapa tiba-tiba menjadi congkak di sini? Bukan bertentangan, melainkan ini adalah pengertian paradoks yang lain lagi: seorang pengkhotbah yang baik perlu menyadari ketidakberdayaannya, untuk dapat mengerti bahwa kemahakuasaan Tuhanlah yang sedang bekerja pada saat ia berdiri di atas mimbar. Ia tidak perlu merasa sungkan dan minder akan kekurangannya, karena justru melalui jalan itulah kuasa Tuhan dinyatakan secara sempurna.[3] Alangkah sulitnya untuk mengerti kebenaran yang sangat sederhana ini. Kita menjumpai mimbar-mimbar yang begitu confidence memberitakan ajaran-ajaran sesat yang tidak berasal dari Firman Tuhan di satu sisi, dan di sisi yang lain pengkhotbah-pengkhotbah yang ‘minder’ dan ‘sungkan’ untuk menegur dosa mereka. Para pencari muka manusia seperti ini tidak mungkin sanggup untuk menyatakan kemuliaan wajah Tuhan yang berbicara melalui mimbar. Tidak ada otoritas, tidak ada penyertaan dari tempat yang tinggi.
Yang kedua, seorang pengkhotbah menyampaikan berita (message) yang relevan bagi pendengarnya. Ada perbedaan antara message dan information. Informasi hanya berupa data, tidak harus ada kaitan yang personal, juga tidak memiliki aspek momen waktu yang krusial. Sebaliknya, message sekalipun tidak harus selalu merupakan new insights, mungkin bahkan perkataan yang kita ‘sudah’ pernah mendengarnya, namun dibutuhkan pada saat itu, karena itu adalah sapaan pribadi dari Tuhan kepada masing-masing pendengar. Tidak ada salahnya dengan new insights yang menambah wawasan pengetahuan kita lebih luas dan kaya, namun ketika seorang menyampaikan Firman Tuhan, ia melakukan lebih daripada hal itu. Seorang pengkhotbah yang diurapi memiliki kepekaan rohani untuk membicarakan kalimat-kalimat yang menyelidiki hati manusia yang terdalam, sementara ia sendiri tidak tentu tahu pergumulan pendengarnya. Relevansi message yang disampaikannya didasarkan pada iman yang sederhana atas kemahatahuan Allah yang mengenal setiap kebutuhan domba-domba-Nya. Karunia nubuat seperti ini tentu adalah semata-mata pemberian Allah dan yang menjadi tanggung jawab si pemberita Firman adalah dia sendiri hidup bersama dengan domba-domba yang ia layani. Ia menderita dan terluka bersama dengan domba-dombanya. Ia sendiri menanggapi dan menggumuli hidupnya di hadapan Tuhan. Ia bukan mesin fotokopi dan ketika ia mengutip perkataan para orang saleh, ia dengan jujur dan tulus belajar untuk mencicipi kedalaman pergumulan jiwa mereka.
Yang ketiga, kuasa yang mengubah (transforming power). Seorang pengkhotbah yang diurapi Tuhan tidak sekadar tampil sebagai pembicara yang menarik. Menarik adalah satu hal, menyampaikan berita yang mengubah hati dan hidup manusia adalah hal yang lain lagi. Seorang pengkhotbah yang baik tidak mempedulikan apakah khotbahnya diterima dan diakui dengan baik atau tidak, melainkan ia mendorong semua pendengarnya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Transforming power ini berkaitan erat dengan convincing power, sementara convincing power berkaitan dengan ketulusan dan kesungguhan kerinduan si pemberita untuk menaati apa yang ia sampaikan. Setiap pengkhotbah adalah orang berdosa yang selalu membutuhkan anugerah pengampunan Tuhan. Ia bukanlah orang yang sempurna dalam pengertian kesempurnaan yang mutlak kelak di sorga. Ia bahkan kadang juga gagal dalam kesaksian untuk menjadi teladan atas apa yang ia khotbahkan. Namun kesempurnaannya terutama terletak pada sikap hatinya yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pendengar yang pertama terhadap khotbah yang disampaikannya. Bersama dengan orang-orang Puritan yang saleh, ia meneriakkan khotbah yang paling keras dan tajam kepada dirinya sendiri.
Yang keempat, dinamika. Ini mirip dengan apa yang sudah dibahas di atas tadi, yaitu kepekaan menangkap apa yang Tuhan mau katakan pada saat itu. Seorang pengkhotbah yang baik, mempersiapkan dengan baik khotbah yang akan disampaikannya. Ia bukanlah seorang yang ‘bergantung kepada kuasa Roh Kudus’ tanpa melakukan persiapan apa-apa. Lloyd-Jones (D. Martyn Lloyd-Jones, ed.) mengatakan agar setiap pengkhotbah mempersiapkan dengan baik khotbah yang akan disampaikan, “The great preachers have been men who prepared great sermons.”[4] (=Pengkhotbah agung telah menjadi orang yang mempersiapkan khotbah yang agung., ed.) Namun ketika ia berdiri di atas mimbar, ia harus mempersilakan Roh Kudus untuk memegang kontrol sepenuhnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, “...though you may go into the pulpit with what you regard as an almost perfect sermon, you never know what is going to happen to it when you start preaching...”[5] (=...meskipun Anda berdiri di atas mimbar dengan apa yang Anda anggap sebagai sebuah khotbah yang sempurna, Anda tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi ketika Anda mulai berkhotbah..., ed.) Dia sendiri menyaksikan bagaimana seringkali kalimat-kalimat yang terbaik yang diucapkan dalam khotbahnya justru merupakan kalimat yang tidak ada dalam persiapannya. Pengkhotbah yang terlalu bergantung pada persiapannya dan tidak terbuka pada pimpinan Roh Kudus secara mendadak di atas mimbar akan sulit untuk menyatakan dinamika ini. Sebaliknya, mereka yang hanya menantikan karya Roh Kudus namun tidak melakukan persiapan apa-apa adalah orang-orang yang tidak taat menjalankan bagian dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya.
Beberapa poin tambahan lagi yang dapat kita pelajari dari pak Tong mengenai tugas khotbah yaitu suatu prinsip sederhana seperti kita warisi dari para reformator. Seorang pengkhotbah hanya memberitakan Kitab Suci. Calvin mengatakan, “The Spirit will not be a maker of new revelations.”[6] Sekalipun demikian, tugas seorang pengkhotbah adalah “to expound the scripture in the midst of the worshipping Church, preaching in the expectancy that God will do, through his frail human word, what He did through the Word of His prophets of old, that God by His grace will cause the word that goes out of the mouth of man to become a Word that proceeds from God Himself, with all the power and efficacy of the Word of the Creator and Redeemer.”[7] Keaslian (authenticity) seorang pengkhotbah bukanlah dalam pengertian ia memberitakan wahyu-wahyu baru yang tidak ada dan bahkan bertentangan dengan Alkitab, melainkan bahwa ia tetap setia memberitakan wahyu yang tua itu, namun yang senantiasa menjadi baru dan segar karena “as if men ‘heard the very words pronounced by God himself.”[8] Seorang pengkhotbah yang baik bergumul agar jemaatnya tidak melihat wajah manusia yang berdosa, melainkan kemuliaan wajah Tuhan yang sedang berkata-kata pribadi kepada domba-domba-Nya.
Dalam kaitan ini, pak Tong juga mengatakan bahwa kita perlu belajar beriman dan percaya bahwa Roh yang telah menggerakkan para nabi dan para rasul memberitakan Firman Tuhan adalah Roh yang sama yang juga dapat menggerakkan kita. Di sini, kita teringat perkataan seorang Elisa sebelum Elia terangkat ke sorga, “Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu.” (2Raj. 2:9) Sayang sekali, di kalangan gereja-gereja Protestan tidak banyak pemberita-pemberita Firman yang memiliki urapan dan kuasa yang besar. Pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya berusaha untuk menyenangkan pendengar dan jemaatnya dan tidak mencari kepenuhan kuasa dan kehadiran Tuhan dalam pelayanannya tidak mungkin dapat hidup memperkenan serta menyenangkan hati Tuhan.
Berbeda dengan pengkhotbah legendaris seperti Dr. Andrew Gih, pak Tong tidak berusaha untuk membujuk (persuade) pendengarnya untuk menerima kebenaran Injil Yesus Kristus. Seringkali pada saat calling beliau mengatakan, “Sekarang saya memberikan kesempatan terakhir bagi mereka yang mau menerima Tuhan ... setelah itu kesempatan akan ditutup.” Injil dan Firman Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu diobral, karena bukan Tuhan yang membutuhkan manusia, tapi manusialah yang membutuhkan Tuhan dan Firman-Nya. Seorang theolog menggambarkan khotbah Jonathan Edwards demikian, “Rather than attempt to persuade the unconverted, Edwards tried by means of his preaching, in addition to offering the Word, (1) to provide the optimal conditions and circumstances within which conversion might take place, (2) to offer the logical connections between guilt and repentance so that those who have been or are being converted might better understand what is happening to them, and (3) to prevent the misinterpretation of pseudo-religious experience, especially by those who believe they have experienced grace but have not.”[9] Seorang pengkhotbah yang baik tidak menyayangkan perasaan pendengarnya agar jangan sampai dibuat terluka. Alkitab mengatakan, “Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.” (2Kor. 7:10)
Mungkin poin yang terakhir, seorang pengkhotbah yang baik setiap kali berdiri di atas mimbar, melihatnya sebagai kesempatan yang pertama kali, sekaligus yang terakhir kalinya. Sebagai yang pertama kali sehingga ia boleh senantiasa menjaga perasaan ketidaklayakan dan ketidakmampuan, supaya ia terus-menerus belajar bergantung kepada kuasa Tuhan. Sebagai yang terakhir kali sehingga ia berusaha untuk memberikan yang terbaik yang dapat ia berikan. Lloyd-Jones dalam bukunya Preaching and Preachers mengutip perkataan terkenal Richard Baxter, “I preach as never sure to preach again and as a dying man to dying men.”[10] Kaitan erat antara eschatological consciousness dengan hidup yang menggunakan waktu dengan baik sudah dicatat dalam Alkitab (Ef. 5:16). Ketika seseorang belajar untuk selalu melihat setiap kesempatan sebagai kesempatan yang terakhir, ia akan mempunyai cara pandang yang berbeda dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup ini.
Dalam tulisan yang singkat ini, saya berharap dapat menggambarkan dengan gamblang bahwa homiletika Pdt. Stephen Tong mewarisi semangat dan pengertian yang dapat kita telusuri dalam sejarah Gereja, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, para reformator dan pengkhotbah-pengkhotbah yang diurapi Tuhan. Kiranya kita dengan rendah hati boleh belajar dari kehidupan Kristus sebagaimana dinyatakan dalam hidup hamba-hamba-Nya yang dikasihi-Nya. Sola Gratia. Sola Fide. Solus Christus. Soli Deo Gloria!
Sumber :
Handout khotbah Pdt. Billy Kristanto di sesi Worker di National Reformed Evangelical Convention (NREC) 2007.
Disalin ulang dan diedit oleh :
Denny Teguh Sutandio, S.S.
(proofreader di Momentum Christian Literature, Surabaya)
Profil Pdt. Billy Kristanto :
Pdt. Billy Kristanto, Dipl.Mus., M.C.S. lahir pada tahun 1970 di Surabaya. Sejak di sekolah minggu mengambil bagian dalam pelayanan musik gerejawi. Setelah lulus SMA melanjutkan studi musik di Hochschule der Künste di Berlin majoring in harpsichord (Cembalo) di bawah Prof. Mitzi Meyerson (1990-96).
Setelah lulus dari situ melanjutkan post-graduate study di Koninklijk Conservatorium (Royal Conservatory) di Den Haag, a conservatory with the largest early music department in the world (mempelajari historical performance practice). Belajar di bawah Ton Koopman, seorang dirigen, organis, cembalis dan musicolog yang sangat ahli dalam interpretasi karya J. S. Bach. Selain itu juga mempelajari fortepiano di bawah Prof. Stanley Hoogland.
Setelah lulus dari situ pada tahun 1998 pulang ke Indonesia, lalu melayani sebagai Penginjil Musik di Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) di Jakarta pada Februari 1999. Pada tahun yang sama memulai study Teologi di Institut Reformed di Jakarta. Lulus pada tahun 2002 dengan Master of Christian Studies. Sejak tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan School of Music di Institut Reformed Jakarta serta menggembalakan jemaat Mimbar Reformed Injili Indonesia (MRII) Jerman : Berlin, Hamburg dan Munich. Beliau ditahbiskan menjadi pendeta sinode Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) pada Paskah 2005 dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral di bidang filsafat di Universitas Heidelberg, Jerman. Beliau menikah dengan Suzianti Herawati dan dikaruniai seorang putri, Pristine Gottlob Kristanto.
[1] Bandingkan perkataan Paulus bahwa di antara orang berdosa, dialah yang paling berdosa (1Tim. 1:15).
[2] Luthers Works Vol. 41, American ed., ed. by Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann (St. Louis: Concordia Publishing House; Philadelphia: Fortress, 1958-86), 216.
[3] Bersama dengan Paulus, ia mengatakan, “Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.” (2Kor. 12:10)
[4] D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching and Preachers (Grand Rapids, Mich.: 1972), 79.
[5] Ibid., 80.
[6] Commentary on John 14:26, Calvini Opera Vol. 47, 334-335. Quoted in Haroutunian, Calvin: Commentaries, 397.
[7] Ibid.
[8] T. H. L. Parker, The Oracles of God: An Introduction to the Preaching of John Calvin (London and Redhill: Lutterworth, 1947), 50. Ia mengacu pada Calvini Opera Vol. 25, 646.
[9] Stephen R. Yarborough and John C. Adams, Delightful Convinction: Jonathan Edwards and the Rhetoric of Conversion, Great American Orators, no. 20 (Westport, Conn., and London: Greenwood, 1993), 10.
[10] Lloyd-Jones, Preaching and Preachers, 86.





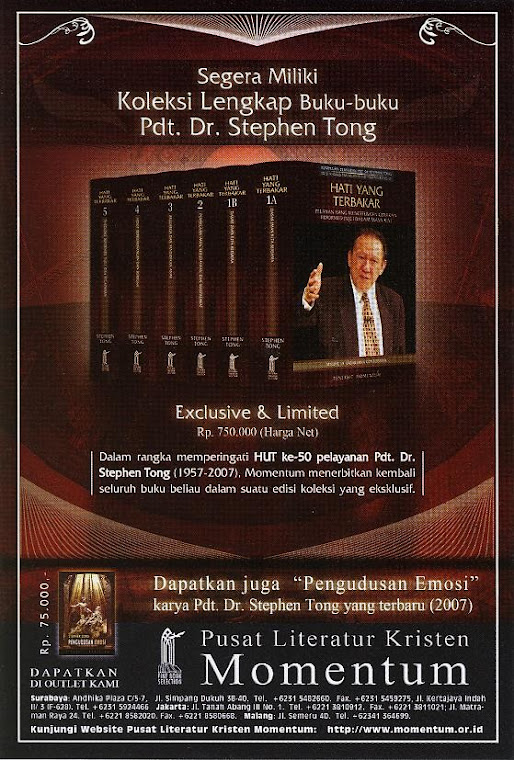
No comments:
Post a Comment