Kemajemukan dan Dialog antar Agama
oleh : Pdt. Billy Kristanto, Dipl.Mus., M.C.S.
Melakukan dialog antar agama memang bukan merupakan hal yang mudah, karena sebelumnya kita perlu menelaah terlebih dahulu apa yang menjadi harapan dari masing-masing pihak dalam dialog tersebut. Tanpa membicarakan hal ini secara terbuka dan jujur, disertai dengan penyataan identitas yang terbuka dan jujur, agaknya sulit untuk berkomunikasi dalam jalur yang sama. Persoalan ini penting karena jika kita mengharapkan dialog yang realistis tentunya kita tidak mengharapkan pembicaraan yang sama-sama 'autis' (saya mendengarkan apa yang saya ingin dengar, bukan apa yang orang lain katakan). Namun sebelumnya kita perlu untuk melihat kesulitan tentang konsep tentang dialog ini terlebih dahulu, karena kita percaya tanpa konsep yang jelas kita tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Salah satu yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu adalah tentang "perbedaan". Bagaimana kita menyikapi perbedaan? Saya pribadi melihat ketidak-dewasaan dalam menanggapi persoalan yang realistis ini seringkali menghambat dialog yang juga realistis dan jujur, dan akhirnya konstruktif serta menghasilkan buah yang baik (fruitful dialog).
Pandangan yang terlebih dahulu kita perlu bereskan adalah semacam konsep ekumenisme yang bagi saya, tidak jujur dan tidak realistis, yaitu ekumenisme yang mengatakan "toh kita pada dasarnya sama, kita tidak perlu membicarakan perbedaan, karena kita ini semua satu, perbedaan hanya memecah-belah". Pandangan seperti ini sebenarnya naif, tidak jujur, paranoid dan tidak dewasa. Model-model ekumenisme yang seperti ini, entah dalam level antar agama, atau antar denominasi dalam satu kepercayaan, akan gagal untuk menciptakan suatu dialog yang kondusif dan konstruktif. Dasar yang ada di balik pandangan seperti ini adalah "perbedaan hanya membawa kepada konflik" dan "konflik akhirnya membawa kepada kekerasan (violence)" dan kita tahu bahwa "violence adalah amit-amit". Di sini kita melihat mitos yang mempercayai bahwa setiap perbedaan hanya akan membawa kepada konflik yang akhirnya menuju kepada kekerasan. Mitos ini, sekalipun bukannya tidak mungkin terjadi atau totally nonsense, juga tidak sepenuhnya benar. Maksudnya, tidak semua perbedaan berakhir pada kekerasan.
Di dalam kepercayaan Kristen kita percaya ada perbedaan yang bersifat komplementer, perbedaan yang saling memperkaya, perbedaan yang tidak perlu bersifat mengancam, perbedaan yang justru meneguhkan dan memperjelas identitas saya baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas yang menganut kepercayaan tertentu. Sikap seperti inilah yang perlu ditekankan dalam dialog yang sehat, jujur dan realistis, daripada mengatakan bahwa "ah, kita sebenarnya toh semua sama".
Di sisi yang lain kita juga harus jujur bahwa ada perbedaan yang tidak bersifat komplementer, maksudnya perbedaan yang tidak dapat lagi dipersatukan, ya, bahkan mungkin tidak bisa di-dialog-kan lebih jauh, karena bagi masing-masing penganut kepercayaan hal itu adalah sesuatu yang prinsipiil dan tidak mungkin dibuang dan ditanggalkan. Pada bagian ini, saya pikir kita juga harus belajar jujur bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu memang ada, dan dalam konteks ini kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain (meskipun kita tahu tetap ada hal yang berbeda yang kita tidak dapat saling setuju satu dengan yang lain). Perbedaan-perbedaan itu sendiri perlu dibedakan lagi, maksudnya, seberapa jauh hal itu penting dan mutlak bagi kepercayaan seseorang. Dengan demikian kita belajar untuk bersikap dewasa dengan sanggup membedakan perbedaan-perbedaan dari tingkat yang saling komplementer sampai kepada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikompromikan. Pada bagian yang terakhir ini kita dituntut untuk belajar saling menghargai satu dengan yang lain.
Kita dapat mengambil contoh untuk perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikompromikan misalnya seperti persoalan apakah “Yesus adalah Tuhan”. Pengakuan seperti ini sulit untuk didialogkan karena bagi kepercayaan Kristen pengakuan ini sangat penting dan tidak mungkin ditanggalkan, sementara bagi kepercayaan lain pernyataan itu bukan hanya tidak penting, melainkan juga tidak benar. Mencari titik temu di antara kedua pandangan (yaitu mempercayai Yesus adalah Tuhan atau Yesus bukan Tuhan) adalah hal yang absurd dan tidak mungkin dilakukan (kecuali kita tidak mengerti hukum kontradiksi atau kita menipu diri).
Pemikir religious pluralism seperti John Hick misalnya mencoba untuk membuat satu payung besar yang diharapkan untuk bisa memayungi semua agama yang mengklaim keunikan kepercayaan mereka masing-masing dengan konsepnya tentang “the Real”. Kalau kita jujur, kita tahu bahwa pandangan ini sebenarnya bukan memayungi semua payung-payung yang lain yang ada di bawahnya, melainkan hanya menambahkan keaneka-ragaman payung yang ada (payung yang ditawarkan oleh Hick adalah payung di antara sekian banyak payung yang lain). Ajaran inclusivisme yang dimengerti dalam konteks ‘payung besar’ ini sebenarnya adalah kebohongan dan kontradiksi dalam istilah. Mengapa? Karena mereka yang menganut pandangan pluralis sekalipun percaya bahwa pandangan mereka (yang pluralis) itu adalah yang paling benar dan paling tepat, dengan demikian pandangan, atau lebih tepat, agama pluralisme tidak luput dari spirit eksklusivisme! Mereka eksklusiv terhadap pandangan yang non-inklusiv. Tapi mungkin sebagian di antara kita ada yang terganggu dengan istilah eksklusiv – inklusiv, kita bisa mengganti istilah tersebut dengan “keunikan” (instead of eksklusivitas) . Pada dasarnya semua kepercayaan, tanpa terkecuali pasti mengklaim keunikan kepercayaan mereka masing-masing, termasuk juga kepercayaan religious pluralisme. Dengan demikian pandangan seperti ini sebenarnya hanya menambahkan jumlah payung agama yang ada, instead of menciptakan satu payung besar di atas payung-payung yang lain. Kejujuran seperti ini perlu sebelum kita memulai suatu dialog yang kondusif dan konstruktif. Persoalan yang lain yang terjadi dalam dialog antar agama adalah memaksakan mendialogkan hal-hal yang memang sulit untuk didialogkan (kita tadi mengambil contoh di atas misalnya seperti pengakuan bahwa “Yesus adalah Tuhan”). Bagian-bagian seperti ini meskipun bukan tidak mungkin sepenuhnya untuk didialogkan (hopefully saya akan kembali pada thema ini lain kali), namun membutuhkan kedewasaan dan sikap saling menghargai satu dengan yang lain, sebab jika tidak yang terjadi bukanlah dialog yang sehat tapi: semangat baku hantam, semangat perang salib, saling menyerang dan menghina satu sama lain, saling menyakiti. Pembicaraan seperti ini tidak konstruktif malah akan menabur spirit kebencian dan inilah yang sebenarnya memang dapat memicu budaya kekerasan. Persoalan yang berikutnya jika kita memaksakan dialog untuk tema-tema yang sentral seperti ini adalah: kita perlu untuk memperhatikan takaran dan kedewasaan iman seseorang (bukan hanya kedewasaan pribadi atau psikologis, tapi juga kedewasaan rohani). Banyak penganut kepercayaan yang tidak siap dalam menghadapi dialog seperti ini, dan instead of iman mereka dibangun, malah menjadi goncang. Semua ini perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Karena itu saya pribadi lebih setuju bahwa toh seandainya dialog mengenai tema-tema sentral seperti itu dilakukan, maka sebaiknya dilakukan di antara para pemimpin agama, dan bukan di dalam forum umum karena tidak semua orang sanggup mencerna makanan keras. Dan kalau toh dialog-dialog seperti ini dilakukan, kita harus jujur dan jelas bahwa tujuannya bukanlah untuk mencari titik temu (karena itu tidak mungkin alias absurd), melainkan untuk memperkaya wawasan satu sama lain, dengan demikian menciptakan toleransi yang lebih dalam dan dewasa karena toleransi itu dibangun di dalam pengertian bahwa kita memang berbeda namun kita tetap bisa mengasihi yang berbeda dengan kita (bagi saya inilah spirit inklusiv yang sejati, yaitu bukan dengan meniadakan dan menindas perbedaan, melainkan dengan tetap belajar mengasihi mereka yang berbeda dengan kita). Kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna di dalam hal ini. Dia yang adalah Allah Pencipta, mengasihi kita manusia yang diciptakanNya, Dia yang Mahakudus mengasihi dan menerima kita yang najis dan berdosa. Allah yang dipercaya di dalam kekristenan adalah Allah yang inklusif, bukan di dalam pengertian dia menutup mata terhadap perbedaan, melainkan dalam pengertian Dia berani menghadapi perbedaan, bahkan mengorbankan AnakNya sendiri mati di atas kayu salib untuk mengatasi perbedaan tersebut di dalam kasihNya. How great Thou art!
Point yang terakhir yang ingin saya sharingkan adalah, jika demikian tema-tema apa yang dapat dilakukan dalam dialog antar agama, jika tema-tema sentral begitu sulit dan membutuhkan kedewasaan yang besar untuk melakukannya? Kita masih dapat melakukan pekerjaan bersama-sama dalam tema-tema yang sama-sama tercakup dalam setiap kepercayaan. Yang saya maksud di sini adalah misalnya seperti tentang keadilan, pendidikan, ekologi, ekonomi, persoalan kemiskinan dan masih banyak yang lain. Kita percaya dalam bagian seperti itu masing-masing kepercayaan dapat memberikan sumbangsih permikiran dan bersama-sama membangun bangsa dan negara yang kita kasihi. Dialog seperti ini tidak menutup mata terhadap perbedaan kepercayaan dalam tema-tema yang sentral, namun dengan sikap yang dewasa belajar untuk menghargai keputusan setiap orang, tidak tertutup juga kemunkinan untuk saling menyaksikan kepercayaan sentral itu kepada penganut kepercayaan yang lain, namun bukan dalam sikap baku hantam dan saling melecehkan, melainkan dalam spirit kesaksian, karena kita percaya yang sanggup membawa manusia dalam pengertian kebenaran bukanlah manusia melainkan Allah sendiri. Dialog-dialog yang dewasa dan bijaksana seperti itu kita harap bukan sekedar menjadi retorika kosong alias excuse untuk menutupi kekurangan kita, melainkan dengan suatu pengharapan bahwa hal seperti itu dapat dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa ini.
Sumber : http://groups.yahoo.com/group/METAMORPHE/message/6198
Profil Pdt. Billy Kristanto :
Pdt. Billy Kristanto, Dip.Mus., M.C.S. lahir pada tahun 1970 di Surabaya. Sejak di sekolah minggu mengambil bagian dalam pelayanan musik gerejawi. Setelah lulus SMA melanjutkan studi musik di Hochschule der Künste di Berlin majoring in harpsichord (Cembalo) di bawah Prof. Mitzi Meyerson (1990-96). Setelah lulus dari situ melanjutkan post-graduate study di Koninklijk Conservatorium (Royal Conservatory) di Den Haag, a conservatory with the largest early music department in the world (mempelajari historical performance practice). Belajar di bawah Ton Koopman, seorang dirigen, organis, cembalis dan musicolog yang sangat ahli dalam interpretasi karya J.S. Bach. Selain itu juga mempelajari fortepiano di bawah Prof. Stanley Hoogland.
Setelah lulus dari situ pada tahun 1998 pulang ke Indonesia, lalu melayani sebagai Penginjil Musik di Gereja Reformed Injili Indonesia/GRII di Jakarta (Februari 1999). Pada tahun yang sama memulai studi theologia di Institut Reformed di Jakarta dan lulus pada tahun 2002 dengan Master of Christian Studies (M.C.S.). Sejak tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan School of Music di Institut Reformed Jakarta serta menggembalakan jemaat Mimbar Reformed Injili Indonesia (MRII) Jerman : Berlin, Hamburg dan Munich. Beliau ditahbiskan menjadi pendeta sinode GRII pada Paskah 2005 dan beliau sedang menempuh studi doktoral di Universitas Heidelberg, Jerman.





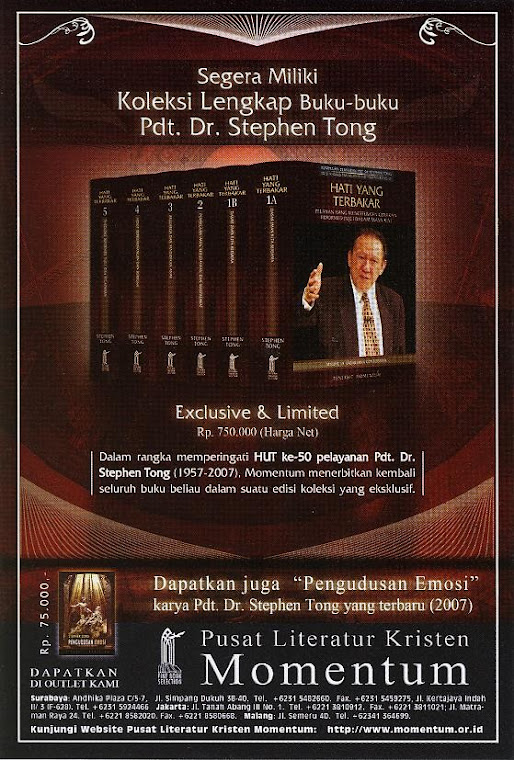
1 comment:
Melihat uraian pak Billy, sebetulnya antar agama bisa terjadi dialog yang sehat. Dari perspektif agama Kristen, kita bisa mencontoh Allah, yaitu 'berdialog' dengan jalan salib. Dengan salib, Allah menghadapi perbedaan.
Kalau pak Billy merasa sulit berdialog hal-hal prinsipal-teologis, jangan-jangan pak Billy sudah jauh dari salib?
Salam,
Rudy Bingtjoro
http://imankristen.com
Post a Comment