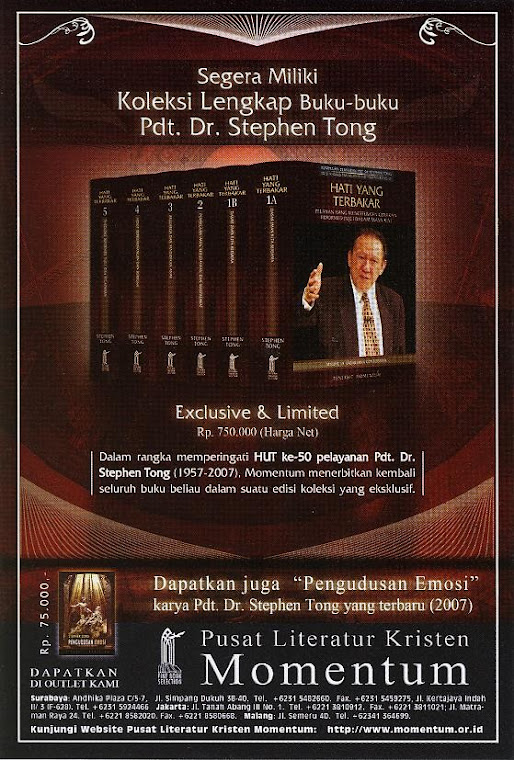IMAN KRISTEN DAN MUSIK
oleh : Pdt. Billy Kristanto, Dipl.Mus., M.C.S.
Iman Kristen dan Musik (1)
Dear beloved brothers and sisters in Christ,
Saya ingin sharing pengertian yang saya dapatkan melalui perjalanan kehidupan saya mengikut Tuhan, khususnya berkenaan dengan musik, suatu bidang yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan saya sejak kecil (namun saya tidak pernah terjatuh ke dalam piano, apalagi tertimpa piano ketika masih orok, seperti halnya Obelix ke dalam ramuan ajaib).
Saya lahir dalam keluarga Kristen, tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang menyukai musik, hanya saja di antara keluarga saya, saya satu-satunya yang diberi kesempatan oleh Tuhan boleh mengembangkan talenta yang Dia berikan melalui suatu pendidikan musik yang formal.
Sejak sekolah minggu saya mulai melayani musik di gereja di mana saya beribadah. Keluarga saya beribadah di Gereja Pentakosta, seperti pada umumnya, kami menggunakan seperangkat alat musik yang membentuk suatu band dalam ibadah. Saya kadang-kadang juga dipercaya untuk ikut bermain di dalamnya, biasanya saya mengisi keyboard atau piano. Ada banyak hal di mana Tuhan membentuk dan menenun kehidupan saya melalui komunitas di tempat ini, di tengah segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Saya menyaksikan teladan orang-orang Kristen yang suka berdoa dan hidup bergantung kepada Tuhan dengan iman yang sederhana. Orang-orang percaya yang dengan tulus melayani Tuhan dengan kerelaan berkorban, hidup memikul salib, tidak takut susah. Orang-orang yang sangat bergairah dalam memberitakan Injil keselamatan, menyaksikannya kepada orang-orang yang belum mengerti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang saling menerima dan mengasihi satu sama lain, sekalipun kita tahu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan serta kelemahannya masing-masing. Namun sekaligus di tempat yang sama saya juga menyaksikan kehidupan yang berkeping-keping, sehabis menerima Perjamuan Kudus yang selalu mengharukan banyak orang, segera melanjutkan konflik dan kepahitan di antara jemaat, keuangan perpuluhan yang tidak jelas digunakan untuk apa, pelayanan yang dimotivasi oleh uang dan kekayaan, termasuk mulai merambatnya ajaran-ajaran kesuksesan (orang Kristen tidak seharusnya sakit, tidak seharusnya miskin) yang menyusup menggantikan ajakan hidup menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ya, Alkitab sendiri mengatakan bahwa realita Kerajaan Allah pun digambarkan oleh Yesus sebagai benih gandum dan ilalang yang tumbuh bersama. Tampaknya konsep steril tentang Kerajaan Allah di mana hanya ada gandum saja merupakan impian yang tidak mungkin akan terwujud selama kita masih berada di dunia ini.
Saya terbentuk dalam suatu kultur yang sangat menggemari pop-culture, suatu kultur yang pada umumnya dapat diterima oleh sebagian besar manusia kesederhanaan kualitas yang tidak harus menuntut penggemarnya untuk banyak berpikir dan mempersoalkannya, surely it’s OK because I feel good, I can enjoy, so I just consume it. Selain musik ini saya sangat akrab dengan musik dangdut yang banyak dikonsumsi oleh karyawan yang bekerja di tempat saya. Keluarga saya tampaknya tidak keberatan untuk menyediakan konsumsi ini sepanjang hari dengan volume suara yang dapat didengar oleh seluruh karyawan, termasuk saya sendiri, sehingga saya sempat hafal paling sedikit puluhan lagu-lagu jenis ini.
Sampai suatu saat saya berkenalan dengan musik jazz yang certainly much more deeper and has a certain depth and quality di dalamnya. Membandingkan jenis musik ini dengan yang selama ini banyak saya konsumsi, saya sadar bahwa yang dulu jauh lebih sederhana daripada yang terakhir, baik di dalam aspek harmony, melody and rhythm. Saya mulai lebih tertarik dengan jenis musik ini bahkan juga belajar untuk bisa memainkannya sendiri, and so God will, pikir saya, saya juga bisa menggunakan kreativitas ini ketika saya melayani di Gereja. Why not? Musical creativity is God’s gift and definitely not from Satan! Dalam kesungguhan saya untuk melayani Tuhan dan dengan motivasi yang saya rasa cukup tulus, saya berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya percaya saya terima sebagai anugerah Tuhan dengan mengembalikannya kepada Sang Pencipta.
Sampai suatu saat saya berkenalan dengan karya piano dari Beethoven, a very simple piece, perhaps not so complicated seperti kebanyakan musik-musik rumit yang sebelumnya saya pernah dengar, tapi juga bukan jenis keserdahanaan seperti musik-musik jenis pertama yang saya pernah konsumsi. Saya mendapati bahwa karya-karya seperti ini berbeda dan memiliki keunikan tersendiri, namun saya belum dapat mengetahuinya dengan jelas mengapa. Saya mulai belajar untuk memainkan jenis musik ini, demikian seterusnya untuk mempersingkat cerita, sampai suatu saat saya akhirnya memutuskan untuk mengambil study jurusan musik setelah lulus dari SMA.
Dalam periode ini saya mulai belajar dan mengaitkan apa yang saya pelajari dan geluti (yaitu bidang musik) dan berusaha untuk mengintegrasikannya dengan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan. Saya tidak puas jika hanya sampai pada batas penguasaan bidang saya pelajari (dalam hal ini musik) di satu sisi, dan di sisi lain pengenalan akan Tuhan yang saya peroleh melalui merenungkan dan membaca firman Tuhan dan buku-buku yang membangun iman saya, tanpa bisa mengaitkan kedua hal ini. Saya sadar bahwa Alkitab memang bukanlah buku musik. Kita akan kecewa jika mencari untuk mendapatkan di dalam Alkitab bagian yang menyatakan penggunaan alat musik tertentu yang lebih “kudus” daripada yang lain, atau jenis musik apa yang disetujui oleh Alkitab (pop-culture kah, dangdut kah, Klassik, Romantik, Barock, postmodern, New Age or Gregorian Chant, atau jangan-jangan musik yang pernah dipakai oleh Daud, yang kita semua sekarang tidak tahu lagi bagaimana merekonstruksinya). Kita juga pasti akan sangat kecewa jika kita berusaha dengan segala kesungguhan untuk mendapatkan dalam Alkitab apakah pada bagian tertentu dari suatu lagi saya lebih baik bergerak ke c-minor atau C Mayor atau ke D7, perlu pakai sus4 atau saya lebih baik diam saja (seperti diusulkan oleh John Cage misalnya).
Saya percaya bagian penjelasan yang seperti itu tidak ada dan memang juga tidak perlu, karena itu akan menjadikan iman kita iman instant yang tidak perlu lagi bergumul. Alkitab menjadi buku pedoman how-to, di mana kita dapat menyelesaikan seluruh persoalan dari rumus fisika, matematika, kimia, persoalan ekologi, ekonomi, science, dan akhirnya juga seni dan musik. Kalau Alkitab harus memuat semuanya seperti layaknya sebuah textbook, kita semua pasti tidak sanggup untuk beribadah dengan membawa Kitab Suci, karena itu berarti saya harus membawa buku dengan berat berton-ton.
Namun ini juga tidak berarti bahwa Alkitab tidak membicarakan tentang ekologi, ekonomi, seni, science dsb. Karena kita percaya ilmu-ilmu itu (logi) sebenarnya berasal dari LOGOS atau Firman. Allah yang menyatakan diriNya melalui firman Tuhan (Maz 19:8-12) adalah Allah yang sama yang juga menyatakan diriNya melalui alam (Maz 19:1-7), yaitu alam di mana manusia menggali dan menemukan berbagai macam disiplin ilmu yang menyatakan kemuliaan Allah di dalamnya. Kita tidak mungkin memisahkan penemuan dalam alam (sebagai wahyu umum Allah) dengan pengenalan melalui firman Tuhan dan di dalam Yesus Kristus (wahyu khusus Allah).
Yang menyedihkan adalah pendapat yang banyak diterima saat ini adalah Alkitab hanya membicarakan kehidupan gerejawi, membicarakan teologi, tapi Alkitab tidak mungkin membicarakan tentang musik, jenis musik, komposisi musik, Alkitab tidak membicarakan semua bidang yang lain, entah itu fisika, geologi, ekologi, ekonomi karena memang Alkitab hanya membicarakan urusan keselamatan jiwa manusia. Dengan kata lain: ilmu-ilmu tersebut silahkan independen dari Alkitab, Alkitab tidak usah mencampuri hal itu karena kedua hal tersebut adalah hal yang terpisah satu dengan yang lainnya. Konsekuensi dari pandangan seperti ini adalah: kita boleh menggunakan dan menkonsumsi jenis seni/musik apapun, kita boleh memiliki pandangan ekonomi apapun, teori ekologi juga terserah, karena science adalah wilayah fakta sedangkan Alkitab berbicara dalam wilayah nilai. Maka kita harus memisahkan keduanya. Teori seperti ini sebenarnya bukanlah apa yang kita terima dari Firman Tuhan, melainkan suatu dualisme yang diciptakan oleh para pemikir enlightenment. Pandangan seperti ini langsung akan menyediakan angin untuk sekularisme masuk ke dalam semua bidang, karena di situ kerajaan Kristus (the kingship of Christ) tidak boleh dinyatakan dalam bidang apapun kecuali teologi (itupun kalau masih ada kekuatan!). Bidang-bidang yang lain pada akhirnya akan diisi oleh isme-isme yang lain, sinful culture yang tidak tunduk pada Alkitab segera akan meresap ke dalam bagian-bagian yang dengan sengaja dibuka untuk dibebaskan dari otoritas firman Tuhan. Kita sekarang berada dalam keadaan pengaruh ecological disaster yang makin lama akan makin mengerikan. Di mana pengaruh pandangan Kristen terhadap ekologi? Tidak perlu? Karena Alkitab tidak membicarakan geologi, sama seperti juga tidak membicarakan c-minor or a-minor? Kita tidak boleh membicarakan teori Adam Smith berdasarkan perspektif Alkitab karena Alkitab adalah buku teologi? Biarkanlah Picasso dan Polluck mengembangkan talenta dan kreativitasnya, itu toh juga berasal dari Tuhan? Kalau seandainya John Cage dan Stockhausen mengusulkan musiknya dipakai dan dipergunakan untuk ibadah, kita pasti selalu akan ada tempat untuk memberikan akomodasi berbintang lima baginya, sebab hati kita sangat luas, kita bukanlah orang-orang sempit yang tidak bisa menerima keaneka-ragaman?
Welcome to our contemporary time: a world with an almost unlimited possibilities to embrace and accomodate all theories of ecology, economy, politics, aesthetics, science, sociology … (BTW we don’t even know which one is ecology, economy, sociology, theology, sociology … it looks all the same).
I’m terribly sorry to stop here today, and thank you for listening my confused thoughts. I really hope I may have the same patience as yours …. and the strength .... to continue ….
Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (Augustinus).
Iman Kristen dan Musik (2)
Di bagian pertama kita sudah membahas bahwa tidak mungkin untuk membiarkan suatu ilmu independen dari penilaian Firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang baik (I Tes 5:21). Tidak menguji adalah suatu bentuk ketidak-taatan terhadap ayat ini. Sayangnya, kita sekarang berada dalam suatu kondisi dunia yang mendiscourage segala pengujian. Orang yang berusaha untuk menguji dikatakan berpikiran sempit, tidak memiliki spirit toleransi, tidak mempunyai kasih, bahkan suka menghakimi. Dunia lebih suka berada dalam suatu keadaan di mana segala sesuatu sebisa mungkin dianggap netral, dengan demikian persoalan salah – benar, kudus – tidak kudus, baik – buruk, tidak akan menyusahkan manusia lagi.
Kita berada dalam perubahan budaya modern dan pasca-modern sekaligus. Mythos yang keliru dari orang-orang modern adalah percaya satu-satunya kebenaran tunggal yang harus diterima secara seragam dengan menolak semua perbedaan yang ada. Sementara dalam kebudayaan pasca-modern ada kecenderungan untuk mengakomodasi semua perbedaan yang ada, budaya merayakan keaneka-ragaman, termasuk juga siapa pun berhak membicarakan segala sesuatu, karena manusia tidak percaya lagi adanya suatu jawaban otoritatif yang dianggap mengulang kesalahan modern totaliterism atau bahkan kesalahan gereja pada jaman abad pertengahan (yang dipersoalkan oleh Luther). Sejarah biasa bergerak dari suatu pendulum dari satu arah ke arah yang lain. Sebagai orang percaya, kita perlu kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, instead mengikuti begitu saja semangat jaman tanpa melakukan suatu refleksi kritis terhadapnya.
Alkitab menyatakan kebenaran memang tunggal (dalam pengertian ada kesatuan/unity, sifat koherensi di dalamnya). Kebenaran selalu bersifat integratif dan tidak mungkin fragmented. Sekaligus kata integrasi atau unity sebenarnya menyatakan adanya aspek pluralitas/diversitas di dalamnya. Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, sekaligus dalam tiga Pribadi. Demikian juga metafor banyak anggota satu tubuh, dan juga banyak karunia satu Roh menyatakan hal yang sama. Di dalam kultur modern selalu ada ketakutan terhadap perbedaan, perbedaan selalu dianggap sebagai ancapan terhadap kesatuan (unity), di mana unity cenderung dimengerti sebagai uniformity (maksudnya tidak boleh ada perbedaan). Sementara dalam pasca-modern kecenderungannya sekali lagi adalah merayakan diversitas, namun diversitas ini akhirnya menimbulkan division atau fragmentasi karena kita tahu memang tidak mungkin untuk mengakomodasi semua pluralitas, menyambut semua keaneka-ragaman dalam hidup sama dengan tindakan memecah-belah diri alias memeluk suatu kehidupan yang fragmented (baca: tidak memiliki integrasi).
Dalam jaman seperti ini, pemahaman tentang karunia-karunia rohani yang berbeda-beda, dan juga penggalian talenta yang berbeda-beda (bukan hanya jenis tapi juga takarannya), merupakan hal urgent yang harus digumulkan oleh setiap orang percaya. Dengan runtuhnya paradigma modern totaliterism, absolut otoriterism, sekarang orang berada dalam keadaan confusion, karena sekarang seolah setiap orang berhak bicara apa saja, setiap orang boleh menjadi guru, setiap orang boleh mengajar yang lain, sementara ia sendiri mungkin tidak jelas pimpinan Tuhan secara khusus di dalam dirinya. Dalam jaman seperti ini kita cenderung kehilangan pengertian akan keunikan diri sendiri, di mana Tuhan menempatkan saya dalam Kerajaan Allah. Orang yang memiliki talenta A mencoba untuk mengerjakan talenta H, orang yang memiliki takaran 1 talenta mencoba mengerjakan porsi 5 talenta, sementara yang memiliki 5 talenta begitu “rendah hati” dengan mencukupkan diri puas dengan hasil 1 talenta. Orang yang tidak memiliki karunia X memaksakan diri untuk tampil sebagai orang yang berkarunia X, sementara yang sungguh-sungguh dipercayakan Tuhan dengan karunia X tidak puas dengan hal itu dan mencoba untuk mengambil karunia A.
Yang jelas, banyak orang tidak sabar (I’m certainly one of them!) dengan masa pembentukan padang gurun selama 40 tahun yang merupakan periode sangat penting dalam kehidupan Musa. Sejujurnya kita lebih suka mengajar orang lain daripada diajar, memimpin orang lain daripada dipimpin, menasihati orang lain daripada dinasihati, mengubah orang lain daripada sendiri terlebih dahulu diubahkan oleh Tuhan. Humility is a very rare jewel in our age, isn’t it? Kita ingin apa yang kita katakan berdampak begitu besar dan semua orang mendengarkan kita dengan terangguk-angguk, tapi kita sendiri tidak suka mendengarkan orang lain. Orang yang tidak dipanggil menjadi ekonom berbicara banyak tentang ekonomi, mereka yang tidak mempelajari seni membicarakan segala sesuatu tentang seni, yang bukan fisikawan mengajar kelas tinjauan iman Kristen terhadap fisika, dan yang paling kacau: tidak mengerti teologi berani bicara di atas mimbar! Everybody can teach everything. This is a very sad condition.
Saya pribadi merindukan suatu kebangunan rohani yang menyentuh salah satu aspeknya: kebangunan pelayanan kaum awam, di mana setiap anggota tubuh Kristus menyadari keunikan panggilannya masing-masing, mengenal karunia tertentu yang pasti Tuhan percayakan dalam hidupnya, seumur hidup menjalankan talenta tertentu dengan takaran tertentu yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Saya tidak perlu menjadi gelisah apalagi iri dan marah-marah jika di dalam Kerajaan Allah saya mendapati orang lain jauh lebih menguasai ekonomi daripada saya, karena itu mungkin adalah panggilan Tuhan di dalam dirinya dan bukan panggilan saya, biarkan dia mengajar bidang yang dia gumuli bersama dengan Tuhan lalu menjadi berkat bagi keKristenan. Mengapa saya harus memaksakan diri menjadi guru dalam semua bidang? We should follow the biblical story, the story of the gospel, rather than Superman story, to shape our life. We are created, we have our limitation. Mengapa tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan hal-hal yang sungguh Tuhan percayakan di dalam hidup kita masing-masing dengan mempertahankan keluasan pandangan Kerajaan Allah (supaya kita tidak menganggap beban kita yang paling penting daripada semua yang lain), sehingga ada kekuatan yang saling melengkapi satu sama lain? Kelebihan orang lain mencukupkan kekurangan saya, sementara kelebihan saya mencukupkan kekurangan orang lain sehingga terjadi keseimbangan seperti dikatakan oleh Paulus. Mari kita belajar saling mengasihi satu sama lain dengan terus mempertahankan kerendahan hati untuk semakin mengenal kebenaran Allah dan sesuai dengan janjiNya, jika ada sesuatu yang berlainan di antara kita, maka Tuhan juga yang akan menyatakannya. Sola gratia, Soli Deo Gloria!
I'd like to thank God for the beautiful weather today ... despite the theo- and eco- logical confusion in our time ... May God bless you abundantly today and give you all a reason to smile, because God loves you :)
Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (Augustinus).
Iman Kristen dan Musik (3)
Pada bagian yang kedua kita sudah membahas kecenderungan baik kebudayaan modern yang anti perbedaan dan menekankan konsep unity in uniformity, dengan kebudayaan pasca-modern yang merayakan pluralitas namun akhirnya jatuh ke dalam disintegritas atau fragmentasi. Firman Tuhan memberikan alternatif yang jauh lebih indah daripada kedua kebudayaan yang sangat mewarnai kehidupan kita di atas. Konsep multi-dimensi atau multi-perspektif bukanlah konsep yang asing bagi firman Tuhan karena firman Tuhan mengajarkan kesatuan dalam keaneka-ragaman. Namun di sisi yang lain, firman Tuhan juga memberikan prinsip agar kita tidak jatuh dalam chaotic pluralism, di mana setiap orang berjalan sesuai dengan apa yang dia pandang baik, sesuai dengan pandangan subyektifnya masing-masing, selera yang membentuk dia sejak kecil, relativisasi kebudayaan yang dibuat independen dari penilaian firman Tuhan. In fact kita percaya bahwa kebudayaan manusia sendiri merupakan campuran antara penaburan benih gandum dan lalang. Adalah suatu kefatalan jika kita sebagai orang percaya berpikir bahwa budaya netral adanya. Ada godly culture ada pula sinful culture. Culture pun suatu saat akan dihakimi oleh Tuhan sendiri.
Sekarang bagaimana dengan musik? Sebagai bagian dari culture, musik juga tidak bebas dari nilai. Kita sudah membahas pada bagian yang pertama jika kita berusaha untuk membebaskan musik dari penilaian firman Tuhan, sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya sekularisme ke dalam musik. Keengganan orang percaya untuk “menguji segala sesuatu dan memegang yang baik” akan semakin menyuburkan angin sekularisme. Lalu bagaimana kita menguji musik? Saya percaya tidak cukup hanya dengan prinsip telos (seperti diusulkan Sdr. Jimmy misalnya).
[1] Kita harus selalu kembali kepada Firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang terjebak pada ajaran-ajaran fragmented yang ditawarkan oleh dunia ini. Alkitab membicarakan bukan hanya telos saja yang harus benar, melainkan means untuk mencapai tujuan ke situ juga harus benar dan kudus ditambah lagi sedikitnya dengan motivasi kita juga harus kudus, yaitu kasih.
[2] Tiga hal ini adalah merupakan hal minimal yang harus digenapi untuk melakukan suatu pengujian yang Alkitabiah.
Mari kita melihat kehidupan Yesus Kristus sendiri. Dalam sepanjang hidupNya Ia selalu menjaga tujuan hidup yang benar (teleological), sekaligus Alkitab mencatat bahwa Ia tidak pernah berbuat dosa, Yesus tidak pernah memakai sarana-sarana apa pun juga asal saja mencapai goal yang benar dalam pelayananNya. Jesus always does the right thing (aspek deontological), He is truth Himself (yang ini saya tidak sanggup memberikan kategori apa-apa karena kalimat ini terlalu dalam dan kaya sehingga tidak dapat direduksi dengan satu/dua kategori), dan Ia adalah penyataan kasih Allah dalam wujud Pribadi yang berinkarnasi, turun ke dunia (menjawab tuntutan situation ethics). Saya percaya, selain tiga hal ini (teleological, deontological and situational) masih banyak aspek yang lain yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus Kristus. Tidak ada habisnya kita mengagumi serta menggali dari kelimpahan hidup yang ada padaNya.
Kembali kepada musik, jika kita ingin melakukan suatu pengujian yang lebih komprehensif dan bertanggung-jawab, selain menguji tujuan serta motivasinya yang harus kudus dan benar, kita juga harus menguji musiknya sendiri: is it the right or wrong music? Is it good music or bad music? Is it holy or sinful?
Tentu dalam realitanya, kita tidak dapat melakukan pemisahan putih-hitam karena kita percaya dalam kejahatan yang bagaimanapun selalu masih ada anugerah Tuhan yang menahan dari kerusakan yang serusak-rusaknya, ada common grace (anugerah umum) yang tetap menyatakan secercah kebaikan di dalamnya.
[3] Demikian halnya dengan musik, tidak ada musik yang serusak-rusaknya sehingga tidak mungkin menjadi lebih rusak lagi (karena sudah terlalu rusak), selalu ada ruang untuk setitik (atau mungkin dua – tiga titik J) keindahan di dalamnya. Sebaliknya, tidak ada musik atau seni yang begitu sempurna sehingga dikatakan musik ini adalah musik yang tanpa cacat sesuai dengan selera Tuhan (itu mungkin pengharapan eskatologis, bukan di dunia yang berdosa ini), bagaimanapun musik adalah hasil karya manusia yang berdosa, yang tidak sempurna, yang di dalam Yesus Kristus boleh berharap bahwa hari demi hari ia semakin dikuduskan dan disempurnakan.
NAMUN, ini tidak berarti bahwa karena semua musik toh tidak ada yang sempurna, selalu merupakan campuran antara yang baik dari Tuhan dan kelemahan manusia yang berdosa, kalau begitu semua musik sama adanya.
[4] Tidak sama. Ada musik yang sangat dipengaruhi oleh keindahan Firman Tuhan, namun ada pula yang dibentuk dari spirit yang sangat melawan Tuhan (yang juga ternyata dalam komposisi musiknya).
Sampai di sini saya ingin share apa yang saya pelajari dalam pergumulan pribadi saya mengikut Tuhan khususnya dalam integrasi Firman Tuhan dan musik. Memang, sekali lagi, Alkitab tidak membicarakan nada-nada dan juga tidak dimaksudkan sebagai textbook untuk semua logi. Namun Alkitab membicarakan mengenai apa itu keindahan. Keindahan menurut konsep Firman Tuhan tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dengan kebenaran, kekudusan, kesalehan, keadilan, kebaikan dsb. Adalah suatu kecelakaan besar di jaman kita yang selalu terbiasa dan latah mengatakan apa yang dipercaya oleh para penganut agama subjectivism bahwa keindahan semata-mata hanya tergantung pada mata si pelihat (beauty in the eyes of the beholder). Mengapa saya sebut musik ini indah? Karena memang itu indah bagi saya. Saya sejak kecil sudah terbiasa mendengar musik ini, saya dibesarkan dalam selera musik ini, maka musik ini indah.
Kita tidak menyangkali bahwa apa yang kita percaya sebagai kebenaran tidak mungkin lepas dari kontext kebudayaan yang membentuk kita (termasuk di dalamnya selera musik yang mewarnai hidup kita sejak kecil), namun ini tidak berarti bahwa dalam pengujian musik yang benar dan baik semata-mata hanya diwarnai oleh bias subyektif dan tidak ada standard atau kriteria obyektif di dalamnya.
[5] Sekali lagi saya menghimbau, adalah lebih bijaksana bagi kita untuk tetap kembali kepada Firman Tuhan, instead of diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dari filsafat-filsafat dari dunia yang melawan Tuhan kita.
Jika kita percaya pandangan bahwa segala sesuatu yang kita anggap benar sebenarnya adalah merupakan produk selera subyektif kita, maka berdasarkan prinsip ini kita juga bisa mengatakan: “Yesus Kristus adalah Tuhan bagimu, itu karena engkau dibesarkan sejak kecil dalam keluarga Kristen. Pantes saja engkau berselera terhadap ajaran Yesus, pantesan engkau menyebut Dia Tuhan.” Berapa banyak di antara kita di sini yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat namun tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, tidak mendengar pembentukan kebudayaan cerita-cerita sekolah minggu sejak kecil? Saya percaya tidak sedikit dan saya percaya masih banyak yang akan menyusul. Apakah Yesus baru menjadi Tuhan lantaran bias subyektif kita sebagai orang Kristen? Kita berani berkata, “Entah saya percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak, Yesus tetap adalah Tuhan.” Yesus Kristus Tuhan adalah suatu fakta kebenaran obyektif yang tidak dipengaruhi oleh kepercayaan subyektif saya sebagai orang Kristen. Hanya saja, memang ketika saya tidak mempercayaiNya sebagai kebenaran yang subyektif (maksudnya hal itu juga saya imani secara pribadi), kebenaran itu tidak menjadi kebenaran yang menyelamatkan saya, namun bahwa itu tetap adalah kebenaran adalah suatu fakta yang tidak dapat diubah (meskipun saya tidak mempercayainya).
Adalah suatu kebohongan dari dunia ini bahwa segala sesuatu yang kita percaya dan kita anggap benar semata-mata adalah kepercayaan serta pandangan subyektif yang tidak ada dasar obyektivitasnya sama sekali. Ketidak-percayaan terhadap pencarian kebenaran yang bersifat obyektif ini,
[6] atau sederhananya: “kebenaran yang sejati”, dengan menggantikannya dengan sikap “ah, itu kan selera kamu, itu kan pandangan subyektif kamu belaka” adalah suatu penghinaan terhadap Allah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebagai yang “akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran” (Yoh 16:13). Kita menganggap Roh Kudus tidak cukup berkuasa untuk memimpin kita ke dalam kebenaran yang sejati seperti dijanjikan Yesus. This is a very serious sin! Dan yang lebih kacau adalah: dunia menuduh bahwa orang yang masih mempertahankan iman yang sederhana bahwa ada kebenaran transendental yang terlepas dari selera subyektif kita, karena itu diturunkan dari atas, dari Bapa segala terang, yang padaNya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran (Yak 1:17), tidak ada kepalsuan di dalamNya, orang yang masih percaya seperti itu adalah orang-orang yang tidak jujur dan sedang berbohong!
Kalau boleh sedikit saya sharing dari perjalanan hidup saya pribadi, ada saat-saat yang menyakitkan dalam kehidupan saya di mana saya harus belajar melepaskan selera saya yang tidak kudus dan menggantikannya dengan yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Ada musik-musik tertentu – mungkin terlalu general mengatakan musik-musik tertentu – katakanlah lagu-lagu tertentu, yang tadinya saya sukai dan gemari berdasarkan selera pribadi saya, sekarang saya menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak membangun, bukannya tidak boleh (I Kor 10:23), karena pandangan hidup kebebasan Kristen bukan persoalan boleh – tidak boleh, melainkan bahwa di dalam kebebasan saya sebagai orang percaya, saya tidak memerlukan hal itu lagi, ada hal yang jauh lebih indah, berharga dan nikmat yang Tuhan sediakan bagi saya. Di sisi yang lain, ada hal-hal yang tadinya saya sangat tidak berselera untuk melakukannya, namun karena saya mengetahui bahwa itu adalah perintah Tuhan, saya belajar untuk menyangkal diri dan mengubah selera saya yang tidak selalu benar dan kudus.
Ah, sudah tiga halaman lebih saya menulis, hari ini sampai di sini dulu. Hopefully, next time masih bisa sharing lagi. Kiranya Tuhan sumber segala berkat mengaruniakan kepada kita sekalian hidup dalam segala kelimpahan (Yoh 10:10).
[1] Sebenarnya pandangan yang hanya menekankan the ultimate goal dalam disiplin ilmu disebut teleological ethics. Pandangan utilitarianisme sangat dekat dengan konsep seperti ini. Kecenderungan konsep demikian adalah: yang penting tujuannya baik, ada manfaat dan hasil yang terlihat, caranya, jalannya, sarananya, whatever it is, doesn’t matter. Pandangan etika seperti ini bersifat reduktif dan karena itu kurang komprehensif dan integratif.
[2] Kembali di sini kita melihat bahwa baik teleological ethics, deontological ethics (it is the right thing to do) maupun situation ethics (yang menekankan motivasi kasih) memiliki kelemahan serta kesempitannya masing-masing.
[3] Orang suka mengatakan tentang hal ini “Jam rusak pun dalam satu hari paling sedikit cocok dua kali”.
[4] Kita dapat memberi analogi di sini yaitu teologi. Teologi pun merupakan hasil karya manusia yang berdosa yang berusaha untuk taat serta merefleksikan Firman Tuhan dalam kehidupan yang sementara ini. Tidak ada teologi yang sempurna, yang dapat dikatakan infallible, setara dengan Alkitab. Namun ini tidak berarti bahwa semua teologia pasti sama dan semuanya relativ adanya. Ada teologi dengan tingkat kerusakan minor, ada teologia dengan tingkat kerusakan sangat parah, ada pula teologi yang – kita sungguh dibuat sangat bingung – mengapa hal seperti itu masih bisa disebut teologi!
[5] Indeed, banyak pemikir postmodernist sekuler yang menganut pandangan seperti ini (saya mengatakan sekuler karena tidak semua pemikir kontemporer menyembah ilah jamannya, masih ada sebagian pemikir yang mempertahankan iman yang sederhana kepada ajaran Alkitab sembari terus kritis menyikapi Zeitgeist yang ditawarkan oleh dunia ini).
[6] Maafkan keterbatasan bahasa saya, jika di sini terpaksa menggunakan kutub “subyektif-obyektif” yang sangat berbau Cartesian untuk menjelaskan tentang iman Kristen.
My conscience is captive to the Word of God. ... for to go against conscience is neither right nor safe (Luther at the Imperial Diet of Worms).
Iman Kristen dan Musik (4)
Pada bagian 1-3 kita sudah membahas bahwa kebudayaan tidak bebas dari nilai moral. Tidak ada kebudayaan yang netral. Jika kita percaya kebudayaan bersifat netral maka konsekuensi logisnya adalah kita sebagai orang Kristen tidak perlu menjalankan mandat budaya, karena yang disebut mandat budaya adalah pengaruh filsafat Firman Tuhan yang dipancarkan dalam kebudayaan yang bersifat transformatif. Jika tidak relevan membicarakan apakah suatu kebudayaan merupakan suatu kebudayaan yang baik, kudus dan berkenan kepada Allah atau sebaliknya buruk, banyak dipengaruhi sifat dosa, merusak dsb, maka seluruh pembicaraan tentang transformasi kebudayaan adalah sia-sia dan juga tidak relevan.
Sebagaimana kita tahu, musik termasuk atau menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Sama seperti di atas jika kita menerima pandangan musik netral sepenuhnya (hal mana sebenarnya sulit untuk dipertahankan dengan dasar alkitabiah) maka pembicaraan tranformasi kuasa Firman Tuhan di dalam musik juga tidak terlalu relevan. Yang paling banyak dipikirkan dalam pandangan seperti ini adalah: ya, beri saja teks firman Tuhan di dalamnya, maka musik otomatis akan mengalami transformasi. Pandangan seperti ini sebenarnya dangkal dan kurang bertanggung-jawab. Ini mirip dengan orang yang menggumulkan bagaimana mentransformasi dunia pekerjaan berdasarkan prinsip Kristen dengan mengadakan persekutuan kantor atau berdoa sebelum saya memulai pekerjaan.
[1] Pandangan seperti ini sayangnya banyak dianut oleh kaum Injili. Asal di dalamnya ada teks firman Tuhan, otomatis menjadi lagu Kristen yang baik dan memuliakan Allah.
Dalam tulisan yang lalu kita juga sudah membahas bahwa dengan menguji telos saja sebenarnya bersifat reduktif dan akhirnya salah. Setiap reduksi yang dipertahankan akan selalu membawa kerugian bagi kita dan orang-orang yang kita layani karena ini sama dengan menolak pertumbuhan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan.
[2] Saya pikir sebagai orang Kristen, adalah lebih baik bagi kita untuk lebih mengikuti Alkitab daripada ajaran-ajaran dunia seperti utilitarianism dan pragmatism. Banyak ajaran-ajaran yang seolah-olah berasal dari Alkitab namun tanpa kita sadar sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia. Kita dapat memberikan satu argumentasi lagi dari Alkitab sendiri bahwa bagi Allah bukanlah hal yang basa-basi ketika Ia menuntut agar yang dipersembahkan kepadaNya adalah korban domba yang tidak bercela, yang tidak bercacat (Imamat 22:21). Di sini kita melihat bahwa bukan hanya tujuannya yang perlu diuji dan diperhatikan, demikian juga motivasi saja tidak cukup, melainkan juga termasuk apa yang dipersembahkan itu sendiri harus diuji. Tidak semua layak dipersembahkan kepada Tuhan.
Beberapa ini contoh dari firman Tuhan bahwa orang-orang saleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan:
· Abraham mempersembahkan roti bundar dari tiga sukat tepung yang terbaik (Kej 18:6)
· Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN, Allahmu. Janganlah kaumasak anak kambing dalam susu induknya (Kel 23:19)
· Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya (Kel 34:26)
· Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada TUHAN, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya (Imamat 2:1)
Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa apa yang kita persembahkan kepada Tuhan juga harus kita uji. Tidak cukup hanya dengan menguji asal tujuan dan motivasinya saja benar.
Sekarang pertanyaannya: bagaimana kita bisa menguji musik itu sendiri sebagai apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Karena sebagaimana sering dikatakan: Alkitab tidak membicarakan nada-nada. Memang tidak, dan juga tidak perlu, tapi Alkitab membicarakan tentang apa itu keindahan, filsafat keindahan menurut sudut pandang Alkitab dan bahwa seni tidak mungkin terlepas dari filsafat keindahan (atau filsafat ketidak-indahan :) yang ada di dalamnya. Bagian inilah yang bisa dibenturkan (baca: diuji berdasarkan firman Tuhan).
Dalam study saya pribadi saya mempelajari bahwa memang tidak ada satu-satunya jaman yang menghasilkan estetika musik yang alkitabiah. Kalau kita menerima ajaran Alkitab kita akan sangat berhati-hati uniformitas seperti diajarkan dalam modernism (hanya ada satu-satunya jenis musik yang benar dan Alkitabiah). Pandangan demikian bukan ajaran Alkitab karena Alkitab memberitakan tentang diversitas atau keaneka-ragaman. Allah Tritunggal adalah Allah di dalam tiga Pribadi, bukan satu-satunya Pribadi. Namun di sisi yang lain, kita juga tidak menerima pandangan pluralisme radikal yang mengatakan bahwa semua jenis musik dapat dipergunakan. Pandangan ini berasal dari filsafat kontemporer yang merupakan pendulum sebaliknya dari modernism. Kita tahu bahwa Alkitab memang membicarakan pluralitas tapi Alkitab memberitakan pluralitas yang terbatas. Menerima semua pluralitas, saya kuatir, sebenarnya hanya merupakan respon simetris dari kesalahan modernism. Dalam jaman seperti ini saya percaya salah satu karunia yang sangat penting adalah karunia membedakan bermacam-macam roh (I Kor 12:10). Tanpa karunia ini Gereja akan tersesat ke dalam pluralisme radikal, mengakomodasi semua pluralitas tanpa merefleksikan atau mengujinya apakah keaneka-ragaman itu dibenarkan oleh Firman Tuhan atau tidak.
Dalam musik berlaku prinsip yang sama. Tidak ada satu-satunya jenis musik yang benar dan Alkitabiah (modern uniformitas), sebaliknya juga tidak benar mengatakan semua jenis musik adalah benar dan kudus (unreflected pluralism kontemporer). Saya coba sharing dari beberapa karya musik di mana kita dapat menguji bahwa ada estetika yang dipengaruhi oleh Alkitab atau wahyu umum, ada juga yang sebenarnya dipengaruhi bukan oleh filsafat sekuler yang tidak setia kepada Alkitab. Dua tokoh yang coba untuk dinilai di sini adalah J.S. Bach dan John Cage.
[3] Ada beberapa argumentasi yang salah untuk menilai bahwa Bach pasti lebih baik daripada Cage, misalnya:
[4] Bach adalah komponis Jerman dan Cage komponis Amerika.
Tanggapan: argumentasi ini tidak dapat diterima karena yang alkitabiah tidak ditentukan oleh ras atau bangsa tertentu. Yang dari Barat bisa alkitabiah bisa tidak, yang dari Timur bisa alkitabiah bisa juga tidak.
Bach artinya sungai kecil, dengan demikian lebih menyatakan kehidupan Kristen yang seharusnya mengalirkan berkat, sementara Cage artinya adalah kurungan alias tidak bebas, maka seperti belum ditebus. Tanggapan: penyelidikan ‘etimologis’ seperti ini tampaknya tidak terlalu berguna dan mengada-ada.
Bach dimulai dengan huruf B seperti kata “better” sementara Cage dengan huruf C seperti “chaotic”. Tanggapan: argumentasi ini lebih mengada-ada dan konyol.
Bach, sebagai seseorang yang hidup di jaman Barock lebih banyak menggunakan wig (rambut palsu) daripada Cage yang hidup di jaman kita. Tanggapan: wig (rambut palsu) sama sekali tidak berperan dalam komposisi yang alkitabiah atau tidak. Demikian kita dapat menambahkan beberapa argumentasi konyol yang lain, namun mungkin ada 1 argumentasi lagi yang mirip dengan yang di atas dan sebenarnya juga konyol, namun banyak diterima yaitu:
Bach adalah komponis jaman Barock, dengan demikian ia adalah tradisional sementara Cage adalah komponis kontemporer. Argumentasi ini konyol karena yang alkitabiah bisa terjadi di masa lampau maupun di masa sekarang, sementara yang rusak dan yang melawan Alkitab juga bisa terjadi di masa lampau dan juga masa sekarang. Perdebatan musik yang berkecimpung antara musik tradisional dan kontemporer sebenarnya membuang-buang tenaga yang seharusnya bisa dipergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik bagi Tuhan. Persoalannya bukan mengenai musik masa lampau dan musik kontemporer, melainkan pengujian estetis menurut terang firman Tuhan.
Seperti kita tahu, Bach yang rada old-fashioned itu masih menggunakan teknik komposisi polyphonic music dengan cantus firmus sebagaimana digunakan dalam jaman sebelumnya (Renaissance dan middle ages). Bach bukanlah satu-satunya komponis yang menggunakan teknik ini, malahan dia sendiri belajar hal ini dari komponis-komponis sebelum dia. D. Bonhoeffer (seorang teolog dan juga seorang pianis yang berbakat) pernah menjelaskan tentang kasih dengan mengatakan bahwa kasih kita kepada Kristus seperti cantus firmus sedangkan kasih kepada sesama adalah seperti polyphonic counterpoint yang dirajut berdasarkan cantus firmus itu. Apa yang dikatakan Bonhoeffer sebenarnya bukan dari pemikiran dia sendiri, melainkan yang terjadi lebih dahulu adalah estetika kristologis (Kristus sebagai fokus yang mempersatukan keaneka-ragaman) mewarnai penggarapan musik mulai dari abad pertengahan dan diteruskan sampai kepada Bach. Musik seperti itu indah (menurut pengertian Alkitab) karena dipengaruhi oleh estetika yang alkitabiah.
Yang dilakukan Bonhoeffer sebenarnya hanya menggunakan insight musical untuk menjelaskan teologinya, sementara insight musical itu sendiri dipengaruhi oleh pemikiran dari Alkitab. Selain Bonhoeffer, teolog yang kadang-kadang membicarakan integrasi antara teologi dan musik adalah Karl Barth, Hans Urs von Balthasar dan terutama belakangan ini Jeremy Begbie (Cambridge). Begbie berusaha untuk menelaah lebih banyak musical language untuk memberikan insights bagi teologi. Bagi saya pribadi, penarikan seperti ini sangat mungkin karena banyak karya musik dari tradisi Barat yang sangat dipengaruhi oleh estetika alkitabiah. Ini tidak menyatakan bahwa Barat lebih superior dari Timur, melainkan karena tradisi kebudayaan mereka banyak dipengaruhi oleh Alkitab sehingga kebudayaan yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang tinggi.
[5] Di samping itu kita juga melihat bahwa di Barat juga banyak kebudayaan yang dihasilkan dari spirit yang melawan Tuhan (mis. violence, anti-otorian, egalitarian, materialism, konsumerism, hedonism etc), yang juga tercermin dalam karya seni mereka. Kebudayaan yang dipengaruhi oleh filsafat Firman Tuhan pasti lebih tinggi (lebih baik, lebih kudus, lebih indah, lebih membangun) daripada yang dipengaruhi oleh filsafat yang melawan Tuhan.
Sekarang kita coba melihat karya John Cage, juga dari Barat, misalnya karya ‘monumental’nya yaitu 4’33’’.
[6] Atau karya lain yang diberi judul HPSCHD di mana 7 pemain harpsichord sekaligus memainkan cuplikan dari karya Cage secara ‘kebetulan’ (chance-determined) ditambah dengan suara-suara elektronik yang lain, atau Imaginary Landscape No. 4 yang ditulis untuk 12 radio. Pada karya yang terakhir ini sekalipun Cage memberikan instruksi bagi para ‘pemain’ radio itu, ‘musik’ yang dihasilkan darinya tidak pernah mungkin bisa dikontrol (kita tidak tahu gelombang hari itu mengeluarkan bunyi apa). Ide “musical happenings” ini merupakan produk estetika postmodern non-intentionality (yang rusak dan melawan Alkitab). Karya seperti HPSCHD menggambarkan kompleksitas kehidupan (yang fragmented dan tidak perlu ada integrasi), suatu bentuk negasi atau perlawanan terhadap one single opinion, karena itu berarti dictatorship. Cage sendiri banyak dipengaruhi oleh estetika Taoisme dan Zen Buddhism. Seorang filsuf bahkan menelusuri kemiripan estetika Cage dengan filsafat dari Martin Heidegger.
Pengujian estetis yang sama kita bisa lakukan terhadap lukisan (abstract) expressionism dari Polluck misalnya atau expressionisme dalam musik Schoenberg, musik bi-tonality, demikian juga dengan jenis musik yang lain. Tidak ada yang bebas dari konsep estetika. Inilah yang membuat musik tidak mungkin netral.
[7]Melakukan pengujian seperti ini selalu tidak mudah dan terutama di jaman yang serba instant, mau langsung jadi, tidak perlu banyak bergumul, over-simplifikasi etc, pengujian seperti ini sangat melelahkan dan dalam natur kita yang lemah kita lebih suka (saya juga!) mencari jalan yang mudah, jalan yang lebar, yang tidak perlu banyak bergumul, tidak perlu banyak belajar, tidak perlu banyak .... pikul salib. Sekarang banyak orang berpikir “atas nama pluralitas” kita melakukan ‘pemutihan’, penetralan segala sesuatu, namun Alkitab memerintahkan kita untuk “menguji segala sesuatu dan memegang yang baik” (I Tes 5:21).
[1] Tentunya tidak salah mengadakan persekutuan kantor atau berdoa sebelum bekerja, itu dapat menjadi hal yang menjadi berkat. Yang saya maksud adalah kalau kita mau memikirkan theology of work secara komprehensif, tidak cukup hanya dengan mengadakan persekutuan kantor saja (memasukkan life sphere ibadah dalam dunia pekerjaan). Pekerjaan itu sendiri harus menjadi suatu ibadah di hadapan Tuhan.
[2] Mengenai pandangan telos seperti yang banyak dianut saat ini sebenarnya merupakan pengaruh dari filsafat utilitarianism dan pragmatisme. Entah kita mau membicarakannya dalam konteks etika Kristen atau tidak, yang jelas ALKITAB membicarakan lebih daripada sekedar tinjauan teleologis. Yesus Kristus tidak hanya memiliki telos yang benar, Dia juga selalu mengerjakan serta mempersembahkan hal yang benar (ini bukan aspek telos tapi merupakan aspek yang lain), dan dia juga selalu memiliki motivasi yang benar. Tiga hal ini dicatat oleh Alkitab sendiri, terlepas dari etika membicarakan ini atau tidak.
[3] Untuk membereskan kesalah-pahaman pandangan karikatural bahwa semua musik ‘klassik’ pasti baik dan bermutu, perbandingan ini akan menyatakan bahwa tidak semua musik dari tradisi ‘klassik’ selalu baik dan membangun.
[4] bagi mereka yang sibuk dan terlalu serius, silakan bagian ini di-skip dan langsung saja pada argumentasi terakhir di akhir paragraf :)
[5] Menanggapi pernyataan Sdr. Jimmy tentang cultural elitist, saya pikir kita perlu membacanya dengan double perspective: di satu sisi para elitists bersalah karena kecenderungan menghina/merendahkan mereka yang memiliki kebudayaan yang lebih rendah karena ini sebenarnya merupakan penyangkalan dari teologia anugerah: “Apakah yang engkau miliki yang tidak engkau terima (dari Tuhan)?” Persoalan para elitists adalah kekurangan spirit inkarnasi; namun di sisi yang lain pandangan yang mengatakan bahwa kebudayaan tertentu memang higher dan lebih berkualitas/bermutu daripada kebudayaan yang lain adalah pendapat yang tidak salah. Mengatakan semua kebudayaan (musik termasuk di dalamnya) tidak memiliki perbedaan kualitas merupakan either ignorance atau penipuan diri.
[6] Tidak sulit untuk membayangkan karya ini: seorang performer berdiri di atas panggung selama empat menit tigapuluhtiga detik tanpa memainkan suatu nada. Yang terdengar di situ adalah mungkin suara audience yang sedang gelisah dan iri terhadap seorang musician yang makan gaji buta.
[7] Analogi bahasa seperti diusulkan oleh Sdr. Jimmy kurang memadai untuk menggambarkan ketidak-netralan musik/seni/culture. Tapi seandainya analogi ini (bahasa) tetap dipertahankan, kita tahu bahwa dalam bahasa apa pun di dunia ini ada kata-kata makian, kata-kata yang mengekspresikan kebencian yang berdosa, kata-kata yang menghujat dsb. Kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut tidak mungkin tidak, harus dikuduskan dan tidak layak dipergunakan untuk memuji Tuhan. Bahasa pun (meskipun sekali lagi sebagai analogi untuk musik sangat lemah dan tidak memadai) ternyata tidak senetral yang kita pikirkan. Bahasa, sebagai salah satu modus dalam hidup manusia, tidak luput dari pencemaran dosa. Bahasa juga perlu dikuduskan oleh Firman Tuhan.
Iman Kristen dan Musik (5)
Hari ini saya ingin sharing sedikit tentang perkembangan musik yang terjadi di jaman Middle Ages. Sayang warisan seni dalam bidang musik tidak banyak dirayakan dibandingkan dengan seni-seni yang lain (kemungkinan besar kita akan lebih kagum memandangi Kathedral di Köln, Ulm, Sainte-Chapelle di Paris atau Duomo di Milano daripada mendengarkan sebuah Gregorian Chant). Beberapa orang bahkan mengatakan jenis musik seperti ini sebenarnya masih belum berkembang alias primitif sehingga sulit untuk diapresiasi. Dalam ibadah, apalagi dalam kalangan gereja-gereja Injili, sedikit sekali (kalau tidak mau dikatakan hampir tidak ada) jenis-jenis lagu Gregorian yang masih dinyanyikan dalam ibadah. Mungkin hampir satu-satunya yang paling populer adalah O come, O come, Emmanuel.
Lagu-lagu Gregorian ditulis monophonic, satu suara tanpa iringan, tanpa melodi tandingan, meskipun tentunya bisa dinyanyikan bersama-sama. Ada keindahan tersendiri dalam karya-karya ini, dengan suatu penggarapan konsep estetika yang berbeda sebagaimana dimengerti oleh jaman-jaman selanjutnya. Salah satu aspek estetika yang ditonjolkan dalam karya-karya ini adalah kesederhanaan iman (simplicity of faith) yang dituangkan dalam gaya musik satu suara, sulit untuk ditandingi dengan musik-musik polyphonic atau homophonic (meskipun tentunya karya-karya polyphonic dan homophonic memiliki keunikannya tersendiri yang juga sulit untuk diterapkan dalam karya seperti Gregorian chant).
Penggunaan tangga nada modus dan bukan mayor-minor seperti yang ada pada jaman-jaman selanjutnya juga memiliki keunikan tersendiri. Tangga nada modus to certain extent menyajikan perbedaan yang lebih kaya dibandingkan tangga nada mayor-minor (yang hanya dua macam). Modus-modus yang beraneka ragam ini bagaikan warna dalam sebuah lukisan. Bahkan komponis-komponis Renaissance awal masih berpikir dalam tatanan tangga nada modus, meskipun mereka sudah menulis musik polyphonic yang progresif.
Selain kesederhanaan iman yang dituangkan dalam gaya musik monophonic dan kekayaan nuansa dalam tangga nada modus, keindahan estetika dalam musik ini adalah terkandungnya potensi yang besar untuk berkembang/dikembangkan. Kita bisa membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran yang besar biasanya ditandai dengan tidak berhentinya pikiran-pikiran tersebut, melainkan dengan memberikan inspirasi kepada yang membacanya untuk bukan hanya mengolah melainkan juga mengembangkannya lebih lanjut. Khotbah-khotbah yang baik juga demikian, tidak hanya memberikan solusi how-to terhadap pergumulan hidup seseorang, melainkan merangsang pendengarnya untuk terus menggumulkan, memikirkan dan merenungkannya lebih lanjut. Potensi sedemikian hanya mungkin terjadi dari bahan dasar yang memiliki kualitas yang cukup untuk dikembangkan. Kita tahu bahwa Gregorian Chant ini menjadi inspirasi karya-karya polyphonic di kemudian hari dalam penggarapan teknik komposisi cantus firmus (melodi utama) seperti ternyata dalam karya Leoninus, Perotinus dan Guillaume de Machaut pada jaman Abad Pertengahan.
Selain kesederhanaan iman, kekayaan nuansa dalam tangga nada modus dan kemungkinan potensi untuk terus berkembang, musik-musik Gregorian Chant juga menonjolkan aspek transendensi Allah, kekudusan, kemuliaan dan kebesaran Allah yang dimengerti secara antitetis dengan keadaan manusia sebagai ciptaan yang kecil, hina dan berdosa (Yes 6:1-5). Konsep transendensi Allah ini sejalan dengan perkembangan Theologia Mistik dalam abad pertengahan (sebagian sangat baik sebagian lagi tidak), khususnya dalam gerakan monastik, dan juga sejalan dengan komposisi arsitektural yang ternyata dalam katedral-katedral Gotik yang menjulang tinggi ke atas. Konsep transendensi Allah seperti diajarkan oleh Alkitab penting untuk terus diberitakan, karena hanya dengan menekankan imanensi-Nya (kedekatan) saja, kita cenderung kurang menghargai Allah. Konsep transendensi dalam Gregorian Chant ini erat hubungannya dengan eschatological character, other-worldly nuance yang terdapat dalam karya-karya ini. Tidak heran jika banyak musikus-musikus kontemporer yang mencoba untuk menimba dari Gregorian Chant untuk meminjam suasana mistik yang ada di dalamnya. Beberapa groups pop and rock, techno dan bahkan black metal menimba inspirasi dari Gregorian Chant. Yang ironis adalah, orang-orang Kristen sendiri tidak tahu bagaimana harus menghargai tradisi musik yang sangat berharga ini dan menggunakannya untuk tujuan yang mulia.
Transendensi Allah, kesadaran eskatologis (bahwa kita hanya sementara berada dalam dunia yang fana ini) dan other-worldly character dari Gregorian Chant memiliki keindahan estetika yang unik yang memperkaya pengertian iman Kristen. Penghayatan iman seperti ini berkait erat dengan suatu hidup yang berserah sepenuhnya (absolute surrender/totale Gelassenheit), another rare jewel in our post-industrial era yang dengan pandangan reduktifnya memperlakukan manusia sebagai mesin produksi. Sekaligus jenis musik seperti ini juga dapat menjadi alternativ tandingan terhadap new age culture (baik itu praktek-praktek meditasi transendental, musik-musik new age, pengembangan diri ala new age, pengolahannya dalam film, literatur etc). New age aesthetics mengajarkan bad and wrong aesthetics, karena presuposisi dasarnya memang melawan Alkitab. Estetika yang keliru dan berdosa akan menghasilkan musik yang keliru dan berdosa. Kehausan spiritualitas di dalam jaman kita (saya percaya bukan hanya di Barat tapi di Timur juga) tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Jikalau keKristenan tidak tahu menghargai tradisi yang baik sebagaimana pernah Tuhan karuniakan dalam sejarah Gereja, saya khawatir kita akan mencoba pendekatan trial and error terhadap semua jenis culture yang ada, tanpa melakukan suatu pengujian yang bertanggung jawab sebagai seorang percaya yang mengaku dan berkomitmen untuk taat kepada Firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita yang sangat lemah. Sola Gratia, Soli Deo Gloria.
Iman Kristen dan Musik (6)—Diskusi
(Sdr. Jimmy—S dan Pdt. Billy Kristanto—B)
J :
Sekali lagi, saya angkat topi utk upaya kamu meninjau masalah ini dari seluruh dimensi yg penting... Tidak disangkal lagi, kamu sangat bertanggung jawab dan serius mendalami hal ini... Kami semua dapat belajar banyak dari kamu... Pembahasan kamu menyegarkan motivasi saya utk belajar lbh serius lagi...
B :
Saya pikir diskusi ini juga mempertajam dan memperjelas kesimpang-siuran konsep tentang musik gerejawi yang banyak dianut, sekalipun mungkin kita belum bisa 100% sependapat.
J :
Satu pertanyaan saja karena saya belum menemukan jawabannya secara lugas dalam pembahasan kamu: Apa properties dari suatu jenis musik yang memungkinkan kita melakukan pengkategorian musik yang kudus atau tidak (selain teks, apalagi)?
Saya setuju bahwa dari sudut pandang estetika, maka ada kemungkinan bahwa jenis musik tertentu (seperti Klasik) adalah high-art. Mungkin inilah perbedaan kita berdua. Kamu berangkat dari estetika. Sedangkan saya berangkat dari preferensi musikal manusianya.
B :
As you already noticed, pengujian musik yang good or bad, atau lebih baik: better and worst.
[1] Pengujian ini terutama dilakukan dengan menyelidiki estetika musik tersebut.
[2] Tentang approach (pendekatan) tentunya bisa beraneka-ragam dan tidak mutlak, namun kita harus selalu ingat bahwa ketika kita membicarakan “starting point” (bukan “approach”) maka hanya ada satu-satunya starting point yaitu penilaian dari Alkitab sendiri. Persoalan berangkat dari preferensi musikal bagi saya adalah ini bukan hanya sekedar perbedaan approach (which I have no problem at all with), melainkan sudah berurusan dengan “starting point”. Preferensi musikal ini berangkat dari diri sebagai subyek yang menyukai musik tertentu (saya suka musik A, kamu musik B, yang lain lagi musik C dan seterusnya). Dengan kata lain starting pointnya masih berada di bawah tradisi filsafat Cartesian (Rene Descartes). Kita tahu bahwa pengaruh Descartes dan Kant (yang mulai dari diri manusia sebagai subyek) hanya membawa kepada agnostisisme, skeptisisme, relativisme, dan terakhir (menurut Hauerwas) nihilism. Kalau kita mulai starting point dari diri (padahal kita tahu diri kita berdosa dan tidak sempurna) maka yang akan terjadi adalah “you can choose whatever you like, what you think is best and good for you”. Starting point dari diri (manusia) pasti tidak akan ada jalan temu karena setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri. Musicology yang dimulai dengan starting point diri bukan jalan dari Alkitab tetapi dari Descartes and co.
Sebaliknya ketika kita melakukan penyelidikan estetis, kita percaya bahwa terlepas dari selera musik saya secara pribadi, ya, terlepas dari pendapat saya sebagai manusia yang berdosa dan tidak sempurna, Alkitab memberikan prinsip-prinsip tentang apa itu keindahan. Dengan kata lain, Alkitab membicarakan tentang estetika. Menurut Fil 4:8 ada kaitan antara keindahan (aspek estetik) dengan kebenaran, kemuliaan, keadilan, kesucian dsb). Apa yang indah adalah apa yang kudus dan apa yang benar. Sehingga musik yang indah (menurut kriteria Alkitab) dapat juga dikatakan kudus, musik yang tidak indah adalah tidak kudus dan tidak benar. Di sini kita langsung berbeda dengan para relativist yang mengatakan bahwa indah adalah persoalan selera, tidak bisa diuji etc. Pandangan itu bukan pandangan Alkitab tapi pandangan filsafat dunia.
Bagaimana kita menguji estetika suatu musik tertentu, atau lebih detail, suatu karya komponis tertentu? Untuk suatu pengujian yang lebih kompleks dan komprehensif kita perlu untuk mempelajari musik tersebut terbentuk dari latar belakang yang bagaimana (di sini diperlukan study interdisipliner bidang-bidang yang lain seperti sosiologi, filsafat, kebudayaan dsb). Atau kalau mempelajari estetika komponis tertentu, kita perlu mengetahui biografinya, kepercayaan atau ideologi yang dia anut (saya sudah sharingkan secara singkat di tulisan yang terdahulu tentang John Cage misalnya yang banyak dipengaruhi oleh Zen-Buddhism). Selain itu juga dia berada di bawah pengaruh tradisi apa, adakah pengaruh estetika Kristen dalam tradisi ini? Jika ada, seberapa jauh? Berapa banyak penyimpangannya?
Konsep estetika ini berkaitan dengan penggarapan yang terjadi dalam 5 musical parameter dasar (harmoni, melodi, ritme, dinamika dan suara [Klang]). Estetika tertentu digarap dalam harmoni atau melodi tertentu yang merefleksikan estetika tadi (kembali dalam pembahasan tentang John Cage saya mencoba untuk mensharingkan kaitan antara estetika yang dianut oleh Cage dengan teknik penggarapan komposisi musiknya). Dengan demikian musik tidak mungkin netral. Dan kalau kita menerima pandangan Alkitab tentang keindahan (bukan pandangan relativisme), kita tahu bahwa keindahan memiliki kriteria obyektif dalam suatu pengujian yang dilakukan di bawah terang Alkitab. Yang indah adalah kudus dan benar, yang tidak indah tidak kudus dan tidak benar. Dengan kata lain, there is better aesthetics and worst aesthetics. Estetika tidak relatif menurut konsep Alkitab.
J : Analogi saya sederhana saja. Dalam dunia linguistik pun kita dapat menemukan beberapa bahasa yang jauh lebih tinggi dalam pengungkapan dan kedalaman makna. Contohnya saja bahasa Inggris dan Indonesia lebih unggul Inggris karena memiliki tenses. Sementara bahasa Yunani mungkin lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Ada pula yang bilang bahasa Mandarin lebih tinggi karena kandungan filosofis dalam perkawinan pelbagai karakter yang menghasilkan karakter baru, dsbnya. Namun, apakah dengan demikian kita seharusnya berdoa/berkomunikasi kepada Tuhan dalam bahasa Yunani/Inggris/Mandarin ketimbang Indonesia karena Indonesia lebih inferior?
B:
Kamu mengangkat satu point yang penting di sini (“higher culture”) yang saya percaya akan semakin memperjelas diskusi ini. Mengenai “higher culture” ini saya ada beberapa tanggapan:
1. Saya pribadi lebih suka menggunakan istilah kebudayaan yang lebih kompleks/berbobot dan kebudayaan yang lebih sederhana, instead of high and low. Pembedaan high and low arts bisa membawa orang terjebak dalam spirit cultural elitist yang salah (menghina culture yang lebih rendah), dengan demikian, seperti sudah saya bahas sebelumnya, merupakan ketidak-mengertian terhadap theology of grace. Dalam tradisi Reformed theology orang lebih suka menggunakan istilah kebudayaan yang lebih kompleks di satu sisi dan lebih sederhana di sisi yang lain.
2. Pembedaan ini penting karena adanya konsep takaran yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tidak setiap orang diberikan takaran yang sama, let say, untuk mengecap ‘high’ education, ‘high’ cultural living, ‘high’ civilization dsb. Alkitab mengajarkan agar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan (motivasi, tujuan dan pemberiannya sendiri). “Yang terbaik” yang dimaksud di sini tentunya adalah “yang terbaik yang dapat saya berikan.” Yang terbaik, sesuai dengan takaran yang Tuhan percayakan pada saya. Persoalan yang terjadi pada cultural elitist adalah tidak mengerti bahwa setiap orang memiliki takaran yang berbeda-beda dari Tuhan. Yang penting di sini adalah setiap orang harus jujur dan mengenal diri dengan benar.
3. Namun ini tidak berarti bahwa takaran itu statis dan tidak dapat berubah. Alkitab juga mengajarkan bahwa mereka yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dalam takaran pun terjadi progresi. Point ini juga sama pentingnya dengan point ke-2, karena tanpa pengertian ini kita cenderung menjadikan konsep takaran itu sebagai rasionalisasi untuk mempertahankan status quo alias keengganan untuk bertumbuh dan terus maju. Di sini saya sulit untuk menerima pop-culture karena salah satu kecenderungan yang sangat kuat dalam kebudayaan ini adalah spirit yang suka mempertahankan “lack of depth” yang menjadi karakteristiknya.
[3] Bukan hanya di dalam musik/seni saja, dalam pengenalan akan firman Tuhan juga bisa merembet spirit pop-culture,
[4] dalam filsafat pelayanan juga dapat dipengaruhi oleh pop-culture.
[5] Spirit instant dan mau langsung jadi, “how-to Christianity” yang mau jawaban siap pakai (tanpa harus bergumul) menjadi karakteristik umum di jaman kita sekarang. Sebaliknya jika kita mengikuti Alkitab, kita harus dengan rendah hati untuk terus mau bertumbuh dengan dipercayakan perkara yang lebih besar oleh Tuhan, termasuk di dalamnya pengenalan teologis yang lebih dalam dan lebih kaya akan Firman Tuhan, juga musik yang lebih berbobot dan lebih kompleks yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ini termasuk dalam bagian pertumbuhan yang wajar dalam hidup Kristen.
4. Sekalipun benar memang ada perbedaan seni yang lebih kompleks dan yang lebih sederhana, namun concern saya sebagai orang percaya lebih berurusan dengan apakah suatu karya memiliki good or bad aesthetics daripada ‘high’ or ‘low’ aesthetics. I have no problem at all dengan estetika musik yang lebih sederhana, karena bagi saya, kedua-duanya (musik yang kompleks atau yang sederhana) dapat dipakai oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan bukanlah tingkat kompleksitas musiknya, melainkan estetika yang benar atau tidak. Ada musik yang sangat kompleks estetikanya, and yet bad aesthetics (seperti John Cage misalnya). Sebaliknya ada musik yang lebih sederhana and good aesthetics. Sebagai orang percaya kita mempertahankan yang good aesthetics dan membuang yang bad aesthetics (mengikuti anjuran Paulus untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang baik [I Tes 5:21]). Di sinilah perbedaan kita dengan para cultural elitists karena mereka (para elitists) akan mempertahankan ‘high’ arts dan menghina serta membuang ‘low’ arts. Bagi kita, good aesthetics bisa ada pada karya seni yang kompleks maupun yang lebih sederhana, demikian juga halnya dengan bad aesthetics. Sama halnya dengan perdebatan musik trasional – kontemporer, perdebatan musik dalam kategori ‘high – low’ arts totally miss the point, karena yang dipersoalkan Alkitab adalah benar dan tidak benar, kudus dan tidak kudus (bukan tinggi atau rendah).
[6]Mengenai analogi bahasa, saya sudah pernah singgung bahwa analogi ini lemah dan tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas persoalan dalam pengujian estetika. Mengapa? Karena bahasa lebih bersifat universal, yang paling dasar yang ada pada setiap bangsa/suku. Jika analogi ini tetap mau dipaksakan juga, yang mungkin dapat menjadi perbandingan yang lebih tepat adalah dengan etno-musik, yang juga ada pada setiap bangsa/suku.
[7] Sementara jenis musik seperti Rock, New Age, Expressionism, bi-tonality etc, bukanlah produk universal setiap bangsa (seperti keanekaragaman dalam etno musik misalnya), melainkan merupakan kebudayaan yang lebih banyak berkait dengan ideologi, bahkan agama tertentu. Ini yang membuat kategori jenis musik yang terakhir ini sangat tidak tepat jika dianalogikan dengan bahasa (karena kandungan nilai kepercayaannya yang sangat kuat).
J :
Kembali ke ibadah, saya melihat kesamaan masalah bila kita juga apply cara pikir yg sama. Saya melihat begini: mari kita pakai bahasa musik kita masing-masing... namun tetap terapkan striving for excellence within each categories...
B :
Jika ada seseorang yang dilahirkan dalam ‘bahasa musik’ New Age lalu dia ingin bertumbuh dalam ‘bahasa musik’nya itu dan menggunakannya dalam ibadah, bagaimana respon kita? Saya pribadi sulit dengan hati nurani yang jujur dan bertanggungjawab di hadapan Tuhan mengatakan “silakan saja, itu memang ‘bahasa musik’ kamu …” karena saya tahu musik-musik seperti itu lahir dari pergumulan agamawi yang melawan Tuhan. ‘Bahasa musik’ kita pun tidak netral, dan perlu terus dikuduskan oleh Firman Tuhan.
J :
Saya tidak menolak aspek keunggulan estetika namun itu menjadi tahap berikut, bukan titik awal.... makanya dalam credo saya, quality saya letakan setelah diversity dan love... jika kita mau pakai musik kontemporer, maka berikan musik kontemporer terbaik...
B :
Saya sependapat dengan kamu jika itu berurusan dengan estetika ‘tinggi – rendah’ maka tidak terlalu matters (asal kita tetap memperhatikan bahwa takaran kita bersifat progresif). Tapi itu matters jika berurusan dengan good/bad aesthetics (bagi saya memberikan yang terbaik mencakup pengujian musik yang baik dan benar). Sudah saya bahas di atas bahwa concern kita lebih berurusan dengan good or bad music instead or ‘high/low’ (complex/simple). Dalam konteks yang pertama (good and bad aesthetics), saya sedikit terganggu dengan kalimat di atas bahwa keindahan boleh ditempatkan setelah diversity and love, karena dalam Firman Tuhan kita tidak mendapati bahwa keindahan (yang berkait dengan kebenaran, kekudusan dsb) boleh dibicarakan ‘belakangan’. Sulit untuk mendapati bahwa Firman Tuhan mengajarkan bahwa pluralitas dan kasih lebih dahulu daripada kebenaran, kekudusan, keindahan, kemuliaan dsb.
[8] Bagi saya, semuanya harus diuji, tanpa mendahulukan yang satu dan mengesampingkan yang lain. Dalam Alkitab kebenaran, keindahan, kemuliaan, kekudusan tidak mungkin dipisahkan dari kasih. Kebenaran ada dalam keaneka-ragaman faset (namun ini tidak berarti semua faset dapat ditampung dalam kebenaran), keaneka-ragaman ini dipersatukan oleh kasih, di dalam kebenaran. Mengenal kebenaran berarti menerima keaneka-ragaman di dalam kasih. Ketika kita menomor-duakan kebenaran (yang berkait dengan keindahan, kekudusan, kemuliaan dsb) kita cenderung akan terjebak pada pluralisme yang diajarkan oleh dunia (bukan pluralitas yang diajarkan oleh Alkitab) dan kasih kita akan menjadi kasih yang tidak berkait dengan pengertian (blind love). Sebaliknya hanya menekankan ‘kebenaran’ tanpa bisa menerima keaneka-ragaman di dalam kasih juga bukanlah merupakan pengenalan kebenaran yang sejati. Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar, Allah yang mengasihi, dan Allah di dalam tiga Pribadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Sola scriptura.
In Christ,
one of the greatest sinners, forgiven by God
[1] Seperti sudah saya bahas dalam tulisan yang lalu bahwa tidak ada musik yang sepenuhnya sempurna, demikian juga tidak ada musik yang sepenuhnya rusak dan tidak ada keindahan yang tersisa di dalamnya. Maka kita lebih baik berbicara tentang musik yang lebih baik dan kurang baik, yang lebih alkitabiah dan kurang alkitabiah, dalam berbagai macam tingkat kebaikan atau kerusakan.
[2] Penyelidikan estetis ini bisa terjadi dalam beberapa tahap tentunya, mulai dari tahap yang paling general, seperti misalnya estetika musik Rock, musik Barock, musik medieval, serial music, expressionism, new age etc, atau yang lebih detail misalnya Barock Perancis, Barock Jerman, Italia etc, dan lebih detail lagi dengan menguji estetika per komponis (let say Mozart misalnya), lebih detail lagi: Mozart pada periode kehidupan yang mana, atau lebih detail lagi: per karya, dan lebih detail lagi: bagian tertentu pada karya tertentu. Pengujian estetika yang general mencoba untuk mencari karakteristik umum dari musik yang diuji (misalnya musik Rock, Klassik, Romantik etc), kelemahan dari pengujian yang seperti ini pasti adalah kecenderungan generalisasinya (ini tidak bisa dihindarkan karena memang pengujiannya terjadi pada tahap yang general). Kalau kita mau melakukan pengujian yang lebih kompleks harus bicara lebih detail.
[3] Ini wajar dan dapat dimengerti karena jika goal yang ingin dicapai adalah mendapatkan jangkauan sebanyak-banyaknya maka yang seringkali harus dikompromikan adalah kualitasnya. Pop-culture yang menuju kepada “depth” tidak akan menjadi pop-culture lagi dan akan dituduh menjadi penganut cultural elitist. Bagi saya pilihan cultural elitist di satu sisi dan pop-culture di sisi yang lain, dua-duanya salah. Alkitab memberikan alternatif yang lain mengenai ini yaitu konsep takaran dalam progresi.
[4] Kalimat seperti “Untuk apa susah-susah mempelajari teologi, itu hanya bikin tambah bingung, bahkan sombong, lebih baik kita belajar saling mengasihi saja” saya kuatir tanpa sadar sebenarnya juga dipengaruhi oleh kecenderungan pop-culture yang cenderung menolak untuk belajar lebih dalam dan terus maju. Dalam Alkitab kasih tidak dapat dipisahkan dengan pengertian yang benar, demikian pula sebaliknya.
[5] Misalnya mencoba untuk mendapatkan jiwa sebanyak-banyaknya dengan mengkompromikan kualitas yang ditakar oleh Tuhan.
[6] Tuhan dapat memakai tulisan dengan kapasitas teologi yang sangat kompleks seperti J. Edwards, maupun juga khotbah-khotbah yang sangat sederhana dari D.L. Moody. Tulisan Kant boleh jadi jauh lebih kompleks, lebih ‘tinggi’ daripada Moody namun ini tidak berarti pemikiran Kant lebih benar dan kudus daripada Moody hanya karena dia lebih kompleks. Pengujiannya adalah kesetiaan kepada Firman Tuhan (entah kompleks atau sederhana).
[7] Ini pun bagi saya juga tidak dapat diakomodasi begitu saja sebagai totally neutral tanpa critical reflection terlebih dahulu. Di satu sisi kita percaya seperti diajarkan dalam Reformed Theology, ada anugerah umum dalam setiap kebudayaan, dan di sisi yang lain kita juga tidak boleh melupakan tanpa pencerahan wahyu khusus, pengertian wahyu umum sesungguhnya kabur dan bahkan cenderung ditekan oleh manusia berdosa (Roma 1:21-23). Dalam etno-musik pasti ada respon terhadap pengenalan akan Allah dalam wahyu umum (bayang-bayang dan kabur), namun juga sekaligus produk keberdosaan dan ketidak-taatan manusia.
[8] Sekali lagi menurut Alkitab konsep keindahan tidak dapat dipisahkan dengan kebenaran, kekudusan, kemuliaan dsb.
Iman Kristen dan Musik (7)—Tanya Jawab
(Jawaban Pdt. Billy Kristanto—B terhadap pertanyaan Sdr. Hansel—H)
Hansel :
Shalom Pak Billy,
Saudara berkata bahwa untuk menguji estetika jenis musik tertentu, kita harus mempelajari latar belakang musik tersebut. Satu pertanyaan saya belum terjawab bahkan setelah membaca 6 email tentang musik yang Saudara post. "Apakah yang Alkitab katakan tentang musik yang kudus dan tidak kudus?"
Billy:
Saya sudah coba sharingkan prinsip ini, sayang sekali Anda tidak menangkap pointnya :)
H :
Mempelajari latar belakang sebuah musik dan kemudian mendasarkan keputusan kita berdasarkan latar belakang tersebut berarti kita mendasarkan keputusan kita pada apa yang kita tahu, dan bukan pada Alkitab.
B :
Di sini Anda salah mengerti. Mempelajari latar belakang, biografi, tradisi musik yang mempengaruhi suatu karya tertentu perlu untuk suatu penyelidikan yang lebih komprehensif, setelah itu pengujian tersebut dibawa dan diuji di bawah terang Alkitab.
H :
Beberapa minggu yang lalu, ada juga yang menge-post soal musik. Dan pendapat dia bahkan jauh lebih ekstrim. Dia seolah-olah berkata hanya musik hymne sajalah yang paling baik. Ketika kita menyanyi untuk Tuhan, kita sama sekali tidak boleh bergoyang. Karena itu, lagu "Oh, betapa indahnya," yang dinyanyikan dengan irama dangdut adalah lagu yang tidak kudus. Tetapi, tidak ada ayat Alkitab sama sekali di dalam email yang dia kirim itu. Berbicara soal bergoyang, tahukah Saudara bahwa Raja Daud pernah memuji dan menyanyi untuk Tuhan sambil menari dan meloncat sekuat tenaga? Tetapi anehnya, Tuhan tidak pernah sama sekali menegur dia untuk tidak menari dan meloncat.
B :
Bagian ini ditujukan kepada saya? Kalau kepada saya: Ya, sebagai hamba Tuhan, puji syukur saya mengenal bagian Alkitab tsb :)
Hanya saja kesimpulan seperti ini bagi saya terlalu cepat dan cenderung menimbulkan pengertian yang salah. Kesulitan penafsiran Alkitab yang seperti ini adalah kerancuan dan kegagalan untuk membedakan bagian Firman Tuhan yang bersifat preskriptif (pengajaran) dan deskriptif (penggambaran). Bagian yang preskriptif berlaku bagi semua orang percaya, bagian deskriptif adalah khusus/unik terjadi pada orang tersebut. Petrus berjalan di atas air sebagai suatu tindakan iman (deskriptif), bukan berarti setiap orang percaya boleh berjalan di atas air sebagai tindakan imannya.
H :
Saya ingin jawaban yang saya dapatkan benar-benar dari Alkitab, dan bukan dari teologi ini dan itu. Terus terang, saya tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang teologi. Yang saya tahu dan kenal sebagai sumber segala kebenaran hanyalah Alkitab.
B :
Tidak mungkin kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang teologi. Seringkali tanpa sadar kita banyak dipengaruhi oleh school of thought theologi tertentu. Statement Anda "Yang saya tahu dan kenal sebagai sumber segala kebenaran hanyalah Alkitab" juga berada di bawah pengaruh tradisi theologi tertentu :)
Mengenai gerakan tubuh dalam ibadah, perlu dipikirkan suatu pembahasan yang mengaitkan antara sikap hati dan filsafat tubuh. Pembahasan ini akan menarik jika dikaitkan dengan thema ekspresi. Untuk sederhananya, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita masing-masing untuk melakukan suatu pengujian:
- Apakah saya menganggap ekspresi itu sebagai sesuatu yang tabu dan tidak alkitabiah?
[1]- Apakah gerakan tubuh/ekspresi yang saya lakukan itu berkaitan dengan apa yang menjadi isi hati saya? (dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan kritik kepada orang Farisi yang menyalahgunakan ekspresi sebagai suatu kemunafikan, precisely karena apa yang tampak di luar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati).
- Apakah ekspresi yang dituangkan dalam gerakan tubuh tersebut bersifat self-centered (saya harus mengekspresikan diri saya) atau God-centered (ekspresi itu sebagai respon kita menikmati Tuhan dalam ibadah).
[2]- Apakah ekspresi atau gerakan tubuh itu membangun sesama jemaat (dan bukan hanya membangun diri saya saja). Bahwa prinsip membangun jemaat lebih baik dan lebih dewasa, lebih sesuai dengan natur kasih daripada hanya membangun diri sendiri, dapat kita pelajari dari I Kor 14:1-5, terutama karena pembahasan ini ada dalam konteks ibadah (pertemuan bersama).
- Apakah ekspresi/gerakan tubuh itu berlangsung dalam batasan kesopanan dan keteraturan (I Kor 14:26-40).
Tuhan memberkati kita sekalian. Semper reformanda.
Yours in Christ.
[1] Jika kita cenderung berpendapat ya, kita perlu berhati-hati dan kritis terhadap pandangan seperti itu, karena pandangan yang mengaitkan kekudusan atau kerohanian yang tinggi dengan semakin meninggalkan ekspresi tubuh lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno daripada Alkitab.
[2] Di sini sebagai orang percaya kita perlu berhati-hati dan membedakan dengan kritis ekspresi yang diajarkan oleh Alkitab dengan ekspresi seperti yang dimengerti oleh aliran expressionisme (yang terakhir ini berpusat kepada diri).
Billy Kristanto
=
http://www.grii.de/ =
Quis credidit auditui nostro? et brachium Domini cui revelatum est? (Is. 53:1)
Sumber :
http://groups.yahoo.com/group/METAMORPHE (mailinglist)
Profil Pdt. Billy Kristanto :
Pdt. Billy Kristanto, Dipl.Mus., M.C.S. lahir pada tahun 1970 di Surabaya. Sejak di sekolah minggu mengambil bagian dalam pelayanan musik gerejawi. Setelah lulus SMA melanjutkan study musik di Hochschule der Künste di Berlin majoring in harpsichord (Cembalo) di bawah Prof. Mitzi Meyerson (1990-96).
Setelah lulus dari situ melanjutkan post-graduate study di Koninklijk Conservatorium (Royal Conservatory) di Den Haag, a conservatory with the largest early music department in the world (mempelajari historical performance practice). Belajar di bawah Ton Koopman, seorang dirigen, organis, cembalis dan musicolog yang sangat ahli dalam interpretasi karya J.S. Bach. Selain itu juga mempelajari fortepiano di bawah Prof. Stanley Hoogland.
Setelah lulus dari situ pada tahun 1998 pulang ke Indonesia, lalu melayani sebagai Penginjil Musik di Gereja Reformed Injili Indonesia/GRII di Jakarta (Februari 1999). Pada tahun yang sama memulai study Teologi di Institut Reformed di Jakarta. Lulus pada tahun 2002 dengan Master of Christian Studies (M.C.S.). Sejak tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan School of Music di Institut Reformed Jakarta serta menggembalakan jemaat Mimbar Reformed Injili Indonesia (MRII) Jerman : Berlin, Hamburg dan Munich. Beliau ditahbiskan menjadi pendeta sinode GRII pada Paskah 2005 dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral di bidang filsafat di Universitas Heidelberg, Jerman.