oleh : Denny Teguh Sutandio, S.S.
“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;” (Amsal 3:5-7)
Krisis Pendidikan Abad Postmodern : Relativisme dan Superioritas Rasio dan Akibatnya
Saat ini kita sedang hidup di suatu era yang disebut postmodern yang menjunjung tinggi relativisme yang mengajarkan bahwa segala sesuatu itu relatif. Dengan fondasi relativisme, maka tidak usah heran, di dalam dunia kita, hampir mayoritas orang tidak lagi memegang standar moralitas yang baik. Khususnya, di dalam dunia pendidikan, Prof. David F. Wells, Ph.D. di dalam bukunya No Place For Truth (Tiada Tempat Bagi Kebenaran) mengungkapkan bahwa banyak sekolah tidak lagi mengajarkan apa yang baik dan yang salah, tetapi lebih memilih untuk mengajarkan tentang bagaimana memelihara dan menggali relasi antar manusia. (Wells, 2004, p. 195) Akibatnya, Wells mengungkapkan bahwa di Amerika, angka bunuh diri remaja tertinggi di dunia, begitu juga pemakaian obat-obatan terlarang, dll. (Wells, 2004, p. 198) Selain relativisme, dunia postmodern yang mengimpor ide filsafat modernisme tentang rasio sebagai “sumber” pengetahuan juga tetap menjunjung tinggi fungsi rasio. Sehingga di dalam dunia pendidikan saat ini, para pakar pendidikan menyuarakan akademis. Di kampus-kampus, semua dosen diselipkan semua gelar akademis yang diraihnya yang membuktikan bahwa semua dosen itu “pintar”. Memang tidak 100% salah ketika para dosen itu dicantumkan gelar akademis, tetapi seringkali yang terjadi, karena bergelar akademis, banyak dosen menjadi sombong dan merasa diri pintar. Nah, jika saya boleh menggabungkan, maka di dalam abad postmodern, dunia pendidikan sedang berusaha menggabungkan konsep relativisme dan superioritas rasio manusia. Relativisme di dalam dunia pendidikan ditandai dengan tidak adanya standar moralitas ditambah adanya rasio yang dijadikan penentu apakah suatu tindakan itu baik atau tidak. Jadi, akademis di dalam dunia pendidikan berhak menentukan standar nilainya sendiri bahkan di luar Allah. Tidak heran, ketika ada seorang dosen “Kristen” di salah satu universitas swasta terkenal di Surabaya mengajarkan bahwa agama dan ilmu tidak ada hubungannya. Proposisi ini berangkat dari presuposisi bahwa akademis menentukan standar nilainya sendiri dan agama tidak ada hubungannya atau tidak boleh mencampuri wilayah akademis. Juga tidak usah heran, ketika seorang dosen “Kristen” mengajarkan bahwa moralitas itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana. Akibatnya, dari kecil, siswa didik tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan ajarkan, sehingga tidak usah heran, banyak anak-anak muda menjadi ateis, kehilangan jati diri, dll, meskipun pada usia anak-anak, mereka bahkan aktif di dalam kegiatan sekolah minggu.
Selain itu, relativisme yang meniadakan (mengaburkan) standar moralitas dan diganti dengan superioritas rasio sebagai standar “kebenaran” diwujudnyatakan melalui sikap individualisme dan kompromi. Prof. David F. Wells, Ph.D. di dalam bukunya No Place for Truth (Tiada Tempat Bagi Kebenaran) mengatakan, “...individualisme dan kompromi sebagai dua karakter Amerika yang mendasar...Individualisme telah menyebar seiring dengan menyebarnya modernisasi, yang menjangkau jauh di luar Amerika. Dan psikologi kompromi timbul dimana masyarakat massa terbentuk...” (Wells, 2004, p. 160) Saya dapat menafsirkan bahwa kedua filsafat ini sebenarnya bukan hanya menjadi karakter Amerika, tetapi karakter postmodernisme yang juga ditandai dengan semangat humanisme atheistik ditambah semangat pluralisme yang ekstrim. Sehingga tidak usah heran, para pendidik baik sekuler maupun yang mengaku diri “Kristen” masih tetap mengajarkan kedua konsep ini. Saya sendiri mendengar seorang dosen “Kristen” yang mengajar saya di bidang Penelitian Kebudayaan dan bergelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Amerika Serikat mengatakan bahwa dirinya bisa belajar dari para mahasiswanya (selain mahasiswa belajar dari dosen) tentang suatu kebudayaan. Tetapi benarkah ini merupakan ketulusan dan kejujurannya ? Mari kita meneliti ulang pernyataannya. Ketika saya mengajukan suatu topik yang bertemakan analisa terhadap gaya ibadat gereja kontemporer yang bisa berakibat fatal di dalam keKristenan, tiba-tiba dosen ini “menyarankan” kepada saya bahwa saya tidak boleh mengadakan “penghakiman” terhadap sesuatu sebelum melakukan suatu penelitian. Dengan kata lain, tidak boleh ada presuposisi di balik sebuah penelitian. Bukankah dengan mengatakan ini, sebenarnya dosen saya sedang mengajukan presuposisi bahwa tidak boleh presuposisi di balik penelitian ? Sungguh, suatu kontradiksi yang aneh. Tetapi saya tidak mendengarkan “saran” dari dosen saya karena “saran” itu aneh. Saya tetap meneruskan makalah saya dan akhirnya saya mendapat nilai C. Setelah mengetahui nilai ini, saya baru berpikir ulang, apakah benar dosen saya ini benar-benar ingin belajar dari mahasiswanya tentang kebudayaan ? Bagi saya, tidak. Mengapa ? Kalau memang benar bahwa dosen saya bisa belajar dari para mahasiswanya, mengapa saya tidak diizinkan memakai suatu presuposisi di balik penelitian kebudayaan yang sebenarnya harus ia pelajari juga ? Bagi saya, dosen itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa dirinya bisa belajar dari para mahasiswanya (kompromi) asalkan itu cocok dengan paradigmanya (bukan paradigma kebenaran sejati) (individualisme/humanisme atheistik). Itulah relativisme yang dimonopoli oleh superioritas rasio manusia yang mengakibatkan timbulnya individualisme dan kompromi di dalam diri para pendidik. Dan lebih parah lagi, kemunafikan itu sangat berakibat fatal, yaitu mengajarkan para mahasiswa untuk bersikap netral. Artinya, di dalam suatu penelitian, misalnya penelitian tentang budaya free-sex atau feminisme yang sering dianggap buruk, para mahasiswa tidak boleh langsung “menghakimi” dan harus berusaha open-minded (berpikiran terbuka) terhadap semua hasil penelitian yang didapat. Dengan kata lain, mereka harus berkompromi terhadap segala sesuatu sekaligus menjadikan diri mereka (bukan Firman Tuhan) sebagai penentu mana yang harus mereka pilih (individualisme/humanisme atheistik).
Pewujudnyataan relativisme dan superioritas rasio di dalam dunia pendidikan akademis juga bisa berupa kesombongan para akademisi. Mengapa saya mengatakan sombong ? Karena mereka sudah kuliah bahkan di Amerika/luar negeri dan menyandang gelar yang tinggi, lalu mereka menyombongkan diri bahwa diri mereka hebat. Yang lebih parah lagi, ada dosen “Kristen” senior yang hanya lulusan S-1 di Indonesia tidak mau ditegur tetapi suka mengoreksi orang lain bukan dengan dasar Firman, tetapi dasar psikologi massa. Bukan hanya itu saja, banyak para akademisi menjadi sombong karena mereka sudah berpengalaman alias senior. Banyak dosen senior merasa diri sudah paling tua, lalu sombong menghina dosen lain yang masih junior bahkan menghina para siswa didik. Tidak heran, kalau dari kecil sampai mahasiswa, pengajaran dan pendidikan yang didapat adalah bagaimana seseorang menjadi pintar/hebat dan kemudian tidak lagi memperdulikan orang lain (konsep Übermensch ala F. Nietzsche yang bahkan tidak memerlukan/memperdulikan Tuhan). Akibatnya, ketika seseorang sudah lulus dari perkuliahan dan bekerja, ia tidak mau lagi ditegur oleh atasannya atau orangtuanya atau sahabatnya ketika dirinya berbuat salah.
Penyebab Timbulnya Krisis Pendidikan Di dalam Dunia Postmodern
Pendidikan di abad postmodern ini bisa mengalami krisis di mana relativisme yang dimuati oleh superioritas rasio disebabkan oleh satu prinsip dasar yaitu hilangnya standar kebenaran. Hilangnya standar kebenaran dimulai sejak kitab Kejadian, ketika manusia memberontak terhadap Allah (berdosa). Rev. Prof. Cornelius Van Til, Ph.D. di dalam bukunya The Defense of The Faith menyatakan, “When man fell it was therefore his attempt to do without God in every respect ... God had interpreted the universe for him, or we may say man had interpreted the universe under the direction of God, but now he sought to interpret the universe without reference to God... The result for man was that he made for himself a false ideal of knowledge.” (Ketika manusia berbuat dosa, itu karena usahanya untuk berbuat tanpa Allah dalam setiap hal... Allah telah menjelaskan/menginterpretasikan alam semesta bagi manusia atau kita dapat mengatakan manusia telah menjelaskan/menginterpretasikan alam semesta di bawah perintah Allah, tetapi sekarang manusia berusaha untuk menjelaskan/menginterpretasikan alam semesta tanpa petunjuk Allah ; ... Hasil bagi manusia adalah bahwa dia menghasilkan bagi dirinya sebuah idaman pengetahuan yang salah.) (Van Til, 1955, p. 15) Bagi Van Til, pada saat manusia berdosa, pada saat yang sama juga mereka sedang mencari standar kebenaran di luar Allah. Pencarian ini bukan mengakibatkan mereka menemukan kebenaran, tetapi kesesatan yang diklaim sebagai “kebenaran”. Kesesatan yang diklaim sebagai “kebenaran” dapat berupa pemutlakkan rasio sebagai “sumber” kebenaran (rasionalisme) maupun pemujaan manusia menggantikan Allah (humanisme ateis).
Hikmat Sejati : Takut akan Tuhan dan Percaya Di dalam Tuhan
Ketika dunia kita mencoba mencari jati diri dan hikmat, mereka dijamin tidak dapat menemukan hikmat sejati di luar Allah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya memperoleh hikmat sejati adalah dari Allah. Penulis kitab Amsal adalah seorang raja yang berbijaksana, yaitu Raja Salomo (Amsal 1:1). Berbeda dari banyak manusia postmodern yang pandai lalu sombong, Salomo tidak sombong karena kebijaksanaannya, ia masih berpegang kepada Tuhan. Hal ini ditunjukkannya pada penuturannya pada pasal 1 ayat 7, “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.” Kata “takut” dalam bahasa Ibrani yir'âh bisa berarti fear (takut) atau morally reverence (penghormatan moral). Lalu, kata “permulaan” bisa berarti first (yang pertama/utama). Jadi, Amsal 1:7 hendak berbicara mengenai menghormati atau taat kepada-Nya adalah hal yang paling utama di dalam pengetahuan. Alasan kita harus takut kepada Tuhan dijelaskan Salomo pada pasal 2 ayat 6, “Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian.” Kata “kepandaian” di dalam terjemahan King James Version adalah understanding yang berarti pengertian. Berarti di dalam Amsal 2:6 ini, Salomo ingin menjelaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala hikmat, pengetahuan dan pengertian, sehingga semua pengetahuan sejati bersumber dari-Nya saja. Bukan hanya takut atau taat kepada-Nya, Raja Salomo memberikan penjelasan lagi di dalam pasal 3 ayat 5 yaitu, “Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.” Atau menurut terjemahan King James Version, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menaruh iman kita di dalam Tuhan dengan seluruh hati kita dan kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bagi Salomo, hikmat sejati bukan hanya sekadar takut akan Tuhan, tetapi percaya di dalam Tuhan. Tindakan percaya di dalam Tuhan bukan hanya sekadar diucapkan di mulut saja, tetapi keluar dari hati dan keluar melalui komitmen hidup kita.
Di dalam komitmen kita untuk percaya di dalam-Nya, kita harus mengerti empat definisi yang dijabarkan Salomo mengenai percaya di dalam Tuhan :
· “Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.”
Ketika anak Tuhan percaya di dalam-Nya, berarti iman itu bukan iman yang bersandar di dalam diri sendiri, tetapi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di dalam pengertian Alkitab yang menyeluruh, iman tidak pernah disamakan dengan ajaran berpikir positif yang diajarkan di dalam abad postmodern ini. Dalam bahasa Yunaninya, iman adalah pistis yang berarti reliance upon Christ (bergantung kepada Kristus). Ketika kita bergantung kepada Kristus, pertama, secara otomatis kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mengapa? Karena ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, sebenarnya kita sedang mengilahkan diri sendiri sebagai “sumber” kebenaran, padahal Alkitab menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa (Roma 3:23). Lalu, kalau manusia sudah berdosa, berarti apapun yang dihasilkan manusia pasti mengandung bibit dosa (meskipun tidak semua). Ini berarti kerusakan total manusia begitu fatal sehingga sungguh suatu absurditas jika manusia masih menganggap diri hebat tanpa Allah. Kedua, kita hanya mengandalkan Kristus di dalam hidup kita. Artinya, di dalam hidup kita, Kristus memerintah sebagai Raja yang menentukan langkah hidup kita, bahkan termasuk di dalam wilayah studi, pekerjaan, dll. Sudah seharusnya anak-anak Tuhan sejati bukan hidup dualisme dengan memisahkan antara wilayah supranatural dengan natural (karena itu ajaran filsus atheis Yunani, Plato) dan mulai taat dan bergantung kepada Kristus dengan mereferensikan segala sesuatu dari sudut pandang Kristus (Christ-centered education). Christ-centered education berarti pendidikan Kristen sejati harus berpusat kepada Kristus sebagai Tuhan. Artinya, ketika kita belajar tentang hubungan sosial (misalnya antar teman/saudara), kita mereferensikannya dengan dwi natur Kristus yaitu sebagai Allah yang transenden (berdaulat/tidak kompromi) sekaligus imanen (yang mengasihi). Lalu, kita juga mereferensikan pernikahan dengan hubungan Kristus dan jemaat. Selain itu, kita juga mereferensikan semua logi di bawah terang Logos itu, yaitu Kristus. Sehingga para siswa didik belajar dan mengetahui bahwa segala sesuatu ada bukan secara kebetulan tetapi atas kehendak dan kedaulatan-Nya saja di dalam Kristus (Yohanes 1:3-4).
· “Akuilah Dia dalam segala lakumu,...”
Percaya di dalam Tuhan juga bisa berarti mengakui dan menyatakan-Nya di dalam segala kehidupan kita. Kata “akuilah” dalam terjemahan King James Version (KJV) dan English Standard Version (ESV) memakai kata acknowledge yang bisa berarti mengakui atau menyatakan. Berarti, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sehari-hari, kita tidak hanya dituntut untuk mengakui Tuhan, tetapi juga menyatakan-Nya. Mengakui dan menyatakan adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita hanya mengakui-Nya, berarti kita hanya pasif, tetapi kita berusaha menyatakan-Nya, berarti kita aktif memberitakan-Nya. Dengan kata lain, dengan kita menyatakan Kristus di dalam hidup kita, kita sedang offensive (bersifat menyerang). Ini berarti di dalam kepercayaan kita di dalam-Nya, ada unsur perjuangan memberitakan-Nya. Di dalam iman Kristen sejati, kita dituntut untuk berani membedakan mana yang benar dan salah (Roma 12:2), berani menguji segala sesuatu dan memegang yang baik (1 Tesalonika 5:21) dan juga berani menyatakan kepada orang lain mana yang benar dan salah dengan kasih/kesabaran dan pengajaran (2 Timotius 4:2). Itulah jiwa offensive di dalam iman Kristen. Iman yang tidak mau berjuang memberitakan-Nya bukan iman sejati, tetapi iman palsu. Sungguh sangat disayangkan banyak orang “Kristen” mengaku diri beriman “Kristen”, tetapi masih berpikiran dualisme atheistik yang tidak mau menyinggung nama Tuhan di luar gereja. Ketika kita mengakui dan menyatakan-Nya di dalam hidup kita, Ia berjanji, “Ia akan meluruskan jalanmu.” Kata “meluruskan” dalam terjemahan KJV yaitu direct bisa berarti menunjukkan. Berarti, ketika kita berada di dalam jalan-Nya dengan mengakui dan menyatakan-Nya di dalam hidup kita sehari-hari, maka Ia adalah Allah yang setia yang akan menunjukkan jalan kita menuju jalan yang dikehendaki-Nya. Ini adalah reward yang kita peroleh setelah kita beriman. Tetapi sayangnya banyak orang dunia (bahkan banyak orang “Kristen”) mau reward (atau dapat disebut hak) tetapi tidak mau mengerjakan kewajiban. Sudah saatnya, anak-anak Tuhan sejati mulai belajar mengerjakan kewajibannya dengan takut akan Tuhan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan yang akan menyempurnakannya. Di dalam dunia pendidikan pun, anak-anak Tuhan harus berani menyuarakan berita kenabian tentang pentingnya integrasi iman Kristen di dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan bukan lagi berdasarkan psikologi dan manajemen, tetapi berdasarkan Firman Tuhan yang akan memimpin jalan hidup umat pilihan-Nya.
· “Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak,”
Selain mengakui dan menyatakan-Nya di dalam hidup kita, percaya di dalam-Nya bisa berarti tidak menganggap diri sendiri bijak (atau memiliki kerendahan hati). Ayat ini di dalam terjemahan KJV, “Be not wise in thine own eyes:” yang berarti janganlah bijak di dalam pandangan matamu sendiri atau jangan menganggap dirimu bijaksana (TB). Ini berarti dengan percaya di dalam Tuhan, kita tidak lagi menyombongkan diri seolah-olah diri kita hebat, pandai, bijaksana, dll, sedangkan orang lain tidak seperti kita, bahkan yang lebih parah Tuhan pun “dihakimi” kita yang sok pintar. Dengan kata lain, percaya di dalam Tuhan identik dengan pembentukan kerendahan hati. Orang yang percaya di dalam Tuhan tetapi masih menganggap diri hebat, sangat perlu diragukan imannya. Sebaliknya, ketika orang percaya di dalam Tuhan, ia sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah yang memampukan dia untuk melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan-Nya (Efesus 2:10 ; Roma 11:36). Inilah kerendahan hati sejati. Di dalam dunia pendidikan, para pendidik dan siswa didik diharapkan juga memiliki kerendahan hati, yaitu mau dikoreksi oleh kebenaran Firman Tuhan (Alkitab) jika ada kesalahan. Pengoreksian ini adalah pengoreksian yang membangun supaya khususnya para siswa didik memiliki dasar, tujuan dan semangat yang jelas yaitu di dalam Tuhan ketika menjalani hidupnya sehari-hari. Tetapi herannya banyak pendidik “Kristen” bahkan siswa “Kristen” tidak mau memakai Firman Tuhan sebagai sumber pengetahuan, tetapi intuisinya ditambah manajemen dan psikologi. Akibatnya, tidak usah heran, tingkat bunuh diri, narkoba, free-sex bukan menurun, tetapi tambah naik. Adalah lebih bijaksana ketika kita belajar dari Raja Salomo yang menegur kita di dalam Pengkhotbah 12:12-13, “Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.” Kedua ayat yang ditulis oleh Raja Salomo ini mengajarkan kepada kita bahwa orang bijak seperti Salomo pun mengakui bahwa hikmat yang diperolehnya pun sia-sia jika tidak ada takut akan Allah. Bukankah seharusnya umat pilihan-Nya di dalam Kristus pun harus rendah hati mengakui bahwa hikmat yang diperolehnya adalah anugerah Allah yang harus dipertanggungjawabkan untuk memuliakan Allah.
· “takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;”
Terakhir, di dalam percaya di dalam Tuhan, ada unsur takut akan Tuhan yang menjauhi kejahatan. Inilah yang saya sebut sebagai circular understanding (pengertian yang melingkar). Artinya, ketika kita takut akan Tuhan, kita percaya di dalam-Nya dan percaya di dalam-Nya mengakibatkan kita semakin takut akan Tuhan. Takut di sini tidak sama dengan sikap takut ketika seseorang dikejar setan. Takut di sini berarti ada suatu sikap gemetar sekaligus sukacita ketika datang di hadapan-Nya. Tidak ada ajaran filsafat maupun agama apapun yang mampu mengajarkan bahwa ketika kita datang ke hadapan-Nya ada rasa sukacita sekaligus takut/gemetar, karena hanya Alkitab saja yang mengajarkan keseimbangan antara transendensi Allah yang berdaulat dan imanensi Allah di dalam pribadi Kristus yang berinkarnasi. Hal ini juga mengakibatkan kita taat menjalankan kehendak-Nya dengan sukacita dan rela hati sekaligus gemetar/takut. Di dalam dunia pendidikan, para siswa didik harus diajar bagaimana mereka harus takut akan Tuhan bukan hanya pada waktu di gereja saja, tetapi juga di dalam sekolah (aspek transendensi Allah), di mana mereka harus membangun semua pengetahuan di bawah terang Firman Allah. Selain itu, di dalam aspek imanensi Allah, para siswa didik harus dididik bagaimana mereka bergumul sendiri dengan Allah tentang panggilan-Nya di dalam hidup mereka. Dengan kata lain, saya menggabungkan unsur rohaniah dan jasmaniah di dalam dunia pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen yang tidak menggarap dua unsur ini secara terkait (yang juga merupakan unsur di dalam pribadi manusia, yaitu tubuh dan jiwa) bukanlah pendidikan “Kristen” meskipun menyandang gelar “Kristen”.
Takut akan Tuhan juga diwujudnyatakan dengan suatu sikap yang semakin membenci dosa, yaitu menjauhi kejahatan. Kata “menjauhi” di dalam bahasa Ibraninya sûr bisa berarti turn off (mematikan). Dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan berarti orang yang juga mematikan dosa/kejahatan. Adalah suatu absurditas yang konyol jika banyak orang “Kristen” bahkan “pemimpin gereja” mengaku diri takut akan Tuhan tetapi masih gemar berbuat dosa. Itu bukan iman Kristen ! Iman Kristen sejati adalah iman Kristen yang mematikan dosa atau jijik melihat dan berbuat dosa. Anak-anak Tuhan membenci dosa bukan karena takut dihukum Tuhan, tetapi atas dorongan pengudusan terus-menerus oleh Roh Kudus yang mengakibatkan mereka melakukan itu dengan suatu kerelaan hati dan sukacita setelah menerima anugerah penebusan Kristus. Di dalam pendidikan Kristen, unsur kekudusan ini harus diajarkan karena Alkitab mengajarkannya. Kekudusan harus diajarkan mulai dari pengajaran tentang kebenaran (baik ilmu maupun kerohanian) dari Firman Tuhan (Alkitab). Saya menyebutnya science sanctification (pengudusan ilmu). Lalu, disusul dengan pendidikan bagaimana membedakan manakah kebenaran dan mana yang tidak. Kemudian, para siswa didik harus diajar bagaimana mereka harus bersikap (memilih) sesudah mereka berani membedakan kebenaran dan kesesatan itu. Terakhir, atas pilihan yang telah mereka ambil, mereka harus diajar untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan.





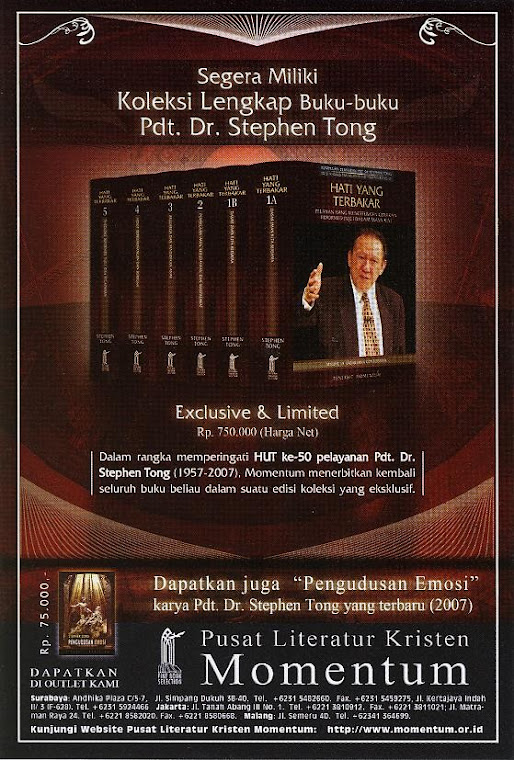
No comments:
Post a Comment